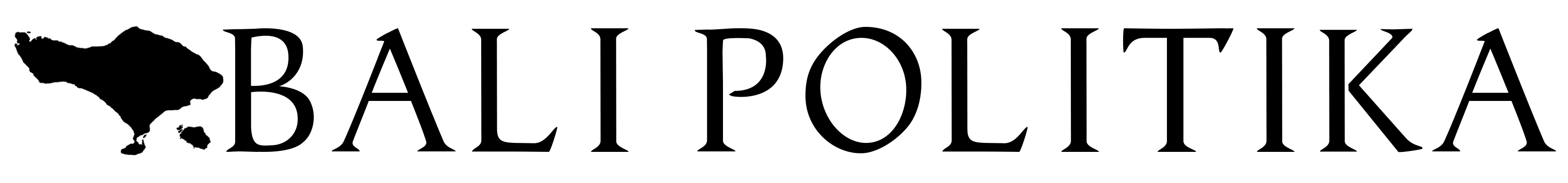“Pak kenapa ya sekarang ini perampasan tanah dan lahan semakin sering dilakukan aparatus negara? Kenapa bukan perampasan aset para koruptor saja yang giat dilakukan oleh para aparat hukum?” Tanya seorang istri pada suaminya.
“Ya lantaran perampasan aset belum atau tak ada landasan hukumnya! Perampasan tanah dan lahan warga ada landasannya! Memang, tidak ada UU Perampasan Aset, karena memang tidak diadakan. Perampasan tanah dan lahan rakyat dilakukan makin sering oleh aparatus negara karena ada UU yang mendasarinya.” Ujar suami.
[Teks di atas adalah dialog singkat yang saya nukil dari status WA Prof Djoko Saryono]
Sejarah manusia, jika diringkas dalam satu garis besar, adalah sejarah perebutan ruang. Dari konflik agraria zaman feodal, kolonialisme yang menancapkan klaim terhadap tanah-tanah jajahan, hingga kapitalisme global yang membangun rezim kepemilikan tanah di atas pondasi eksploitasi, semuanya mengarah pada satu konklusi: tanah bukan sekadar benda mati yang bisa dimiliki, tetapi objek konflik yang menyimpan kenangan panjang.
Dalam percakapan sepasang suami-istri di atas, tersirat kegelisahan yang mendalam. Mengapa negara tampak lebih giat merampas tanah rakyat dibanding merampas aset para koruptor? Jawabannya terletak pada hukum dan kepentingan. Hukum dibuat bukan untuk semua orang secara setara, tetapi sering kali sebagai instrumen politik untuk menjaga status quo.
Michel Foucault dalam Discipline and Punish menyebutkan bahwa kekuasaan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga produktif—ia membentuk realitas, membangun legitimasi, dan mengatur kehidupan sosial. Negara modern bekerja tidak hanya dengan senjata dan militer, tetapi dengan hukum yang menjadi alat pendisiplinan. Ketika tanah dirampas atas nama pembangunan, hukum memberi justifikasi: ini demi kepentingan umum, demi investasi, demi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ketika wacana perampasan aset koruptor mengemuka, yang terjadi justru penundaan demi penundaan. Tidak ada landasan hukum yang dibuat, karena sejak awal tidak ada niat untuk menciptakannya.
Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract pernah mengingatkan, “Manusia terlahir bebas, tetapi di mana-mana ia berada dalam belenggu.” Dalam konteks ini, belenggu itu adalah sistem hukum yang dibuat dengan kesadaran penuh bahwa kepentingan dominan harus tetap lestari. Hukum agraria di banyak negara berkembang tidak hanya mengatur kepemilikan tanah, tetapi juga menjadi alat dominasi kelas penguasa. Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang di satu sisi memberikan harapan terhadap reforma agraria, tetapi di sisi lain tidak pernah benar-benar menjadi fondasi bagi redistribusi tanah yang adil.
Jika tanah adalah artefak yang menyimpan jejak panjang konflik manusia, maka aset koruptor adalah entitas abstrak yang lebih mudah disembunyikan. Tanah memiliki fisik yang bisa diperebutkan, bisa dikuasai secara kasatmata. Sementara aset dalam bentuk rekening luar negeri, properti di luar negeri, atau saham di perusahaan-perusahaan cangkang sulit dijangkau oleh hukum yang telah disesuaikan untuk melindungi oligarki.
Karl Marx dalam Das Kapital telah lama mengkritik bagaimana kapitalisme menciptakan sistem di mana hukum dan ekonomi berjalan dalam simbiosis mutualisme. Perampasan tanah rakyat kerap diklaim sebagai kepentingan pembangunan, sedangkan perampasan aset koruptor menjadi diskursus yang tidak pernah tuntas. Sistem ekonomi neoliberal yang mendominasi kebijakan negara-negara berkembang menempatkan tanah sebagai modal utama untuk pertumbuhan ekonomi, sedangkan kapital dalam bentuk aset keuangan bersifat cair dan bisa berpindah tempat dengan mudah.
Negara kerap menggunakan retorika pembangunan untuk membenarkan tindakan perampasan tanah. Antonio Gramsci dalam konsep hegemoni menyebutkan bahwa negara tidak hanya berkuasa melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan yang dibangun lewat ideologi. Narasi bahwa pembangunan memerlukan pengorbanan rakyat adalah contoh konkret bagaimana negara membentuk opini publik agar tindakan represifnya diterima secara wajar.
Dalam konteks Indonesia, perampasan tanah bukanlah fenomena baru. Dari era kolonial hingga sekarang, rakyat kecil selalu menjadi korban. Kasus-kasus seperti penggusuran lahan di berbagai daerah demi proyek infrastruktur sering kali terjadi tanpa konsultasi yang adil dan transparan. Sementara itu, kasus-kasus besar yang melibatkan korupsi triliunan rupiah seringkali berakhir dengan hukuman ringan atau impunitas. Ini menegaskan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi dalam jaringan kepentingan politik dan ekonomi yang kompleks.
Jika sistem hukum yang ada tidak mampu menyeimbangkan kepentingan rakyat dengan kepentingan elite, maka perlu ada desakan terhadap perubahan paradigma. Pertama, harus ada keberanian politik untuk merumuskan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya sistematis dalam memberantas korupsi. Kedua, reforma agraria yang sejati harus dikawal bukan hanya dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, tetapi juga dengan gerakan sosial yang kuat untuk memastikan tanah tidak menjadi alat akumulasi segelintir orang.
Walter Benjamin dalam Theses on the Philosophy of History menyatakan bahwa setiap peristiwa sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengingat dan memaknainya. Jika perampasan tanah terus terjadi dan perampasan aset koruptor terus diabaikan, maka sejarah hanya akan menjadi pengulangan dari ketidakadilan yang sama.
Sejarah bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dapat diubah. Pertanyaannya: apakah kita masih memiliki daya untuk menuntut perubahan, atau kita hanya menjadi saksi pasif dari perampasan yang terus berulang?
Jika sejarah perampasan tanah dan impunitas atas aset koruptor terus berulang, bukankah ini pertanda bahwa kita tengah terperangkap dalam lingkaran sistem yang tak berpihak pada keadilan? Jika hukum, yang seharusnya menjadi pilar keadilan, justru digunakan sebagai alat legitimasi bagi ketimpangan, bagaimana kita dapat berharap pada perubahan yang nyata?
Sejarah mengajarkan bahwa ketidakadilan tidak akan terkoreksi dengan sendirinya. Ia harus digugat, dipertanyakan, dan dilawan dengan kesadaran kolektif. Setiap generasi menghadapi tantangan moral yang menuntut keberanian untuk bersikap. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan menjadi saksi pasif dari pengulangan ketidakadilan ini, atau kita berani menuntut perubahan?
Lebih jauh, kita harus bertanya: apakah pembangunan yang mengorbankan mereka yang lemah benar-benar layak disebut kemajuan? Apakah pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan hak-hak rakyat kecil dapat disebut sebagai keberhasilan? Ataukah kita justru telah terbiasa dengan ketidakadilan yang tersamarkan dalam retorika pembangunan dan hukum yang timpang?
Dalam dunia yang terus berubah, di mana nilai-nilai keadilan kerap ditentukan oleh kepentingan segelintir orang, barangkali pertanyaan paling penting bukanlah apakah sistem ini akan berubah, tetapi apakah kita bersedia untuk memperjuangkan perubahan itu? Sejarah bukan sekadar kisah yang kita baca—ia adalah sesuatu yang kita tulis bersama. Maka, bagaimana kita ingin dikenang oleh generasi mendatang? Sebagai mereka yang diam di tengah ketidakadilan, atau sebagai mereka yang berani menuntut dunia yang lebih adil. (*)
BIODATA
Fileski Walidha Tanjung adalah seorang penulis kelahiran Madiun, 21 Februari 1988. Karyanya berupa puisi, cerpen, dan esai telah dimuat di berbagai media nasional dan internasional.