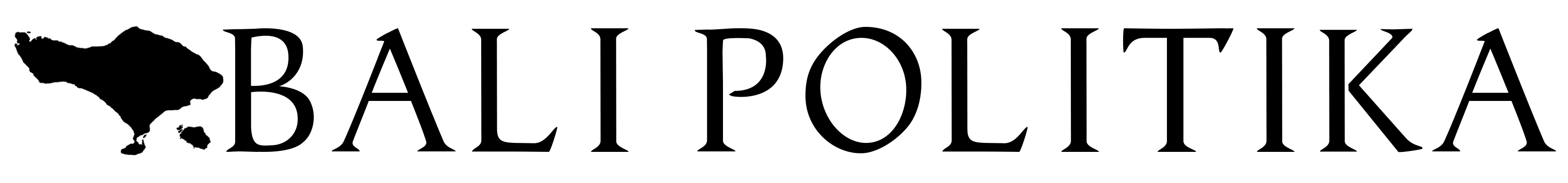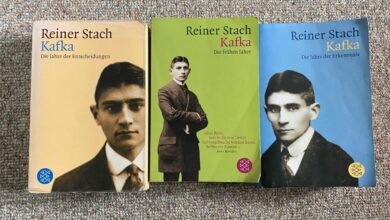Sapardi Djoko Damono, sastrawan dan kritikus sastra kenamaan Indonesia, pernah menyatakan bahwa “Sastra adalah cara yang paling halus untuk memahami kehidupan manusia. Melalui sastra, kita belajar tentang kompleksitas jiwa manusia yang tidak bisa dipelajari dari buku pelajaran biasa.” Ungkapan ini menyoroti peran unik sastra sebagai medium yang bukan hanya menyampaikan cerita, tetapi juga membuka ruang refleksi mendalam atas keberadaan manusia.
Berbeda dengan buku pelajaran yang cenderung menyampaikan fakta dan teori secara sistematis, karya sastra mengajak pembaca menyelami pengalaman emosional, konflik batin, dan dinamika sosial yang kompleks. Dalam puisi, cerpen, atau novel, pembaca tidak hanya mengenal tokoh-tokoh fiktif, tetapi juga bercermin pada diri sendiri. Melalui pergulatan tokoh-tokohnya, sastra memperlihatkan betapa rumitnya perasaan, nilai, dan pilihan hidup manusia.
Dengan membaca sastra, kita mengasah empati dan kepekaan terhadap penderitaan maupun kebahagiaan orang lain. Kita belajar melihat dunia dari perspektif yang berbeda, memperluas wawasan tanpa harus mengalaminya secara langsung. Inilah kekuatan halus dari sastra—ia tidak menggurui, tetapi menyentuh. Ia tidak memaksa, tetapi menggugah.
Maka, dalam dunia yang semakin teknokratis dan serba instan, sastra tetap relevan sebagai sarana penting untuk memahami dimensi terdalam dari kehidupan manusia. Seperti yang dikatakan Sapardi, sastra membuka jendela menuju kompleksitas jiwa yang tak terjangkau oleh pelajaran biasa.
Membaca karya sastra bukan sekadar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi merupakan proses pembelajaran yang mendalam tentang kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, serta pengembangan daya pikir dan rasa. Bagi siswa, keterlibatan dengan sastra memberikan kesempatan untuk memahami berbagai karakter, latar sosial, dan konflik batin yang memperkaya empati serta daya nalar kritis. Kafka menyatakan bahwa “buku yang baik harus menjadi kapak untuk memecahkan laut beku dalam diri kita.” Karya sastra membantu siswa menggali sisi terdalam dari dirinya sendiri dan orang lain, sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan teks informatif atau materi ajar konvensional.
Selain itu, keterlibatan siswa dengan sastra sejak dini membantu mereka mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih tajam dan ekspresif. Sastra memperkenalkan gaya bahasa, simbolisme, dan struktur naratif yang memperkaya kemampuan komunikasi lisan maupun tulisan. Ketika siswa terbiasa dengan keragaman bentuk dan makna dalam teks sastra, mereka menjadi lebih terampil dalam menafsirkan dan menyampaikan ide secara kreatif. Hal ini sangat penting di tengah tantangan literasi yang masih rendah di banyak wilayah Indonesia. Kurikulum Merdeka yang kini diterapkan bahkan menekankan pentingnya profil pelajar Pancasila, termasuk kemampuan berpikir kritis dan berakhlak mulia—dua hal yang bisa diperkuat melalui pembacaan karya sastra.
Peran guru dalam konteks ini menjadi sangat sentral. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, melainkan fasilitator yang menghidupkan teks sastra di hadapan siswa. Mereka harus mampu membangun suasana apresiatif di kelas, bukan menjadikan sastra sebagai hafalan semata. Sebagaimana diungkapkan Goenawan Mohamad, “Sastra adalah cara lain untuk memerdekakan pikiran.” Guru perlu memperlakukan sastra sebagai ruang pembebasan kreativitas dan pemikiran kritis siswa, bukan sebagai beban ujian. Dalam Kurikulum Merdeka, guru juga didorong untuk merancang pembelajaran berbasis proyek literasi yang kontekstual dan bermakna bagi siswa.
Untuk mendukung tujuan ini, pemilihan karya sastra yang sesuai usia dan relevan dengan kehidupan siswa menjadi kunci. Misalnya, di tingkat SMP, puisi-puisi sederhana Sapardi Djoko Damono seperti “Hujan Bulan Juni” bisa memperkenalkan keindahan bahasa dan kesunyian perasaan secara halus. Di tingkat SMA, cerpen “Robohnya Surau Kami” karya A.A. Navis atau novel “Laskar Pelangi” karya Andrea Hirata dapat digunakan untuk memicu diskusi tentang keadilan sosial, pendidikan, dan impian. Guru bisa memanfaatkan kegiatan seperti pembacaan puisi bersama, diskusi nilai-nilai dalam cerita, atau proyek menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi siswa untuk menanamkan kecintaan terhadap sastra.
Dengan demikian, pentingnya membaca karya sastra bagi siswa terletak pada kemampuannya membentuk pribadi yang lebih peka, cerdas secara emosional, dan berdaya nalar tinggi. Guru memiliki peran strategis dalam menanamkan fondasi ini sejak dini, sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif pembelajaran. Melalui sastra, pendidikan tidak hanya mendidik akal, tetapi juga membentuk jiwa. Dalam dunia yang penuh tantangan dan kompleksitas, sastra adalah bekal yang tidak ternilai.
Di tengah arus deras digitalisasi, pembelajaran yang serba instan, dan tekanan kurikulum yang seringkali mengejar target kuantitatif, keberadaan sastra dalam dunia pendidikan justru semakin penting dan mendesak untuk diperjuangkan. Kita tengah menghadapi generasi yang tumbuh dengan paparan informasi berlimpah, tetapi seringkali miskin kedalaman rasa dan ketajaman makna. Di sinilah urgensi membaca karya sastra muncul—bukan sebagai pelengkap kurikulum, tetapi sebagai fondasi pembentukan karakter dan kesadaran moral. Sastra mengajarkan kita untuk jeda, merenung, dan mendengar suara-suara yang tidak terdengar dalam percakapan sehari-hari: suara kegelisahan, empati, harapan, dan kemanusiaan.
Jika kita ingin mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga matang secara emosional dan sosial, maka memberi ruang bagi sastra di ruang-ruang kelas adalah langkah yang tak bisa ditawar. Guru sebagai ujung tombak transformasi literasi harus diberdayakan untuk menjadi jembatan antara siswa dan dunia sastra—bukan semata-mata dalam bentuk analisis teks, tetapi dalam pengalaman hidup yang melekat pada kata-kata. Menumbuhkan minat membaca sastra berarti membuka ruang untuk dialog antargenerasi, memperkaya imajinasi, dan melatih kepekaan terhadap realitas yang beragam.
Jika bangsa ini masih percaya pada pendidikan sebagai jalan menciptakan manusia utuh, maka sudah saatnya kita menempatkan sastra di posisi yang strategis, bukan marjinal. Karena seperti yang dikatakan Sapardi Djoko Damono, “Sastra adalah cara yang paling halus untuk memahami kehidupan manusia.” Dan dalam dunia yang semakin keras, justru kehalusan itu yang paling kita butuhkan.
Di tengah dunia pendidikan yang semakin pragmatis dan terukur lewat angka, sastra justru menawarkan sesuatu yang tak bisa dihitung—kepekaan, empati, dan pemahaman terhadap kompleksitas manusia. Ketika siswa dicekoki hafalan dan target ujian, mereka kehilangan ruang untuk bertanya tentang makna, tentang nilai, dan tentang siapa mereka sebenarnya. Membaca karya sastra bukanlah aktivitas pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak di tengah krisis nalar dan kepekaan sosial yang kita lihat hari ini.
Kita membutuhkan lebih banyak siswa yang mampu memahami orang lain, bukan hanya menjawab soal pilihan ganda. Kita memerlukan ruang kelas yang membicarakan puisi dan cerita pendek, bukan hanya silabus dan kisi-kisi ujian. Dan untuk itu, peran guru menjadi sangat penting. Guru harus menjadi pintu pembuka ke dunia sastra—dengan pendekatan yang kontekstual, menyenangkan, dan membebaskan. Dalam semangat Kurikulum Merdeka, inilah saatnya guru dan sekolah benar-benar memerdekakan pikiran siswa melalui sastra.
Jika kita ingin pendidikan Indonesia benar-benar melahirkan manusia utuh—bukan sekadar lulusan yang bisa menghafal dan menghitung—maka kita perlu memberi tempat yang layak bagi sastra. Karena seperti kata Sapardi Djoko Damono, “Sastra adalah cara paling halus untuk memahami kehidupan manusia.” Dan dalam dunia yang semakin gaduh dan tergesa-gesa, kehalusan dalam memahami sesama adalah hal yang langka, sekaligus sangat dibutuhkan.
*Penulis merupakan pengajar bahasa dan sastra Indonesia di salah satu perguruan tinggi di Lamongan.