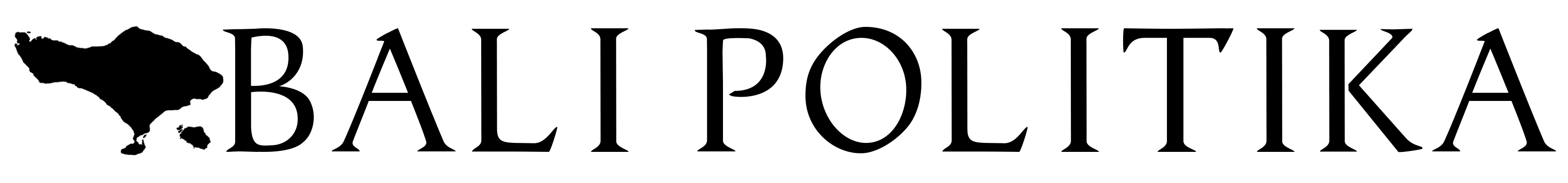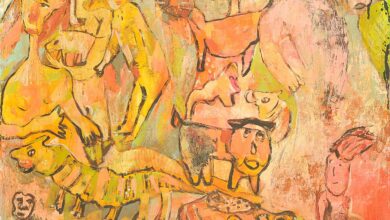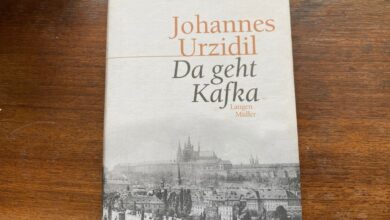BALI bukan hanya pulau seribu pura, tetapi juga nusa beribu-ribu pustaka. Pustaka dari berlapis-lapis zaman diwariskan, direka ulang, kemudian ditubuhkan dalam setiap tapak kehidupan manusia di pulau mungil ini.
Rajapurana Pura Ulun Danu Batur (selanjutnya ditulis Rajapurana Batur) adalah satu dari tebaran pustaka penting yang sampai kepada kita saat ini. Seperti namanya, Rajapurana Batur merupakan sekumpulan naskah lontar yang disimpan dan disucikan di Pura Ulun Danu Batur, Desa Adat Batur, Kintamani, Bangli, Bali.
Lontar-lontar tersebut oleh masyarakat setempat acapkali disebut Sanghyang Rajapurana atau Bhatara Rajapurana. Penyebutan itu menegaskan arti penting sekaligus penghormatan masyarakat terhadap setiap figur aksara yang tergurat dalam lembar-lembar lontar Rajapurana Batur.
Rajapurana Batur tidak saja dianggap penting oleh masyarakat adat dalam zona wilayah adat karaman Batur. Melampaui batas kawasan, teks-teks ini juga bernilai penting bagi masyarakat Batun Sendi Batur—desa-desa aliansi ring satu Batur—serta masyarakat Pasihan Ida Bhatari Sakti Batur—jaringan subak yang berorientasi pada Pura Ulun Danu Batur.
Tigabelas Cakep yang Diwariskan
Rajapurana Batur terdiri atas 13 cakep lontar yang tersimpan dengan baik di Pura Ulun Danu Batur. Naskah ini hanya akan dikeluarkan dalam pelaksanaan ritual-ritual penting di pura tersebut. Sebagai naskah yang penting, lontar-lontar tersebut telah dialihaksara pada tahun 1979 oleh Museum Bali, dibuatkan duplikat berbahan tembaga oleh Desa Adat Batur, serta digitalisasi oleh Desa Adat Batur bekerja sama dengan Unit Lontar Universitas Udayana pada tahun 2023 lalu.
Naskah lontar Rajapurana Batur berjumlah 13 cakep (bendel) yang dapat dibagi ke dalam tiga kelompok wacana besar. Naskah terbanyak berkaitan dengan ketetapan-ketetapan yang harus dipatuhi masyarakat. Kelompok ini diklasifikasikan sebagai pangeling-eling, antara lain naskah yang diidentifikasi oleh Budiastra, dkk. (1979) dengan judul: (1) Pangeling-eling Wong Batur; (2) Pangeling-eling Gaman Desa; (3) Pangeling-eling Dane Saya; (4) Pangeling-eling Klian Tumpuk (naskah a); (5) Pangeling-eling Klian Tumpuk (naskah b); (6) Gama Patemon; dan (7) Pungga Habanta.
Kelompok kedua adalah naskah-naskah yang berkaitan dengan tatanan keagamaan serta pelaksanaan upacara di tempat suci. Kelompok naskah ini dikelompokkan sebagai teks pangaci-aci, yang terdiri atas naskah berjudul Wedalan Ratu Pingit, Pratekaning Usana Siwa Sasana, Pangaci-aci Ida Bhatara, dan Babad Patisora.
Kelompok ketiga merupakan naskah-naskah dengan narasi cerita epik-mitologis (purana), yang terdiri atas naskah berjudul Tutur Usana Bali dan Purana Tattwa. Bagian awal Babad Patisora juga dapat dikategorikan sebagai teks purana karena menceritakan kisah mitologi Pulau Bali, khususnya dalam hal kebencanaan.
Secara umum, tahun penulisan naskah lontar Rajapurana Batur tidak tertulis dengan jelas. Dari 13 naskah yang ada, 12 naskah tidak memberi keterangan tentang tahun penulisannya. Hanya ada satu naskah yang menuliskan tahun penyalinaan, yakni naskah berjudul Pangeling-eling Klian Tumpuk (naskah b).
Naskah Pangeling-eling Klian Tumpuk (naskah b) merupakan naskah salinan dari cakep lontar berjudul sama (naskah a) yang selesai disalin pada hari Paniron, Selasa Paing Madangkungan, Pananggal ke-4, bulan Asuji (Katiga), tahun 1860 Saka. Apabila dikonversi ke penanggalan Masehi, maka hari itu jatuh pada tanggal 30 Agustus 1938. Dengan demikian usianya telah 87 tahun. Apabila dilihat dari kondisinya, saya menduga ini adalah naskah termuda dibandingkan dengan naskah-naskah lainnya.
Penyalin naskah Pangeling-eling Kelian Tumpuk (naskah b) memiliki nama pena Wipraghora Walapurwa. Sang penyalin mengabadikan identitasnya sebagai seorang brahmana dari Griya Bukit, Bangli (asrameng Ukir Bangli), yang menyalin lontar Pangeling-eling Kelian Tumpuk (naskah a) atas permintaan masyarakat Batur, pascarelokasi kawasan akibat bencana erupsi Gunung Batur tahun 1926.
Ketakwaan Berbasis Lingkungan
Ada sejumlah teks Rajapurana Batur yang menyinggung konsep ketuhanan yang berbasis pada nilai-nilai lingkungan. Pada tulisan ini akan dibahas dua teks sebagai awalan.
Pertama kita akan menengok Purana Tattwa. Teks ini berbahasa Bali-Kawi. Narasinya bergulat seputar mitologi penciptaan Gunung Batur. Pada katalog Gedong Kirtya Singaraja, kisah yang mirip dengan Purana Tattwa diidentifikasi dengan judul Babad Batur (kode naskah: VA/839/4).
Purana Tattwa menjelaskan bagaimana Gunung Batur tercipta. Konon diceritakan, awalnya di Kaldera Batur (bembengan agung) tidak terdapat gunung. Hanya ada kawah besar bekas pijakan Bhatara Pasupati yang tergenang air.
Beberapa masa kemudian, Ida Bhatari Ayu Mas Membah memilih untuk bersetana di sana. Ida Bhatari disunggi abdinya yang setia, Ki Pucangan. Sesampainya di sana, Ida Bhatari disetanakan di tengah-tengah danau. Saat itulah terjadi peristiwa kosmis berupa dentuman selama 11 hari 11 malam hingga terbentuk gunung yang terus membesar. Pada akhirnya letusan gunung hanya menyisakan sebagian kecil danau di sebelah timur-selatan gunung. Gunung itu adalah Gunung Batur yang disucikan sebagai kahyangan Ida Bhatari Mas Membah.
Selain membuat gunung, selanjurnya diciptakan mata air bernama Tirta Mas Mampeh. Air ini tercipta dari air suci yang ditempatkan pada seruas bambu. Air Tirta Mas Mampeh diberkati oleh Ida Bhatari Mas Membah sebagai air kehidupan masyarakat agraris di Pulau Bali. Secara spiritual, air suci Tirta Mas Mampeh inilah yang dialirkan ke hilir dalam bentuk mata air-mata air untuk pertanian di subak-subak.
Narasi dalam teks Purana Tattwa beririsan dengan mitos Ida Ratu Ayu Mas Membah yang hidup di beberapa desa di Bali. Kisah ini juga menjadi pengikat hubungan kultural-spiritual antara masyarakat subak dengan Pura Ulun Danu Batur melalui ritus pertanian selama setahun penuh. Puncak relasi ritual ini terjadi pada Ngusaba Kadasa setiap Purnama Kadasa (sekitar bulan April) di mana subak-subak akan mempersembahkan sawinih (hasil panen utama) sebagai bahan upacara Ngusaba Kadasa.
Persembahan sawinih pada prinsipnya adalah ucapan terima kasih atas air dan panen yang melimpah, sehingga petani dan sawahnya tetap hidup. Praktik persembahan sawinih bisa dimaknai sebagai bentuk kesadaran orang Bali atas daur hidrologi, di mana air tidak serta merta menyembul tanpa eksistensi kawasan resapan di kawasan hulu.
Selanjutnya kita bisa memeriksa teks Pratekaning Usana Siwa Sasana. Narasi tentang konservasi lingkungan satu di antaranya termuat pada lembar 11 rekto naskah tersebut yang menjelaskan tata kelola Danau Batur secara lahir-batin.
Teks ini menegaskan danau sebagai ekosistem yang sangat berdampak bagi kehidupan. Maka, seluruh elemen negara—pemerintah (sang mawa rat), pejabat, bangsawan, hingga intelektual—wajib mengambil peran yang dipertanggungjawabkan langsung ke hadapan Sang Ilahi.
Nilai-nilai yang muncul dalam Pratekaning Usana Siwa Sasana dapat ditiru dalam penyikapan krisis lingkungan yang kian masif saat ini. Pada prinsipnya pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab masyarakat di sekitar kawasan, tetapi tanggung jawab bersama. Komitmen pemerintah dalam mengurai persoalan lingkungan adalah keniscayaan. Bukan sekadar omon-omon untuk menarik simpati yang ditebar lima tahun sekali. (*/bp)
BIODATA
I Ketut Eriadi Ariana (Jero Penyarikan Duuran Batur), dosen Sastra Jawa Kuno Universitas Udayana. Pemuda asli Batur yang sejak 2019 terpilih sebagai jero penyarikan duuran (sekretaris adat) di Pura Ulun Danu Batur/Desa Adat Batur. Tertarik pada isu kebudayaan dan ekologi. Menulis buku Ekologisme Batur (2020) dan antologi puisi Bali modern Ulun Danu (2019).