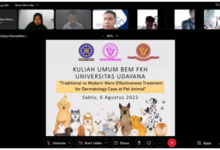ADZAN ashar sudah berkumandang hampir satu jam yang lalu. Namun, aku masih menatap hamparan langit jingga di ufuk barat. Matahari yang beranjak ke peraduan menciptakan lukisan alam berwana kuning keemasan. Kilau cahaya senja yang indah seolah sengaja hadir untuk mengantar kepulangan raja siang serta menyambut kehadiran dewi malam.
Lukisan alam yang mempercantik langit itu juga merupakan simbol kekuasaan Tuhan agar semua makhluk yang tinggal di bumi senantiasa mengagungkan hasil karya Yang Maha Kuasa. Manusia kadang terlalu sombong dengan kepandaiannya sehingga melupakan kodrat sebagai hamba.
Jujur aku sempat heran dengan cara pandang orang jaman dulu. Saat aku masih bocah ingusan, setiap senja datang anak-anak justru dilarang keluar untuk menikmati keindahan. Surub yang diwarnai senja keemasan dianggap sebagai candik ala yang bisa mendatangkan petaka. Ajaran animisme dan dinamisme masih kental.
Swastameta dianggap sebagai gerbang gaib yang mengincar para bocah untuk dibawa ke alam kegelapan. Tidak seperti sekarang, penampakan swastameta atau yang dikenal dengan istilah sunset menjadi buruan orang untuk menikmati panorama alam.
Terlebih bagi orang-orang yang berprofesi sebagai penulis, senja bisa menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya sebuah karya yang memuja keindahan. Namun, kali ini aku sengaja menikmati senja bukan untuk mencari inspirasi, tapi justru sebagai sarana untuk instropeksi diri. Dari sini aku menyadari bahwa memasuki usia senja itu ternyata lebih mengkhawatirkan daripada masuk dunia remaja.
Banyaknya nikmat dunia yang makin berkurang, mengingatkan aku pada jatah usia yang semakin berkurang. Bisa jadi rambut putih yang mulai tumbuh di kepala merupakan teguran dari Tuhan agar diriku mulai meninggalkan dunia hitam dan segera menuju ke dunia putih. Uban sebagai pengingat bahwa masa tenggang hidup tinggal menunggu waktu yang tepat.
Namun, ternyata hal itu tidaklah semudah mengatakannya. Dalam praktiknya di usiaku yang sekarang, masih banyak keinginan duniawi yang ingin aku dapati. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Aku ingin membahagiakan istri dan anakku. Bahkan aku ingin hidupku berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Tapi aku bisa apa? Sebagai penulis kelas teri yang karyanya jarang laku, hal utama yang aku sangat aku inginkan adalah semoga kegiatan menulis itu dapat membawa namaku sebagai penulis ternama di negeri ini.
Aku ingin menjadi penulis dengan karya bestseller yang banyak diburu pembaca di seantero negeri. Dengan begitu, aku akan mampu memenuhi segala keinginanku. Meski faktanya Allah belum meridhoi berjuta keinginanku itu.
“Kang, orang melihat senja itu biasanya kan seneng dan bahagia, tapi kau kok malah sedih gitu, kenapa?” tanya Purwita sambil melongo menatapku.
“Aku gak sedih, Wit. Hanya lagi termenung.”
“Mikir apa?”
“Usia kita yang sudah memasuki senja, sementara dari berjuta keinginanku belum ada satu pun yang terwujud,” sahutku kembali mengarahkan pandangan ke hamparan senja di langit barat.
“Enggak usah bicara puitis gitu, Kang. Sisa umur itu cukup dinikmati, gak perlu dipikiri. Lagipula senja yang ada di langit itu gak sama dengan usia senja manusia. Jadi lebih baik perbanyak bersyukur saja supaya kau gak banyak mengeluh seperti itu,” bantah istriku.
“Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini pasti ada manfaat dan maksudnya. Demikian pula dengan senja yang sedang kita nikmati ini.” Masih saja aku membenarkan tanpa berpaling dari hamparan senja di ufuk barat.
Purwita terdiam. Pandangannya kembali terarah ke ufuk barat. Senja yang perlahan-lahan mulai memudar lebih menyita perhatiannya. Awan kuning kemerahan yang berarak pelan melangutkan jiwanya.
“Termasuk sejuta keinginanmu yang menurutmu belum ada yang terwujud itu.”
“Apa maksudmu berkata seperti itu, Wit?” Dengan terpaksa aku ganti memandang wajah istriku.
“Kang, berdoa tanpa berusaha merupakan suatu kemalasan. Dan berusaha tanpa berdoa itu merupakan kesombongan. Jadi berkacalah pada dirimu sendiri, sudahkah usaha dan doamu itu kau jalankan dengan seimbang?” Wanita yang sudah aku nikahi lebih dari 15 tahun itu menatapku dalam-dalam.
“Ya, seperti yang kau lihat. Setiap hari aku sudah berusaha dan berdoa sekuatku.”
“Yakin, seperti itu?” Purwita menatapku ragu.
Aku mengangguk dengan mantap.
“Buktinya adzan ashar sudah berlalu sejam yang lalu, tapi kau belum juga sholat dan justru masih menatap senja sambil menggerutu. Apa itu namanya seimbang, hah?”
Astagfirllohhaladzim! Aku terperanjat. Benar apa kata istriku, aku memang belum bisa berbuat seimbang antara mengejar keinginan dan melakukan kewajiban sebagai seorang hamba.
“Kang, tidak semua doa itu langsung dikabulkan oleh Alloh. Ada kalanya doa itu ditangguhkan. Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan,” ujar istriku seraya melangkah meninggalkan aku.
Ya Allah, perkataan istriku yang lembut terasa bagai tamparan keras ke wajahku. Sebagai lelaki yang merupakan seorang imam dalam keluarga, tak seharusnya aku menurutkan segala keinginan yang jutaan jumlahnya. Aku harus berusaha membunuh jutaan keinginan yang berlebih itu dengan mensyukuri apa yang ada.
Aku harus meyakinkan diri, bahwa sekecil apa pun perbuatan baik meski sebesar biji sawi, tapi jika dilandasi niat yang tulus, Tuhan pasti akan membalasnya berlipat ganda. Karena Tuhan itu Maha Kaya. Jangankan untuk sejuta keinginan satu orang sepertiku, keinginan seluruh manusia saja Tuhan mampu memenuhinya.
Oh! Serta merta serasa tersentuh jiwaku. Jiwa manusia berusia senja yang harus mulai memikirkan kehidupan setelah dunia. Seketika aku beranjak masuk rumah untuk menunaikan sholat ashar yang waktunya sudah hampir habis.
***
Usai sholat, aku menatap senja yang berarak pelan dan mulai memudar seiring akan datangnya malam yang gelap. Menyaksikan kepergian senja, tiba-tiba saja aku juga merasakan ada sesuatu yang hilang dari diriku. Suatu rasa yang dulu mampu membangkitkan semangat hidup dalam segala suasana. Andai saja aku punya kuasa, ingin rasanya aku tahan semburat senja itu agar tak beranjak dari ufuk barat.
Masih banyak kenangan tentang senja yang ingin aku urai bersama sejuta keinginan yang berlebih di dasar sanubari. Senja yang dulu pernah mempertemukan aku dengan seorang gadis sedikit tomboy yang sekarang menjadi pendamping hidup ini. Senja pula yang dulu mengiringi proklamasi hati saat aku menyatakan niat tulus mencintai Purwita.
Jika saja mungkin, ingin rasanya aku curi sepotong irisan senja untuk kubawa pulang dan kusimpan dalam lemari kayu. Agar setiap saat aku ingin mengenang senja terindah yang pernah kusaksikan, aku tinggal membuka lemari dan mengangkat potongan senja itu dengan kedua telapak tangan.
Namun sayang, aku bukanlah Seno Gumira Ajidarma yang piawai memotong senja untuk disematkan dalam sebuah cerita sebagai bentuk persembahan pada seorang kekasih. Aku hanyalah pemulung kata-kata yang sampai hari ini belum mencicipi manisnya buah ketenaran. Keinginan besar itu masih menggantung di awing-awang. Senja bagiku adalah sebagai penyaksi atas perjalanan hidup yang pernah terlewati bersama Purwita.
“Wita, tolong besok kau masaklah yang enak. Nanti kita makan bersama sambil menikmati senja di pematang sawah,” ujarku suatu ketika.
“Apa? Masak enak? Memang Kang Heru punya uang buat belanja daging agar kita dapat masak enak dan makan di bawah senja?” Purwita bertanya sambil membelalakkan mata.
Aku menggeleng tanpa dosa.
“Kang, dalam hidup ini ya, lebih baik kita makan lauk garam tapi nyata daripada makan lauk sate tapi hanya mimpi belaka. Jangan sampai kita itu besar pasak daripada tiang, mampu makan enak sambil menikmati senja, tapi duit dari ngutang.” Lanjut Purwita dengan tatapan menghunjam.
“Wita, enak itu bukan berarti mahal. Walaupun kau hanya masak daun singkong dengan lauk kerupuk miskin, tapi selama semua kita lakukan dan nikmati dengan rasa cinta maka kelezatan pun sudah bisa kita dapatkan,” ujarku meyakinkan istri.
“Bilang saja lagi bokek!” cemo’oh Purwita.
Meski begitu, tak urung perempuan kelebihan lemak itu tetap saja menuruti apa yang jadi keinginanku. Wanita itu yakin, bahagia bukan hanya milik orang-orang kaya. Tuhan menciptakan keindahan senja untuk semua makhlukNya yang dapat melihat. Tak terkecuali untuk aku dan Purwita.
Maka siang itu juga aku memetik aneka sayuran dari pekarangan sekitar rumah. Istriku memasak dengan bumbu-bumbu andalan yang diwarisi dari nenek moyang. Ia bikin sayur daun singkong dengan citarasa tinggi. Ia juga masak urap bayam dan daun kenikir. Aku membantunya sebisaku.
Besar harapanku agar saat senja sore nanti, aku dan istri bisa mendapatkan kebahagiaan kembali. Kesulitan ekonomi seringkali membuat kami tak sempat menikmati keindahan senja yang dulu jadi saksi bertautnya dua hati.
Kebahagiaan adalah hak setiap makhluk bernama manusia. Terlebih untuk orang yang mulai memasuki usia senja seperti aku dan istri. Biar saja para orang kaya menikmati senja dengan pergi ke pantai atau tempat-tempat wisata lainnya, aku dan istri menikmati senja cukup dengan cara sederhana.
Tujuan utama kami ingin kembali menikmati senja berdua hanyalah untuk mengenang masa-masa pacaran sebelum semua itu tinggal kenangan. Sekalian sebagai untuk membunuh sejuta keinginan yang berlebih agar kekesalan hidup tak selalu menindih.
***
Aku dan istri menggelar tikar kecil di tepi persawahan. Kami menata bekal makanan yang sudah dipersiapkan dengan posisi menghadap ke barat. Dengan begitu saat senja muncul di langit, kami bisa segera makan berdua sambil menatap senja yang pernah menyatukan kami dalam cinta.
Namun, manusia hanyalah bisa berencana. Keputusan akhir tetap jadi hak Yang Maha Kuasa. Senja yang kunanti belum lagi datang, tiba-tiba langit berselimut mendung hitam. Tak sempat aku dan istri berkemas, hujan sudah turun dengan deras.
Aku yang hampir memasuki usia senja itu gagal menikmati senja bersama istri. Yang aku dapatkan tinggallah omelan Purwita yang dilanda kekesalan tinggi. Aku dihukum cuci perabot kotor yang Purwita pakai masak sehari tadi.
Demi Alloh, memang tragis. Namun, aku tidak mau mengeluh. Sejuta keinginan yang semula ingin kubunuh, nyatanya justru semakin tumbuh. Mungkin benar apa yang dikatakan istriku. Bahwa aku kurang bersyukur.
Mengikuti keinginan, sebelum jasad dikubur di liang lahat tidak akan pernah ada habisnya. Tapi hidup adalah pilihan. Maka sebelum menentukan sejuta keinginan ada baiknya mengukur kemampuan diri yang diberikan Tuhan. Dengan begitu keinginan itu tidak akan membunuh kebahagiaan yang sejatinya bisa didapat dengan cara-cara sederhana.
Sebagai lelaki, aku harus menjadi sosok pengendali agar bahtera rumah tangga tidak sampai kehilangan arah. Aku akan terus berusaha dan berdoa tanpa melupakan rasa syukur atas nikmat yang telah aku terima.
BIODATA
Heru Patria adalah nama pena dari Heru Waluyo. Karya puisi dan cerpennya pernah dimuat diberbagai media cetak dan online. Ia menerima Anugerah Sutasoma 2024 dari Balai Bahasa Jawa Timur. Buku kumpulan cerpennya yang telah terbit: Di Bawah Ketiak Reformasi (2013), Reformasi Setengah Hati (2013), Pijar Lilin di Tengah Hujan (2014), Indahnya Kebersamaan (2015), Dalam Belenggu Reformasi (2015), Read Up Comedy (2016), Opera Sebuah Rasa (2017), Kleptokrasi (2027), Mantra Penolak Corona (2018), Hingga Ujung Waktu (2023), Cita Rasa Cinta (2023).