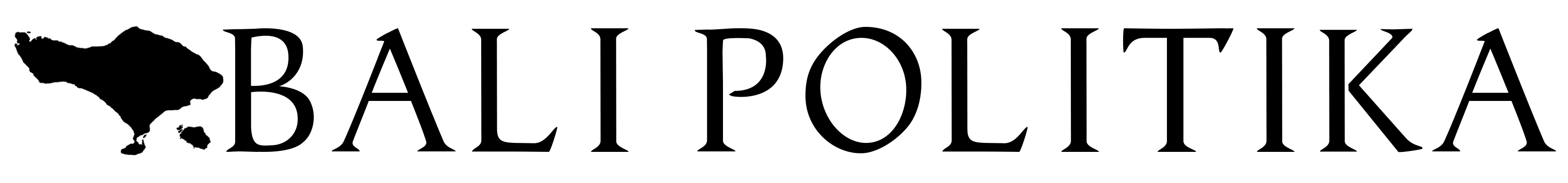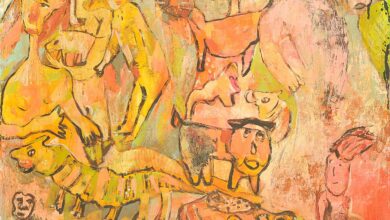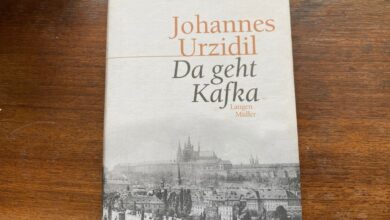SEMENJAK lingusitik dikenal sebagai sebuah ilmu, bahasa senantiasa berada pada ketegangan dan perdebatan yang membawa dua keterbelahan besar. Keterbelahan pertama merupakan aliran yang memandang bahasa sebagai sebatas alat dan mereduksinya menjadi sekedar perkara gramatika. Belahan kedua, aliran yang mencoba memandang bahasa bukan semata-mata persoalan gramatikal tetapi juga refleksi kategori-kategori mental kognitif manusia.
Pada aliran pertama bahasa dilihat sebagai alat analisis terhadap fenomena alam dan diarahkan untuk membongkar rahasianya secara empiris. Pengalaman manusia yang diekspresikan dalam bahasa dianggap tidak memiliki kendala sejauh ia dinyatakan secara logis, sintaksis dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris (Latif,1996:19). Pada titik inilah gramatika menjadi inti perhatian utama dalam analisis bahasa dan terjadi pemisahan yang tegas antara subyek dan obyek. Hubungan antara manusia sebagai subyek dan realitas sebagai obyek yang ‘dibahasakan’ menjadi terabaikan.
Fokus pada gramatika yang mengakibatkan pemisahan subyek-obyek ini melahirkan aliran-aliran baru yang berinduk pada pengikut fenomenologis yang memandang bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas obyektif saja tetapi justru menganggap peran subyek sangat sentral dalam kegiatan berbahasa atau berwacana. Bahasa menurut pemahaman kaum fenomenologi merupakan tindakan penciptaan makna, tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dan bertujuan “sesuatu’ dari si pembicara.
Aliran kedua mencapai puncaknya dengan munculnya posmodernisme yang membongkar sekat antara teori politik dan ilmu bahasa yang sebelumnya merupakan dunia asing yang berbeda. Dalam analisis posmedernisme bahasa bukan semata-mata alat komunikasi atau sebuah sistem kode (nilai) yang secara sewenang-wenang menunjuk sesuatu realitas monolitik. Bahasa adalah suatu kegiatan sosial yang terikat, dikontruksi dan direkontruksi dalam kondisi khusus dan tidak semata-mata tersusun menurut hokum yang diatur secara imiah dan universal.
Dalam kajian Baudrillard dan pakar-pakar posmodernisme lain seperti Gramsci, Ritzer dan Mallinooswky, analisis tentang bahasa, realitas sosial dan kekuasaan memperoleh ruang kerja bersama untuk saling memahami dan menjelaskan perilaku dan kinerjanya masing. Bahasa lebih disikapi dan dipahami dalam perspektif sosial terutama dalam hubungannya dengan aspek-aspek kekuasaan. Dalam hal ini bahasa merupakan teks sedangkan kekuasaan merupakan konteks.
Bahasa Sebagai Simbol
Hayakawa (1994) menjelaskan bahwa proses simbolik ada dan terjadi di mana-mana pada semua tingkat peradaban manusia dari yang paling sederhana sampai pada tingkat yang paling canggih. Simbol sebenarnya merupakan hasil rekaman otak manusia atas pengalaman-pengalamannya dan di dalam otak tersebut pengalaman diterjemahkan menjadi simbol-simbol. Karena itulah lebih lanjut dikatakan oleh Dibyasuharda (Gie,1981) bahwa bentuk simbol adalah penyatuan dua hal yang luluh menjadi satu.
Dalam simbolisasi, subyek menyatukan dua hal menjadi satu atau tunggal. Oleh Susana K. Langer (1989), simbol dibedakan menjadi dua macam, yakni simbol presentasional dan simbol diskursif. Simbol presentasional, simbol yang cara penangkapannya tidak terlampau membutuhkan intelektual. Dengan spontan simbol ini menghadirkan apa yang diakndungnya seperti misalnya alam, lukisan, pahatan dan sebagainya. Makna dari simbol ini ditangkap melalui hubungan antar elemen-elemen simbol dalam struktur keseluruhan.
Sedangkan simbol diskursif adalah simbol yang cara penangkapannya cenderung menggunakan intelektual dan tidak secara spontan tetapi berurutan. Simbol diskursif mempunyai sistem yang tidak dapat diabaikan dan dibangun oleh unsur-unsur menurut perhubungan tertentu yang kemudian baru dapat dipahami maknanya. Bentuk simbol diskursif yang paling lekat dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa yang jelas-jelas mempunyai kontruksi yang konsekuen dan tersusun menurut aturan sintaksis dan gramatikal tertentu sebelum menghasilkan gambaran mengenai suatu kenyataan tertentu. Karena itu dikatakan oleh Hayakawa bahasa adalah bentuk simbol yang paling maju, paling halus, paling canggih dan paling lengkap.
Namun meskipun bahasa mempunyai kompleksitas yang luar biasa tetap diakui bahwa ada bagian penting dari realitas yang sulit ditembus oleh pengaruh formatif bahasa, yaitu wilayah yang disebut pengalaman dalam, ruang hidup perasaan dan emosi yang lebih merupakan kegiatan intersubyektif manusia. Tidak memadainya bahasa untuk menyampaikan pengalaman intersubyektif karena bahasa sebagai sebuah simbol tidak mampu secara sempurna mencerminkan bentuk alamiah perasaan. Sehingga manusia kadang-kadang tidak mampu membentuk konsep-konsep yang terperinci tentang perasaan dengan bantuan bahsa yang wantah.
Bahasa yang dipakai untuk merujuk kepada perasaan hanya mampu memberi penamaan secara umum terhadap pengalaman dalam misalnya: kegairahan, kebahagiaan, ketentraman, cinta, dan sejenisnya. Namun bahasa tidak mampu merincikan bagaimana kebahagiaan berbeda-beda jenisnya, berjenis-jenis kesedihan, dan sebagainya. Pada titik ini terbukti bahwa hakikat alam perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat secara rinci dan tegas dinyatakan dalam simbol diskursif. Oleh karena itu pula oleh para ahli filsafat, fenomena perasaan dan emosi biasanya dianggap sebagai hal yang irasional.
Bahasa: Teks dan Konteks
Halliday (1992) menjelaskan bahwa teks dipahami sebagai bahasa yang sedang berfungsi, atau dengan kata lain bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam situasi tertentu yang tentu saja berlainan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat lepas yang mungkin dituliskan dalam sebuah papan tulis. Berangkat dari penjelasa Halliday ini maka berarti semua bahasa yang sedang digunakan dan ambil bagian tertentu dalam konteks situasi dapat disebut dengan teks, baik itu berwujud tulis atau dapat juga tutur.
Dalam pengertian ini teks tidak dapat dianggap sebagai perpanjangan teori tata bahasa karena memahami teks tidak semata-mata menerjemahkan tetapi lebih kearah menafsirkan. Karena sifatnya sebagai satuan makna, teks melebihi satuan-satuan kebahasaan yang lain dan harus dipandang dari dua sudut secara bersamaan, sebagai produk maupun sebagai proses. Teks merupakan produk dalam arti ia merupakan output yang dapat dipelajari karena mempunyai susuna tertentu yang dapat diungkapkan secara sistematik. Teks merupakan proses dalam arti merupakan proses pemilihan makna terus-menerus, sesuatu perubahan melalui jaringan makna dengan setiap perangkat pilihan yang membentuk suatu lingkungan bagi perangkat yang lebih lanjut.
Dengan demikian teks akan sarat mengemban makna sosial dalam konteks situasi tertentu. Teks adalah hasil dari lingkungannya, hasil suatu proses pemilihan makna yang terus menerus yang dapat diibaratkan sebagai jalan setapak atau jalan kecil melalui jaringan-jaringan yang membentuk suatu sistem kebahasaan. Teks lahir sebagai sebagai sebuah proses dan hasil dari makna sosial dalam konteks situasi tertentu yang terjadi melalui suatu hubungan yang sistematis antara lingkungan sosial di satu pihak dengan organisasi bahasa di lain pihak.
Keberadaan teks yang erat dengan situasi sosial atau konteks teks membutuhkan konsep-konsep untuk menafsirkannya. Konsep-konsep itu oleh Malinowski disebut sebagai medan wacana, pelibat wacana dan sarana wacana.. Medan wacana menunjuk pada hal yang sedang terjadi, pada sifat tindakan sosial yang sedang terjadi, apa yang sedang disisbukkan oleh para pelibat, yang didalamnya bahasa ikut serta sebagai unsur pokok tertentu. Pelibat wacana menunjuk pada orang-orang yang mengambil bagian, sifat para pelibat, kedudukan dan peran mereka, serta jenis-jenis hubungan peran antar pelibat. Sedangkan sarana wacana berkaitan dengan bagian yang diperankan oleh bahasa, hal-hal yang diharapkan (target) para pelibat berkaitan dengan peran bahasa, organisasi simbolik tek dan mode-mode retoriknya.
Dengan adanya unsur teks yang tidak lepas dari konteks situasi sosial itu bahasa menjadi bukan semata-mata alat komunikasi atau sebuah sistem kode ata nilai yang secara sewenang-wenang menunjuk suatu realitas monolitik. Bahasa adalah suatu kegiatan sosial yang terikat dengan setting sosial tertentu dan berbagai kepentingan yang bermain di dalamnya.
Bahasa dan Kekuasaan
Berkaitan dengan teks dan konteks, bahasa dapat dipandang sebagai representasi dari hubungan-hubungan sosial tertentu yang dapat membentuk subyek-subyek, strategi-strategi dan tema-tema wacana tertentu. Akibatnya pula bahasa dapat menjadi ruang pergelaran kuasa-kuasa tertentu dan kepentingan-kepentingan tertentu.
Dengan bahasa manusia mampu melakukan tiga hal yang sangat esensial dalam hidupnya. Pertama, pada tataran paling sederhana dengan bahasa manusia mampu berkomunikasi dengan sesamanya. Kedua, bahasa merupakan landasan utama pada mana gambaran mental internal manusia ditata dalam proses yang disebut berpikir. Dan ketiga, bahasa memungkinakan manusia terlibat dalam proses interaksi sosial, perubahan sosial dan pembentukan arah cita-cita perubahan sosial budaya. Karena itu bahasa tidak hanya dibentuk dan ditentukan tetapi sebaliknya juga mampu membentuk dan menentukan sejarah sosial.
Berkaitan dengan fungsi bahasa dalam proses interaksi dan perubahan sosial, bahasa mempunyai daya pembebasan dan revolusioner. Bahasa mempunyai dimensi emansipatoris dan transformatif sekaligus pula dapat bersifat netral dan bebas nilai. Bahasa dapat menjadi jahat atau buruk kalau diarahkan sebagai media penindasan kesadaran manusia baik secara transparan atau tersirat. Sebaliknya bahasa dapat digunakan sebagai sarana membebaskan kesadaran manusia dari belenggunya.
Keterkaitan atau pengaruh faktor kekuasaan terhadap bahasa menyinggung keterlibatan teks atau wacana dengan kontek yang dipresentasikan dalam universum tanda-tanda yang pada perkembangannya akn diperkuat oleh semiotika. Bahkan dalam pandangan seorang pakar bernama Louis Althusser, teks tidaklah dibentuk oleh subjek sebaliknya subyek dapat dibentuk oleh teks.
Secara historis sebenarnya keterkaitan antara bahasa dengan politik dan kekuasaan telah lama diyakini. Para filosof Yunani memandang bahasa sebagai alat untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran. Dalam pandangan hidup orang Athena abad ke-5 bahasa menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang konkret dan praktis. Bahasa dianggap sebagai senjata ampuh dalam percaturan politik tingkat tinggi. Bahasa juga hadir bersamaan dengan sejarah sosial komunitas-komunitas yang dalam pengertian modern disebut sebagai bangsa. Bahasa tidak saja dipandang sebagai kegiatan personal tetapi juga sebagai kegiatan sosial.
Sebagai representasi dari hubungan-hubungan sosial tertentu, bahasa senatiasa membentuk subyek-subyek, strategi-strategi, dan tema-tema wacana tertentu. Bahasa menjadi ruang bagi pergelaran kuasa-kuasa tertentu yang dapat mengakibatkan punahnya suatu orde tata sosial lama dan terciptanya orde tata sosial baru dengan “bahasa” sebagai rezim yang berkuasa.
Di sisi lain ketegangan antar bahasa dengan kekuasaan menjadikan posisi bahasa menjadi semakin nisbi dan arbiter.Bahkan menurut kaum post-modernisme dengan teori dekontruksinya melaui salah seorang pencetusnya, Derrida, dengan tegas berkeyakinan bahwa bahasa merupakan ruang tafsir yang terbuka.
Menurut kaum dekonstruksi paling tidak tergambar tiga asumsi baru tentang bahasa berkaitan dengan realitas sosial, politik dan kekuasaan. Pertama, bahasa sentiasa ditandai oleh ketidastabilan dan ketidaktetapan makna; kedua, ketidakstabilan dan ketidak tetapan itu menyebabkan tidak ada metode analisis yang memiliki klaim istimewa apa pun atas otoritas dalam kaitannya dengan tafsir bahasa dan tafsir tekstual, dan ketiga, dengan posisi bahasa yang penuh dengan ketidakstabilan dan ketakmapanan, tafsir bahasa adalah kegiatan yang tidak terbatas dan lebih mirip “permainan” daripada sebagai analisis yang kaku.
BIODATA
Tjahjono Widijanto lahir di Ngawi, 18 April 1969. Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Menulis puisi, esai, dan sesekali cerpen di berbagai media nasional. Buku-bukunya berupa kumpulan puisi, kumpulan esai dan kritik sastra, esai sosial budaya, dan cerpen, terbit sejak tahun 1990 hingga sekarang. Diundang dalam berbagai acara sastra, a.l:, Cakrawala Sastra Indonesia (Dewan Kesenian Jakarta,2004), memberikan ceramah sastra di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan (Juni, 2009), Festival Sastra Internasional Ubud Writters and Readers Festival 2009), Mimbar Penyair Abad 21 (DKJ, 1996), dll. Memperoleh Penghargaan Sastra Pendidik dari Badan Pusat Bahasa (2011), Penghargaan Seniman (Sastrawan) dari Gubernur Jawa Timur (2014) dan Penghargaan Sutasoma (Balai Bahasa Jawa Timur, 2019). Memenangkan berbagai sayembara menulis a.l: Pemenang II Sayembara Kritik Sastra Nasional Dewan Kesenian Jakarta (2004), Pemenang Unggulan Telaah Sastra Nasional Dewan Kesenian Jakarta (2010), Pemenang II Sayembara Pusat Perbukuan Nasional (2008 dan 2009), Pemenang II Sayembara Esai Sastra Korea (2009), dll.
I Nyoman Wirata lahir di Denpasar, 1953. Selain penyair, dia adalah seorang pelukis. Dia menulis puisi sejak tahun 1975. Buku puisi tunggalnya adalah Merayakan Pohon Di Kebun Puisi (2007), Destinasi (2021). Dia menerima anugerah Widya Pataka (2007) dan Bali Jani Nugraha (2020) dari Pemerintah Provinsi Bali.