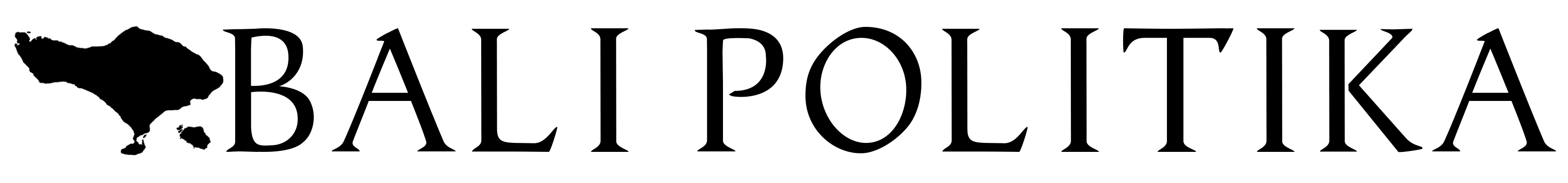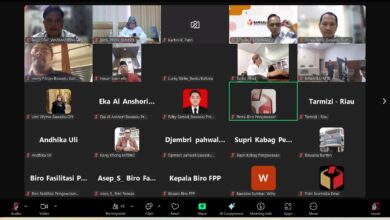Di Provinsi Bali saat ini terdapat 440.000 potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Dari berbagai kesimpulan penelitian dan berbagai seminar terkait eksistensi UMKM dan koperasi, untuk menghadapi persaingan ketat di bidang usaha, berkisar di antara lemahnya akses permodalan, pemasaran, teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia.
Pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan kalangan UMKM dan koperasi secara nasional pada umumnya, dan Provinsi Bali pada khususnya merupakan kewajiban pemerintah. Oleh karenanya, peranan UMKM dan koperasi mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan negara dari pajak. Peran UMKM dan koperasi sebagai katup pengaman masalah sosial dan bahkan politik tidaklah kecil.
Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi kalangan UMKM dan koperasi adalah lemahnya akses permodalan, terutama dalam rangka pemenuhan persyaratan formal untuk bisa terlayani perbankan, yaitu jaminan. Walaupun usahanya layak, tetapi kalau tidak tersedia jaminan yang cukup, mereka tidak bisa mendapatkan layanan dan akses permodalan.
Pada tahun 2010, setelah setahun terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, penulis mencermati fenomena ini. Pernah diterapkan kebijakan progran kredit tanpa agunan oleh pemerintah daerah dan jaminan disiapkan melalui APBD. Setelah diterapkan, ternyata menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
Bertitik tolak dari hal di atas, penulis mencoba mengkaji dan merumuskan terobosan berdasarkan atas mekanisme dan ketentuan yang ada, prioritas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi di Bali, melalui diskusi dengan para akademisi (Universitas Udayana) dan praktisi, serta konsultasi dengan Departemen Keuangan dan Gubernur Bali, dilanjutkan dengan penyusunan kajian akademik. Maka dituangkanlah gagasan pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah di Provinsi Bali. Gagasan dan terobosan tersebut disampaikan kepada Gubernur Bali, Komisi II DPRD Bali dan badan legislasi, yang pada akhirnya disepakati membentuk Paniitia Khusus (Pansus) dengan menunjuk penulis sendiri sebagai ketua Pansusnya.
Perjalanan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), ternyata tidak berjalan mulus. Banyak hambatan bernuansa politis yang berusaha menghambat dan cenderung untuk menggagalkannya. Dengan berbagai upaya untuk meyakinkan penting dan strategisnya Jamkrida ke depan untuk UMKM dan koperasi, serta ekonomi Bali ke depan, akhirnya Perda disahkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 720/KM.10/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang izin usaha.
PT Jamkrida Bali Mandara beroperasi mulai tahun 2011 dengan modal disetor dari APBD Bali sebesar Rp50 miliar dengan usaha membantu UMKM dan koperasi melaui penjaminan kredit pada bank, di mana atas penjaminan yang diberikan, baik pihak UMKM maupun bank mendapat dukungan mitigasi resiko dan subsitusi jaminan.
Perkembangan sampai dengan September 2023, plafon penjaminan yang disediakan sebesar Rp38,76 triliun, nilai penjaminan sebesar Rp26,7 triliun dan jumlah entitas yang terjamin sebesar 546.730 atau rata-rata sebesar 77.000 UMKM dan koperasi per tahun selama lima tahun terakhir.
Sebuah gerakan dukungan riil kepada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat di Bali, dan berpengaruh signifikan terhadap daya tahan dan kelenturan ekonomi Bali yang mayoritas didukung oleh kalangan ekonomi rakyat. Secara kelembagaan, PT Jamkrida Bali Mandara telah 5 kali berturut-turut ditetapkan sebagai perusahaan milik daerah terbaik secara nasional.