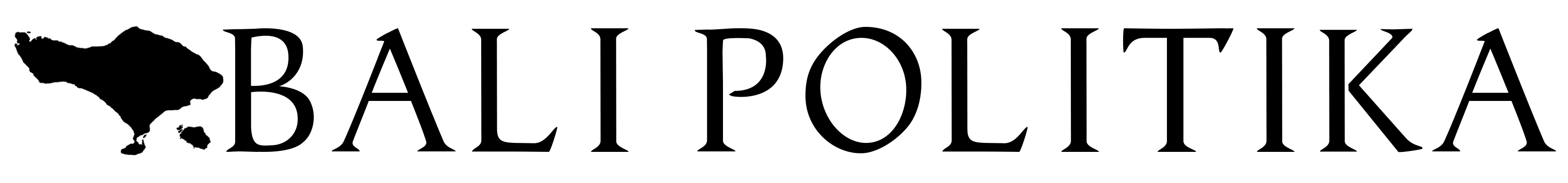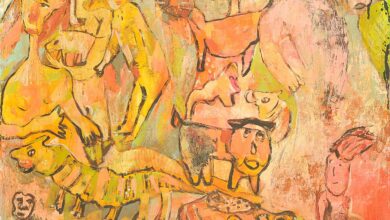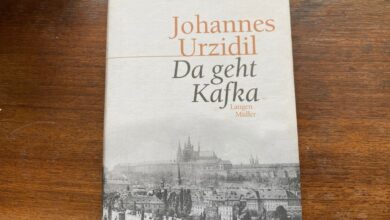MENYUBLIM: Ananda Sukarlan lewat karya Libertas menunjukkan bagaimana musik (klasik) dan puisi saling berkolaborasi dalam satu panggung tanpa perlu menyebutnya dengan embel-embel “musikalisasi puisi”.
MUSIK klasik telah lama terinspirasi oleh konflik, seperti perang, misalnya. Ada beberapa komposer yang merespons perang dengan gagasan perdamaian, ada juga yang menyuarakan semangat kemiliteran. Sebutlah Frank Bridge, komposer Inggris sekaligus pasifis yang menulis lagu ringan dan terkesan mudah. Harmoni yang luas dan energi bergejolak dalam sonatanya mungkin tidak terkesan menunjukkan perdamaian dalam pengertiannya yang tradisional. Tetapi trauma perang dunia mendorongnya untuk menyusun komposisi yang menurutnya bermakna. Ia menulis sonata yang didedikasikan untuk Ernest Farrar, seorang komposer muda yang mati dalam perang.
Bridge meninggal pada tahun 1941, sebelum dia melihat negaranya menang atas Jerman dalam perang berikutnya. Tetapi ia pernah menuliskan cita-cita pasifis kepada muridnya yang terkenal, Benjamin Britten. Britten menulis War Requiem untuk mengenang empat kawannya yang menjadi korban Perang Dunia 2. Karya diselingi puisi Wilfred Owen, seorang penyair-prajurit Perang Dunia 1 yang menulis tentang kematian perang. Requiem bukanlah komposisi pertama –atau terakhir– Britten yang mendesak perlunya perdamaian. Sebagai seorang yang sudah lama menjadi seorang pasifis dia telah menulis musik pada tahun 1930-an untuk Persatuan Ikrar Perdamaian dan terus mengeskpresikan cita-cita damainya melalui musik hingga tahun 60-an dan awal 70-an.
Apa yang dilakukan Britten dalam memadukan musik dan puisi adalah hal yang lazim seperti juga dilakukan Ananda Sukarlan dengan tembang puitiknya. Dengan memadukan musik klasik dengan puisi, ia ingin menyuarakan kegelisahan kepada “dunia” tentang nilai dan makna yang dalam untuk kembali dihayati bersama dalam sebuah konser, di mana kita akan kelimpahan nada-nada “Tuhan” yang samar dan rahasia.
Musik seringkali merupakan perwujudan harapan banyak orang akan perdamaian, berhentinya kekerasan, kekejaman massal, dan perang. Jacques Attali memperingatkan kita dalam Noise: a Political Economy of Music, bahwa musik mungkin ada hubungannya dengan disonansi dan kekerasan seperti juga dengan perdamaian dan harmoni sosial. Penilitan yang dilakukan Attali memerlukan pemahaman yang mendalam karena ia mengantisipasi kritik terhadap kepercayaan yang agak naif bahwa “musik dan penciptaan perdamaian” bisa dijadikan sebagai obat mujarab bagi sakit peradaban. Walaupun paradoks mengenai hubungan musik dengan perubahan sosial di mana kekerasan dan perdamaian berkelindan kini diakui secara luas olah para praktisi maupun peneliti.
Meskipun manusia telah lama memainkan musik untuk mendorong tercapainya perdamaian, ketenangan dan harmoni sosial (bahkan mungkin sebelum mereka dapat berbicara), mereka dapat menggunakan suara, nada, ritme yang sama untuk membangkitkan emosi yang mendorong pada kekerasan dan mengirim manusia (terutama laki-laki) ke medan pertempuran. Bagi mereka yang menganjurkan dan meniliti hubungan antara musik dan pengalaman sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, pemahaman bersama (komunikasi), dan perdamaian, harus bergulat dengan “sisi lain” dari kekuatan musik untuk menggerakan kita kepada hal sebaliknya; kejahatan.
Seni sudah sejak lama menjadi piranti untuk mengembangkan peradaban batin manusia, tari, teater, sastra, dan musik. Seni berakar secara historis dan kontekstual. Musik adalah salah satu bentuk seni yang mudah ditangkap telinga hati, ia mencerminkan nilai-nilai dan praktik sosial yang membantu membawa suatu kelompok saling melintas satu sama lain, berkelindan dan menghayati kedalaman nilai-nilai kemanusian.
Musik ada di setiap agama, ada di setiap budaya. Musik melekat pada alam. Musik menjalar di mana-mana. Musik berakar pada spiritualitas manusia. Maka, tidak heran ada gagasan bahwa musik dapat membawa kedamaian dan kesejahteraan.
Lantas, bagaimana musik menciptakan perdamaian? Bagaimana musik menyembuhkan sakit peradaban? Bagaimana musik mencegah kekerasan? Bagaimana musik membangun masyarakat yang beradab?
Musik dan Puisi: Mata Uang Diplomasi
Bukan sesuatu yang aneh jika musik dan puisi seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya dapat digunakan sebagai alat “diplomasi lunak” dengan kekuatan bunyi dan kata-kata, yang mana dapat membawa pesan (nilai-nilai) untuk kemudian mendorong manusia menciptakan “peradaban sehat”.
Bukan hanya para komposer, tapi juga penyair sudah sejak lama menyuarakan “suara lain” kepada dunia yang selalu gelisah dan rawan. Pelukis dan para seniman lain pun lazim menggunakan media masing-masing untuk mengucapkan kegelisahannya tentang kondisi dunia yang kadang-kadang “merosot” jatu ke jurang neraka.
Mengenai musik dan puisi dalam konteks dialog perdamaian, sebagai satu kesatuan nilai memang keduanya sama. Jika dilihat dari “pesan”, artinya pragmatis, keduanya akan tampak sebagai alat saja. Tetapi musik dan puisi adalah seni, yang tentu saja akan selalu bersikap estetik daripada praktis. Maka, diplomasi perdamaian melalui keduanya tidak mungkin “verbal”, artinya tanpa menyentuh dasar batin manusia. Justru “diplomasi budaya” melalui musik dan seni akan jauh menghunjam nurani dan mendorong kepada penghayatan nilai-nilai universal yang indah untuk dijadikan pegangan manusia dalam mengarungi kondisi-kondisi kritis dunia yang tak pernah damai itu.
Apa yang dilakukan Ananda Sukarlan dengan karyanya, Libertas, bisa menjadi contoh yang baik, tentang bagaimana musik (klasik) dan puisi saling berkolaborasi dalam satu panggung tanpa perlu menyebutnya dengan embel-embel “musikalisasi puisi” yang mana keduanya bukanlah sesuatu yang terpisah satu sama lain, melainkan menyatu dan menyublim.
Libertas; sebuah karya untuk bariton (walaupun juga bisa dinyanyikan tenor dengan register rendah, seperti sudah dinyanyikan tenar Indonesia ternama Nikodemus Lukas), paduan suara dan orkes kamar. Karya ini berdasarkan puisi-puisi tentang kemerdekaan dari Archibald Macleish, Chairil Anwar (Ananda Sukarlan menyandingkan “The Young Dead Soldiers do not Speak” dengan “Krawang-Bekasi” yang sering dianggap sebagai “jiplakan” atau tepatnya saduran dari puisi yang disebut pertama), Sapardi Djoko Damono (“Kita Ciptakan Kemerdekaan”, satu-satunya puisi yang memang khusus diciptakan untuk menjadi bagian dari karya Libertas ini), Walt Whitman, Hasan Aspahani (“Palestina”) dan Luis Cernuda.
Seperti juga telah dilakukan Ananda Sukarlan pada tanggal 13 Juni 2024 dengan karya-karyanya “Findolandesia” untuk biola dan piano sebagai “perkawinan” lagu kebangsaan Finlandia “Maamme” dan “Tanah Airku” dari Ibu Sud (dimainkan dengan mengesankan oleh pemain biola muda Aurell Marcella, lulusan Australian Institute of Music dan terpilih menjadi anggota G20 Orchestra yang prestisius), atau “I Wish Matilda Had Waltzed to Minang” (gabungan “Kampung Nan Jauh di Mato” dan “Waltzing Matilda”) yang akan dipagelarkan bulan Juli nanti. Keduanya memang diciptakan untuk merayakan hubungan diplomatik dan persahabatan dua negara, yang pertama 70 tahun Finlandia dan Indonesia, yang kedua 75 tahun Australia dan Indonesia.
Ananda juga menciptakan karya baru “Two Australian Songs” untuk soprano dan piano, berdasarkan puisi penyair Australia; Henry Lawson dan Judith Wright yang akan dimainkan oleh soprano Mariska Setiawan dan pemain alat gesek dari Melbourne Symphony Orchestra.
Musik dan puisi sebagaimana dilakukan Ananda Sukarlan tersebut adalah suatu bukti bahwa keduanya bisa menjadi “mata uang” atau alat tukar budaya yang membawa nilai-nilai universal. Musik dan puisi akan bekerja sama untuk membawa nilai-nilai itu dengan kekhasannya masing-masing. Puisi meminjam musik untuk menunjang bangun estetiknya (sembari tetap menyiratkan makna), musik juga meminjam puisi untuk memperkuat “ketebalan” daya dorong makna agar nurani paling keras sekalipun dapat tergedor oleh tangan-tangan halus nada-nada.
Sir Karl Jenkins, salah satu komposer yang berprestasi, telah menggubah karya One World bersama World Choir for Peace dan World Orchestra for Peace (yang didirikan pada tahun 2018 untuk menandai peringatan 100 tahun Perang Dunia Pertama), membawakan pertunjukan peringatan The Armed Man: A Mass for Peace di Berlin dengan Paduan suara 2000 penyanyi dari 30 negara. UNESCO Artists for Peace, yang didirikan bersama oleh Sir Georg Solti dan Charles Kaye pada tahun 1995 yang menegaskan kembali “kekuatan unik musik sebagai duta perdamaian” membuka kemitraan untuk karya Paduan suara baru yang menomental itu; One World.
One World, sebagai satu contoh bahwa musik dapat dijadikan alat diplomasi untuk merekatkan kembali “keretakan” akibat wabah penyakit, perubahan iklim, perang, terorisme, perdagangan manusia, pelanggaran HAM, dan seterunya. Seperti juga puisi yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yang menyatukan para pemuda untuk menyiapkan dan mewujudkan kemerdekaan, menjadi bangsa yang berdaulat atas tanah air dan bahasa sendiri.
Seperti juga musik, puisi-puisi Chairil Anwar, WS Rendra (dengan pembacaannya di atas panggung), Wiji Thukul, dan lain-lain, menggunakan puisi untuk berdiplomasi dengan kekuasaan (apakah penjajah atau pemimpin bangsa sendiri) agar menjalankan keadilan seadil-adilnya, agar tercipta kehidupan yang tenang, damai dan sejahtera.
Maka, melalui bunyi dan kata-kata kita dapat melakukan “diplomasi budaya” agar nilai-nilai universal dapat disalurkan tanpa kekerasan dan paksaan. Agar supaya tumbuh kesadaran-kesadaran sebab mau membuka diri pada “suara keindahan” atau “suara lain” dan mungkin juga “suara Tuhan” yang dititipkan kepada mereka, para seniman dan orang-orang kreatif di sepanjang zaman.
Sebagai “mata uang” diplomasi musik dan puisi tidak bisa dipisahkan, keduanya akan digunakan bersamaan untuk “membeli” kemungkinan-kemungkinan, mencapai puncak-puncak makna dan ketinggian peradaban manusia yang manusiawi, yang insyaf akan dirinya, yang telah “menerima” hidup sebagai anugerah bukan sebagai bencana, yang bersikap adil dan tidak melakukan kekerasan demi ambisi kekuasaan. Singkatnya manusia berbudaya yang menjaga perdamaian di mana-mana dengan pikiran dan laku, sehingga tercipta kesejahteraan di mana-mana.
Akhirnya, dialog perdamaian melalui musik dan puisi dapat disimpulkan sebagai dialog kebudayaan bukan polemik kebudayaan, dan hasil dari dialog-dialog intens itu akan menjadi laku (tindakan) bukan saja bunyi atau kata-kata di atas kertas, tapi perjuangan melaksanakan nilai-nilai dan memecahkan persoalan mendasar kita, menciptakan harmoni jiwa dan harmoni sosial. Wassalam. (***)
BIODATA
Emi Suy. Lahir di Magetan, Jawa Timur, dengan nama Emi Suyanti. Sampai saat ini Emi sudah menerbitkan lima buku kumpulan puisi tunggal, yaitu Tirakat Padam Api (2011), serta trilogi Sunyi yang terdiri dari Alarm Sunyi (2017), Ayat Sunyi (2018), Api Sunyi (2020) serta Ibu Menanak Nasi Hingga Matang Usia Kami (2022), buku kumpulan esai sastra Interval (2023), serta satu buku kumpulan puisi duet bersama Riri Satria berjudul Algoritma Kesunyian (2023). Ia menulis naskah opera (Libretto) I’m Not For Sale tentang perjuangan tokoh perempuan Ny. Auw Tjoei Lan menantang kematian menyelamatkan kehidupan.