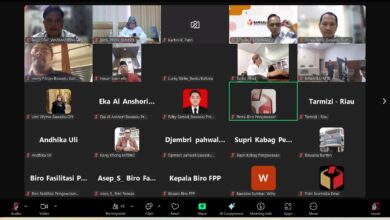CALEG SELEBRITIS: Primus Yustisio, Caleg Selebritis yang Memperoleh Suara Tertinggi di DPR Dapil Jawa Barat
JAKARTA Balipolitika.com- Perolehan suara para calon legislatif (caleg), termasuk caleg dari kalangan selebritis bertambah seiring penghitungan suara Pemilu 2024. Sejumlah artis maju menjadi caleg DPR RI dengan daerah pemilihan yang berbeda-beda. Salah satunya Jawa Barat. Per Rabu, 21 Februari 2024, pukul 12.00 WIB, perolehan suara tertinggi di Jawa Barat dipegang oleh Primus Yustisio. Para caleg selebritis ini tersebar di berbagai daerah pemilihan di Jawa Barat. Berikut data perolehan suara mereka dari yang tertinggi:
1. Primus Yustisio
Aktor Primus Yustisio, yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN), berada di dapil Jawa Barat V (meliputi Kabupaten Bogor). Dia memperoleh 59.378 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 45.22 persen.
2. Dede Yusuf Effendi
Dede Yusuf dari Partai Demokrat berlaga di dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) memperoleh 52.963 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 28.40 persen.
3. Tommy Kurniawan
Aktor Tommy Kurniawan diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) memperoleh 47.757 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 45.22 persen.
4. Mulan Jameela
Penyanyi Mulan Jameela dari Gerindra dengan daerah pemilihan Jawa Barat XI (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya) mendapatkan 44.289 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 61.70 persen.
5. Rachel Maryam Sayidina
Rachel Maryam Sayidina dari Gerindra dengan Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) memperoleh 33.310 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 28.40 persen.
6. Desy Ratnasari
Artis peran Desy Ratnasari dari PAN dengan Dapil Jawa Barat IV (Kabupaten dan Kota Sukabumi) memperoleh 31.152 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 43.53 persen.
7. Taufik Hidayat
Mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat dari Gerindra dengan Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) memperoleh 26.738 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 28.40 persen.
8. Melly Goeslaw
Penyanyi Melly Goeslaw dari Partai Perindo dengan Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) memperoleh 26.471 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 35.70 persen.
9. Ali Syakieb
Aktor Ali Syakieb dari PDI Perjuangan di Dapil Jawa Barat XI (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya) memperoleh 24.116 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 61.70 persen.
10. Nurul Arifin
Artis Nurul Arifin dari Golkar dengan daerah pemilihan Jawa Barat I. Nurul Arifin memperoleh 22.833 suara. Data ini diperoleh dengan progres data masuk 35.70 persen. (dp)