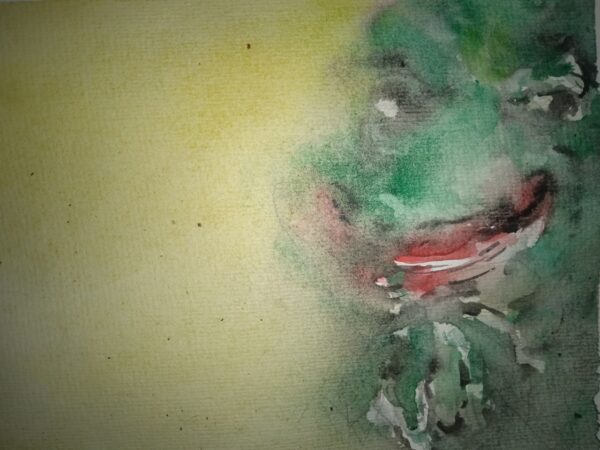SEMBARI menunggu pawai ogoh-ogoh, sehari jelang Nyepi di Titik Nol Ubud yang dikerumuni turis asing, nampak beberapa anak muda Bali berpakaian adat lengkap dengan udeng asyik memutar spin secara virtual.
Satu dari mereka kemudian berceloteh kepada yang lain, “Ah sial, tiang (saya) kurang hoki, gimana khee (loo)?“ ujarnya kepada seorang kawan sembari menunggu hasil yang ternyata berakhir jackpot itu.
Si temannya kemudian berkata kepada yang kurang hoki tadi, “Ah, tenang aja boleh coba lagi. Siapa tahu rezeki”, ujarnya sembari tertawa di hadapan temannya yang mengaruk-garuk kepala karena gagal jackpot.
Saya yang berdekatan dengan mereka hanya bisa mengelus dada, menyaksikan fenomena semakin masifnya praktik judi online di segala tingkatan umur.
Sama seperti persoalan narkoba, prostitusi, senjata ilegal, sampai pada korupsi yang dipandang sebagai bagian dari “shadow economy” yang memberikan kerugian massif sekaligus keuntungan bagi segelintir orang itu; begitu pun pinjol dan judol semakin melekat pada kehidupan berbangsa kita.
Ironisnya, kedua bisnis yang menyebabkan penyakit sosial dan psikologis bagi masyarakat ini belum sepenuhnya diatasi oleh pemerintah.
Bahkan, disinyalir judi online yang menurut banyak kajian investigasi kendalikan dari kamboja itu malah didalangi oleh elite-elite lokal sendiri.
Kalau sudah begini rasa-rasanya semakin hambarlah julukan sebagai negara paling religi, jika dihadapkan pada realitas sosial di mana masyarakat semakin akrab dengan judi dan pinjaman online yang justru jauh dari istilah religius.
Jika kita cermati, eksistensi pinjol dan judol dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih mementingkan religiusitas itu tidak terlepas dari dampak dinamika sosial-budaya yang hari ini dan nanti berada dalam tarik-ulur antara identitas keagamaan yang mengakar dan gelombang budaya global yang justru mendorong dehumanisasi.
Masyarakat Indonesia, yang secara historis dibangun atas nilai-nilai kolektivisme (gotong royong), kesederhanaan (sederhana), dan spiritualitas (religiusitas), kini sedang terjebak dalam kontradiksi akibat infiltrasi budaya hedonistik dan matrealistik yang dipacu oleh teknologi dan kapitalisme global.
Oleh karena itu , memahami pinjol dan judol bukan sekadar masalah praktik ekonomi yang ilegal semata, melainkan juga cermin dari pergeseran orientasi hidup masyarakat dari yang merasa berkecukupan menjadi ingin berkelimpahan, dari yang mempunya rasa untuk bersyukur menjadi semakin konsumtif.
Tapi, jika semata-mata hanya menyalahkan masyarakat dengan segala problematika sehari-hari yang sudah mereka alami apalagi menuding segala yang terjadi itu akibat ulah asing, bagi saya merupakan tindakan dan pikiran yang dangkal yang justru memperpanjang mentalitas mencari-cari kambing hitam tanpa menyelesaikan masalah sebenarnya.
Saya bersepakat dengan pendapat dari Sukidi, pemikir kebhinekaan dan tokoh Muhammadiyah itu dalam artikelnya yang termuat di Kompas berjudul “ Mewaspadai Berbagai Kemungkinan“.
Ulasnya hal-hal buruk yang merusak bangsa Indonesia sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, artinya kita harus mengoreksi internal kita dahulu yang sudah sistemik rusaknya ini.
Dalam artikel lain berjudul “Menyelamatkan Republik Kita”, Sukidi mengingatkan sekaligus memberikan kita dasar untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara menyerang akar dari kejahatan (the root of evil) itu sendiri, bukan semata-mata hanya menebas cabang-cabang kejahatan (the branches of evil).
Pinjol dan Judol Kekuatan Bhutakala Era Baru
Jika dihubungkan dengan teologi Hindu, khususnya nusantara, kepercayaan yang saya yakini, eksistensi judol dan pinjol merupakan manifestasi bhutakala era baru.
Adapun bhutakala dipercaya sebagai kekuatan alam yang bersifat negatif.
Dalam setiap perayaan Nyepi, bhutakala dimanifestasikan dalam bentuk ogoh-ogoh beragam rupa yang kemudian dibakar melalui proses pralina setelahnya agar unsur panca maha bhuta (api, air, tanah, udara, dan cahaya) yang negatif tadi kembali ke asalnya sebagai simbolisme teologis untuk terus menjaga keseimbangan.
Secara teologis, pengendalian bhutakala dengan menggunakan ritual itu merupakan usaha yang bersifat niskala (ketuhanan) guna menanggulangi mala petaka yang ditimbulkan oleh makhluk domenik alias makhluk halus.
Jika digeser dari teologis ke sosial, manifestasi bhutakala melampaui makhluk halus hingga namun laku manusia yang merusak tatanan Tri Hita Karana alias keseimbangan harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia.
Apalagi dalam konteks judol dan pinjol yang banyak unsur negatifnya itu, maka menetralisir dua manifestasi bhutakala ini harus dilakukan dengan serius karena dampak yang ditimbulkan sangat sistemik di level mikro, mezzo, dan makro.
Pinjol dan judol di level mikro bahkan bisa berujung hilangnya nyawa, kasus bunuh diri (ulah pati) yang dilakukan oleh seorang remaja putri di Jembatan Tukad Bangkung, Badung baru-baru ini.
Korban diduga nekat mengakhiri hidup karena tekanan tagihan pinjol.
Terlepas dari cara yang dilakukan korban secara teologi dan sosial itu salah, kejadian ini menambah panjang tragedi hilangnya nyawa akibat pinjol dan judol.
Sebagai masyarakat sudah sepantasnya kita berempati dan bereaksi merespons kasus-kasus serupa yang terjadi di seantero Indonesia.
Tetapi, kepedulian kita ini jangan juga dimaknai untuk membenarkan atau menoleransi perilaku berpinjol dan berjudol.
Untuk judol misalnya, si pelaku sebenarnya memiliki pilihan yang harusnya rasional untuk tidak berjudi di mana menang dan kalahnya sudah dirancang oleh si bandar.
Kepedulian kita harus diarahkan kepada hal etis dan moral yang menyangkut dampak dari yang penjudi lakukan bagi dirinya sendiri dan keluarga.
Apalagi kebanyakan dari pemain pinjol ini berasal dari kelas menengah bawah.
Judi bagi kelas berjouis merupakan hiburan namun bagi kelas proletar perilaku berjudi justru menjadi jeratan.
Begitu pun pinjol yang seringkali bukan diakibatkan oleh kebutuhan, tapi juga kepuasan untuk memiliki sesuatu dengan cara yang instan.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan berhutang apalagi jika menyangkut kebutuhan yang penting dan genting, hanya saja rasional dalam mempertimbang risiko menjadi hal mutlak agar mental kita tidak dibunuh oleh tekanan penagihan yang ditimbulkan oleh pinjol di kemudian hari.
Di level makro, kita juga harus mendorong penyelesaian praktik pinjol dan judol lebih masif lagi.
Penegakan hukum yang adil perlu terus-menerus kita lantangkan apalagi saat ini kita masih hidup dalam sistem hukum dua level.
Level pertama, di mana orang miskin dilecehkan, ditangkap, dan dipenjara karena pelanggaran yang ‘tidak luar biasa’.
Sementara level dua, kejahatan yang sangat besar yang dilakukan oleh kaum oligarki dan korporasi, seperti kongkalikong dengan praktik judol dan pinjol justru ditangani melalui kontrol administratif lemah, denda simbolis, dan penegakan hukum perdata yang memberikan kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan kaya ini dari tuntutan pidana.
Kepada mereka yang disinyalir mempromosikan praktik judol dan pinjol, menerapkan cancel culture rasa-rasanya perlu dilakukan agar menimbulkan efek jera di ruang publik agar mereka yang memiliki kekuatan dan akses untuk mempengaruhi orang banyak dapat menggunakan potensi mereka dengan sebijak mungkin bukan malah menjerumuskan orang lain kedalam lingkaran setan judol dan pinjol.
Masyarakat Teknologi Ala Indonesia: Kemajuan di Arus Alienasi dan Krisis Makna
Transformasi teknologi digital memang telah mengaburkan batas moral di mana perilaku judi dan utang yang dulu terlihat secara fisik, kini menjadi abstrak dan “tak kasat mata” di balik layar gawai.
Gawai sendiri seolah menjadi organ nonalamiah yang jika kita coba lepaskan atau kurangi pemakaian meskipun satu jam saja, maka kecemasan akan melanda kita.
Akibat teknologi, masyarakat menjadi semakin teralienasi dari kontrol sosial tradisional karena laku dari kedua hal tadi terjadi dalam ruang virtual yang impersonal.
Dari sudut pandang Marxist yang ide-idenya masih relevan untuk menjelaskan fenomena zaman secara kritis, kemajuan pada akhirnya menciptakan bentuk baru dari alienasi ini pada akhirnya menjadi alat penindasan terselubung.
Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir pernah memperingatkan akan modernitas kita yang seperti topeng yang selalu dipakai tanpa dihayati.
Fenomena judol dan pinjol adalah contoh konkret dari “topeng” ini, di balik kemudahan teknologi, ada kehancuran psikologis dan sosial akibat dari nihilisme yang tidak kita akui dan sadari .
Sartre dalam Existentialism is a Humanism juga menegaskan, “Manusia adalah makhluk yang tidak memiliki esensi sebelum eksistensinya; ia harus menciptakan dirinya sendiri melalui pilihan-pilihannya.”
Namun, dalam dunia yang didominasi logika teknologi, pilihan-pilihan ini sering kali direduksi menjadi preferensi konsumtif yang instan, bukan proyek eksistensial yang bermakna.
Pada akhirnya judol dan pinjol adalah manifestasi konkret dari nihilisme modern di mana saat modernitas yang kita rasakan itu kehilangan nilai transendennya, maka kita cenderung mencari “dopamin instan” sebagai pengganti makna yang absen kembali kepada nilai-nilai yang transenden dalam hal ini pemaknaan kembali pada yang religius yang melampuai sebatas ritus rasa-rasanya perlu kita lakukan.
Memahami Mekanisme Psikologis Pinjol dan Judol
Judol dan pinjol dapat berkerja membentuk lingkaran setan tidak terlepas dari permainan mekanisme psikologis yang dimainkan oleh platform-plaform terhadap persepsi para korbannya.
Setidaknya ada tiga mekanisme psikologis yang erat dengan persepsi yang saya cermati dibentuk secara laten oleh platform-platform pinjol dan judol.
Pertama, persepsi terkait kontrol yang sebenarnya ilusi di mana kita diposisikan sudah menjadi hal wajar jika bertemu dengan mereka yang berkutat dengan judol dan pinjol ada perasaan seolah-olah mereka memiliki kontrol akan hasil, batasan, dan dampak yang di timbulkan padahal sebenarnya tidak sama sekali.
Kemudahan pencairan pinjol dengan rayuan bunga yang kecil, misalnya membuat mereka ingin lagi dan lagi untuk menambah pinjaman tanpa berpikir panjang akan dampak dari tekanan penagihan yang dilancarkan oleh pinjol.
Begitu pun dengan judol hanya karena kemenangan sekali mereka terus menerus melakukan top up untuk permainan selanjutnya apalagi dengan bayaran yang menyesuaikan kantong mereka sehingga mereka merasa seolah-olah tidak rugi-rugi amat yang masih dalam tataran yang bisa mereka kontrol padahal dari yang sedikit ini jika dikalkukasi akan terus berlipat ganda yang efeknya merugikan finansial si pelaku.
Kedua, emosi akan kenikmatan di mana ketika kita mendapatkan cuan dari kemenangan judol dan hutang pinjol maka kita akan merasakan kenikmatan seolah-olah finansial kita menjadi sehat kembali dan proses yang kita tempuh itu setara dengan hasil hal ini ditambah dengan gambaran yang seolah-olah berkebalikan dengan citra negatif keduanya.
Kenikmatan yang sesaat muncul kemudian menimbulkan dorongan untuk melakukan tindakan lagi dan lagi.
Ketiga, bermain-main dengan persepsi nasib di mana dalam masyarakat Indonesia, ada pepatah “Manusia berencana, Tuhan menentukan“.
Judol dan pinjol mencerminkan upaya manusia untuk mengakali nasib dengan cara instan. Keduanya adalah cermin dari paradoks, keinginan untuk mengontrol nasib, tapi justru terjatuh dalam ketidakpastian yang lebih dalam.
Seperti lampu gemerlap kasino, janji judol dan pinjol menyilaukan, tetapi akhirnya memperlihatkan realitas keras, takdir tak selalu bisa dipaksa padahal di balik kepercayaan kita akan nasib ada nilai kesabaran (sabar), kerja keras (ikhtiar), dan kepercayaan pada proses.
Pada akhirnya, melawan pinjol dan judol tidak cukup dengan kampanye moral atau pemblokiran platform.
Perlu gerakan kolektif untuk menata ulang sistem ekonomi-politik yang adil, memutus oligarki, dan mengembalikan makna hidup yang transenden sebagai upaya untuk melawan bhutakala era baru ini.
Pada akhirnya kembali seperti yang diingatkan oleh Sukidi, menyelamatkan republik ini adalah tugas bersama, bukan hanya memberantas kejahatan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang memanusiakan.
Tanpa itu, kita hanya akan menjadi bangsa yang religius di atas kertas, tetapi terjajah oleh manifestasi bhutakala digital buatan sendiri. (*/bp)
BIODATA
Putu Ayu Sunia Dewi adalah Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Media Televisi Perhimpunan Pelajar Indonesia Seluruh Dunia (PPI DUNIA) 2025-2026.