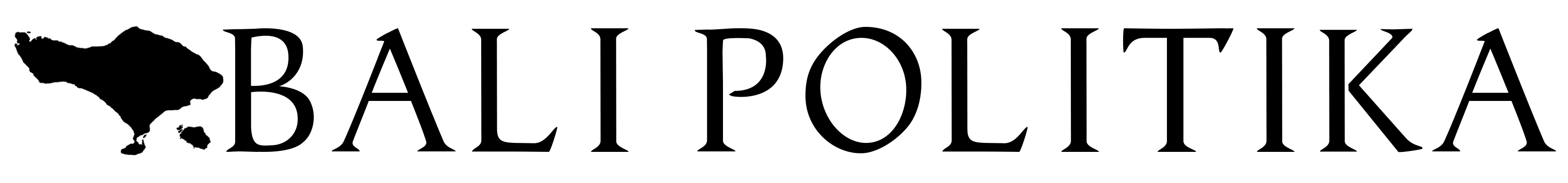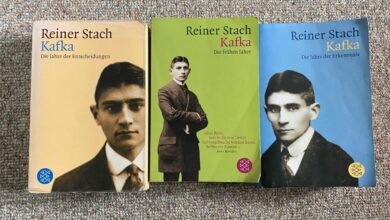APA yang tersisa dalam laku budaya masyarakat adat Buahan, Kecamatan Kintamani, Bangli, menarik untuk ditilik lebih jauh. Desa ini menjadi salah satu desa yang cukup tegar “merawat diri” di tengah badai kapital pariwisata yang sedang kencang-kencangnya menghantam kawasan Kintamani. Kearifan leluhur dari ribuan tahun silam ditanam dalam ceruk terdalam peradaban mereka; di belantara paling rimbun laku hidup masyarakat untuk terus diwariskan.
Buahan sebagai komunitas adat yang otonom telah eksis setidaknya sejak sepuluh abad silam. Inskripsi tertua berangka tahun 916 Saka (994 Masehi) mencatat komunitas adat ini sebagai Karāmān i Wingkang Ranu Bwahan ‘penduduk ke-rama-an di tepi danau yang bernama Buahan’. Inskripsi ini–bersama empat kelompok lainnya–dikenal masyarakat akademis sebagai Prasasti Bwahan (selanjutnya ditulis Prasasti Buahan)1.
Istilah karāman dapat disepadankan dengan pengertian desa. Astra (2023) mengartikan karāman sebagai ‘penduduk desa’ atau secara lebih terbatas merujuk pada ‘pemuka adat; tetua desa’. Adapun desa dalam hal ini adalah satuan persekutuan hidup berbadan hukum yang mencakup wilayah, manusia, serta peraturan dan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut2.
Namun demikian, apabila diamati secara morfologis, kata karāman–atau dalam Prasasti Bwahan A ditulis karāmān–berasal dari kata rāma yang berarti ‘ayah; tetua’. Kata rāma mengalami afiksasi berupa pengimbuhan konfiks ka-an, sehingga membentuk kata turunan karāman, yang dapat diartikan ‘keayahan’ atau ‘ketetuaan’.
Karāman atau ketetuaan secara sosiologis sejalan dengan sistem adat kemajelisan-kelebihdahuluan (ulu-apad) yang eksis di sejumlah desa tua di Bali sampai saat ini. Gelar para tetua adat di desa-desa dengan sistem ulu-apad antara lain rāma kabayan, rāma bahu, atau balirāma.
Belakangan, kata rāma tampaknya berkembang menjadi guru atau wayah yang maknanya masih berkelindan. Oleh karena itulah ditemukan panggilan guru kubayan, guru bahu, guru singgukan, baliwayah, guru kraman [karāman], atau jero guru sebagai gelar kehormatan bagi tetua desa pada desa-desa sistem ulu-apad.
Khusus di Desa Buahan, istilah rāma (balirāma) bahkan digunakan sebagai nama ritual. Ritual tersebut adalah pagaman balirāma yang dilaksanakan pada puncak Ngusaba Kadasa di Pura Desa Buahan setiap Panglong Pertama Sasih Jyestha (sehari setelah Purnama Jyestha).
Lima Kelompok Prasasti Buahan3
Saat ini penduduk Buahan mewarisi 23 lempeng prasasti tembaga. Sebanyak 22 lempeng di antaranya tertatah tulisan beraksara Bali Kuno dengan bahasa Jawa Kuno, sedangkan satu lempeng sisanya tidak tertatah aksara. Lempengan-lempengan tersebut memiliki dimensi beragam, diklasifikasi dalam lima kelompok menurut tahun dan wacana yang dimuat.
Prasasti Buahan A adalah kelompok prasasti tertua. Kelompok ini terdiri atas lima lempeng tembaga dengan dimensi 34 x 14 cm. Penanggalan prasasti adalah hari Paniron, Wrehaspati Kliwon Wuku Marakih, Pananggal Kelima, bulan Palguna (Sasih Kawulu: antara bulan Februari-Maret), tahun Saka 916 (994 Masehi).
Pada waktu tersebut tetua Desa Buahan menghadap raja suami-istri, Sri Gunapriya Dharmapatni-Sri Dharmodayana Warmadewa. Tujuan menghadap raja adalah memohon hak otonomi, agar desanya tidak lagi terikat dengan Kedisan, baik secara birokrasi maupun politik.
Permintaan penduduk Buahan disetujui, kemudian diabadikan dalam prasasti untuk dijaga sebagai ketetapan hukum yang sah dan mengikat. Prasasti tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk Buahan kepada raja, termasuk ketetapan tentang batas-batas desa.
Berselang 31 tahun setelah turunnya prasasti kelompok pertama, Desa Buahan kembali dianugerahkan dua buah lempeng prasasti. Kali ini yang memerintah Bali adalah Sri Dharmawangsawardhana Marakatapangkaja Sthanotunggadewa, putra kedua Sri Udayana-Mahendradatta. Prasasti itu berangka tahun 947 Saka (1025 Masehi), hari Panglong Kedua, bulan Palguna (Sasih Kawulu: antara bulan Februari-Maret) yang bertepatan pada hari Tungleh, Anggara Pahing Madangkungan. Inilah Prasasti Buahan B.
Peristiwa yang ditatah di atas lempeng tembaga berdimensi 33 x 14 cm itu sama pentingnya dengan kelompok prasasti pertama. Pada waktu itu, penduduk Buahan mengajukan permohonan untuk membeli hutan perburuan raja.
Pembelian hutan seluas 900 x 1100 depa ini bermotif ekonomi. Hutan dibeli untuk memperluas ruang gerak penduduk dalam memenuhi kebutuhan pakan sapi dan kayu bakar. Apabila dibaca dalam lanskap politik masa kini, kita bisa meraba keberanian penduduk Buahan kuno seribu tahun yang lalu untuk berinvestasi demi memperkuat ekonomi rakyat.
Hutan yang dibeli dari raja seribu tahun lalu masih ada dan terjaga dengan baik hingga saat ini. Menurut tetua desa, di hutan adat inilah mereka berburu kijang untuk kurban ritual tahunan di salah satu pura di Desa Buahan. Upaya perlindungan terhadap hutan tersebut dikukuhkan dalam aturan adat yang melarang warga melakukan eksploitasi berlebihan terhadap hutan. Hutan disakralkan sebab di dalamnya terdapat beberapa situs penting seperti Pura Jero Ratu dan Pura Suci.
Hari Tungleh, Anggara Wage Pahang, Panglong Kelima, bulan Kartika (Sasih Kapat: antara bulan Oktober-November) 1068 Saka (1146 Masehi), tetua dari tiga desa di tepi danau (Kedisan, Buahan, dan Air Abang) menghadap Sri Maharaja Sri Jayasakti. Namanya masing-masing adalah Bapa Ni Purnajiwa, Bapa Ni Sribuddhi, dan Bapa Ni Buddhisara. Mereka menuntut ketegasan negara untuk menghadirkan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban penduduk dan warganya, sebagaimana ketetapan yang sebelumnya telah berlaku di desa masing-masing.
Permohonan dari ketiga desa dibalas melalui ketetapan yang diabadikan di atas lempeng tembaga berdimensi 39 x 7,5 cm. Sri Jayasakti menetapkan berbagai tindakan yang boleh-tidak boleh maupun harus-tidak harus dilakukan penduduk di tiga desa tepi danau tersebut. Salah satu ketetapannya adalah mengizinkan pemanfaatan beberapa jenis pohon, terutama pohon kemiri untuk membuat perahu. Demikianlah isi Prasasti Buahan C yang berjumlah empat buah lempeng, dengan rata-rata di setiap lempengnya tertatah enam baris.
Dua kelompok prasasti paling muda diturunkan pada tahun 1103 Saka (1181 Masehi). Tanggalnya sama, yakni pada hari Maulu, Buda Paing Wayang, Pananggal Kesembilan, bulan Srawana (Sasih Kasa: antara bulan Juli-Agustus). Prasasti yang ditatah sangat indah dalam lempengan tembaga berukuran 38,5 x 8 cm dan 42 x 9,5 cm itu dikeluarkan oleh Maharaja Sri Haji Jayapangus.
Kelompok prasasti berukuran 38,5 x 8 cm–dikenal sebagai Prasasti Buahan D–diturunkan untuk penduduk Desa Jhuharan. Sementara itu, kelompok sisanya–dikenal sebagai Prasasti Buahan E–diturunkan untuk Desa Buahan. Apakah Jhuhuran dan Buahan adalah komunitas adat yang sama? Perlu penelusuran lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan ini.
Menariknya, penulisan gelar Sri Haji Jayapangus dan kedua permaisurinya di dalam dua kelompok prasasti ini sedikit berbeda, meskipun secara makna masih sejalan. Prasasti Buahan D menulis Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkaja Cihna, dengan permaisurinya masing-masing adalah Bhatari Sri Parameswara Indujalancana dan Sri Mahadewi Sasangkajaketana. Sementara itu, pada Prasasti Buahan E gelar raja ditulis Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkaja Lancana dengan dua orang permaisurinya: Bhatari Sri Parameswari Indujaketana dan Sri Mahadewi Sasangkajacihna.
Terlepas dari perbedaan penulisan gelar, kedua prasasti menegaskan ketokohan Sri Haji Jayapangus sebagai tokoh historis, bukan tokoh fiksi-mitologis. Jayapangus tegas dicatat sebagai seorang pemimpin agung yang banyak melahirkan kebijakan strategis berdampak positif bagi rakyat. Jayapangus bukan seorang pendusta yang mengkhianati perkawinan untuk sekadar bermain serong dengan wanita lain hingga dikutuk hangus menjadi abu.
Dua Prasasti Buahan itu bersaksi bahwa Sri Haji Jayapangus adalah pemimpin yang telah memahami intisari ajaran Manawakamandaka. Paduka Maharaja yang bijak telah memutus kegalauan hati rakyat yang terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum. Kekacauan yang sangat mungkin disebabkan oleh para politisi culas yang mengangkangi konstitusi.
Jayapangus setidaknya mengeluarkan 44 kelompok prasasti selama memerintah. Arkeolog, Semadi Astra, berpendapat bahwa prasasti-prasasti yang dikeluarkan Sri Haji Jayapangus dilatarbelakangi oleh banyaknya perselisihan penduduk desa sebagai wajib pajak dengan pihak-pihak yang berkewajiban menunaikan dan mengelola drwyahaji (pendapatan negara dari pajak, cukai, iuran, dsb.). Petugas mungkin telah memungut drwyahaji melebihi ketetapan yang ada. Kemelut yang diduga telah terjadi sebelum Jayapangus memerintah (Astra, 2023)2.
Menurut penjelasan prasasti-prasasti itu kita jadi sedikit paham tentang ketokohan Sri Haji Jayapangus sebagai raja agung (mahāraja). Kebijakan pro rakyat itulah yang sekiranya dikenang dan membekas dalam ingatan masyarakat hingga kini, yang menjelma dalam tradisi tulis, tradisi lisan, situs, maupun ritus. Maka, bukan suatu yang berlebihan jika ada masyarakat yang marah ketika tokoh yang mereka sangat hormati dinarasikan sungsang.
Menjaga untuk Dijaga
Warga Desa Adat Buahan memandang Prasasti Buahan bukan semata tinggalan historis. Secara turun-termurun, fisik maupun narasi prasasti telah dimaknai sebagai pelita hidup yang turut membentuk karakter dan identitas orang Buahan.
Pemuliaan masyarakat adat terhadap lempeng-lempeng prasasti itu dapat dimengerti melalui gelar yang disematkan, yakni Ida I Ratu Pingit atau Bhatara Pingit. Frase ida i ratu maupun bhatara sama-sama merujuk pada ‘beliau yang mulia’. Sementara itu, kata pingit dapat berarti ‘rahasia’, ‘sakral’, atau ‘keramat’.
Penyebutan Ida I Ratu Pingit atau Bhatara Pingit kepada lempeng-lempeng tembaga itu menegaskan posisi prasasti di dalam semesta paling sakral orang Buahan. Gelar itu adalah bukti ketundukan hati orang Buahan terhadap entitas yang dianggap mulia, agung, dan kudus. Lempeng-lempeng prasasti itu secara spiritual diyakini sebagai penjelmaan dari spirit suci yang telah, sedang, dan akan tetap melindungi tanah Buahan beserta isinya.
Wujud fisik Ida I Ratu Pingit diperlakukan sangat khusus. Prasasti hanya diturunkan setahun sekali pada tengah malam Purnama Jyestha. Otoritas yang memiliki kewenangan untuk menurun-naikkan hanyalah pimpinan adat tertinggi: Jero Kubayan. Setelah prasasti turun, warga adat menyambut suka-cita dengan iring-iringan gong bak karnaval yang memecah keheningan malam.
Saat puncak upacara, lempeng-lempeng tembaga itu akan dibersihkan. Ritual itu disebut ngangsih [ngangsuh?]. Ngangsih hanya boleh dilakukan oleh Jero Kubayan didampingi Jero Bahu dan/atau orang-orang dengan izin khusus. Sementara Jero Kubayan melaksanakan ngangsih, penduduk desa akan duduk khusuk di penataran pura, menyuarakan kidung puja-pujian, serta menabuh gamelan gong gede dan salunding.
Ritual ngangsih dilakukan selayaknya memandikan dan menghias seorang manusia. Selain air, ngangsih melibatkan piranti berupa bedak dan wangi-wangian. Setelah diberi bedak dan wewangian, lempengan disisir dan dicermini dengan janur berbentuk khusus. Proses akhir adalah mempersembahkan kukus arum (asap dari pembakaran cacahan kayu sakti, cendana, majagau, dan menyan).
Selama Ida I Ratu Pingit dipersembahkan upacara, penduduk Buahan wajib menjaga sikap. Penduduk tidak boleh tidur di ranjang. Mereka akan tidur di lantai dalam kesederhanaan. Mereka tidak boleh memanjat pohon, karena dipandang dapat mencederai kemuliaan Ida I Ratu Pingit. Apabila pantangan-pantangan itu dilanggar, mereka meyakini akan tertimpa kemalangan.
Tetua Buahan juga meyakini Prasasti Buahan sebagai tanda (cihna) kemakmuran. Sepanjang identifikasi yang pernah dilakukan, seluruh prasasti berjumlah 23 lempeng. Namun, menurut penuturan Jero Kubayan dan tetua desa yang lain, setiap tahun jumlah yang turun selalu berubah-ubah. Pernah ditemukan hanya belasan lempeng, padahal sudah dicari-cari dengan teliti. Pernah pula turun lebih dari jumlah yang seharusnya. Fenomena itu memunculkan pandangan bahwa semakin banyak prasasti yang “berkenan” turun, maka setahun ke depan tanah akan semakin subur, danau akan penuh ikan, bencana pun akan terhindarkan dari desa.
Apabila dibaca dalam konteks ekologis, Prasasti Buahan adalah sempadan terakhir yang menjaga ketahanan lanskap lingkungan Desa Buahan, khususnya hutan. Lewat asuhan ketaatan dan ketakutan atas kutukan leluhur, pohon-pohon di hutan adat Buahan bisa hidup tanpa was-was sampai saat ini. Ini adalah refleksi penting untuk meruwat pemahaman kita tentang tata kelola lingkungan berbasis masyarakat adat di tengah narasi keambrukan ekologi dunia.
Pada titik ini, kita yang masih memerlukan air dan udara bersih sesungguhnya wajib berterima kasih dan belajar pada Buahan. Mereka adalah salah satu yang masih setia menjaga jantung Pulau Bali untuk tetap berdenyut dan menghidupi.
_____
1Tulisan ini memilih menggunakan kata “buahan” untuk menggantikan kata “bwahan” yang terbaca pada prasasti maupun tulisan-tulisan dari para pakar terdahulu. Dasar pertimbangannya adalah ejaan penulisan latin bahasa Bali modern serta penulisan nama Desa Buahan yang resmi dipakai desa setempat.
2Astra, I Gde Semadi. (2023). Birokrasi Kerajaan Bali Kuno Abad XII-XIII. Pustaka Larasan
3Pembahasan bagian ini diolah dari kajian alih aksara dan alih bahasa Putu Budiastra berjudul Prasasti Bwahan, Kintamani-Bangli terbitan Museum Bali (1978) yang diperkaya dengan hasil observasi langsung terhadap Prasasti Buahan pada 13 Mei 2025.
==================================
*I Ketut Eriadi Ariana (Jero Penyarikan Duuran Batur) adalah dosen Sastra Jawa Kuno Universitas Udayana. Pemuda asli Batur ini sejak akhir 2019 mengemban tugas spiritual-kultural sebagai jero penyarikan duuran (sekretaris adat) di Pura Ulun Danu Batur/Desa Adat Batur. Tertarik pada isu-isu kebudayaan dan ekologi. Menulis buku Ekologisme Batur (2020), buku antologi puisi Bali modern Ulun Danu (2019), dan sejumlah buku karya bersama.