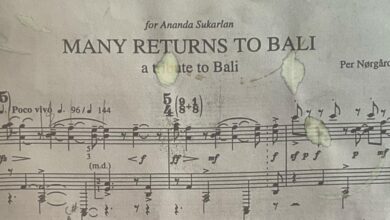JIKA sejarah adalah museum gagasan, maka salah satu artefak paling purba di dalamnya adalah hasrat manusia akan “kebenaran”—bukan sebagai fakta objektif, tetapi sebagai pengalaman yang menenangkan. Kenyataan ini menyingkap paradoks yang mengganggu: otak manusia, sebagaimana tubuhnya yang berevolusi, tidak didesain untuk membedakan benar dan salah, melainkan untuk bertahan hidup. Bahkan lebih dari itu: untuk merasa nyaman.
Yuval Noah Harari, dalam Sapiens, menggarisbawahi bahwa spesies manusia bertahan bukan karena ia mengetahui kebenaran, melainkan karena ia mampu menciptakan dan mempercayai fiksi kolektif. “Homo sapiens menaklukkan dunia berkat kemampuannya bercerita.” Di sinilah kita mendapati asal-muasal dari authority-based truth—sebuah kebenaran yang tidak bersandar pada fakta, melainkan pada siapa yang mengatakannya. Dalam masyarakat pramodern, kebenaran datang dari kepala suku, dari para dukun, dan pemimpin. Dalam masyarakat modern, dari akademisi, tokoh publik, atau influencer. Yang berubah hanya nama dan panggung, bukan pola kerjanya.
Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions bahkan menyatakan bahwa ilmu pengetahuan pun tidak kebal terhadap pola ini. Ia tumbuh dalam kerangka paradigma—kerangka yang tidak selalu benar, tetapi dominan. Perubahan paradigma bukan terjadi karena kebenaran baru menggantikan yang lama, tetapi karena komunitas ilmiah mulai merasa paradigma lama tidak lagi memuaskan rasa ingin tahu mereka. Kebenaran pun tunduk pada rasa puas, bukan pada logika yang murni.
Pertanyaannya: mengapa rasa puas begitu menentukan? Karena otak kita, seperti dikatakan oleh Antonio Damasio, bekerja bukan hanya berdasarkan logika, melainkan emosi. Dalam Descartes’ Error, Damasio menunjukkan bahwa pengambilan keputusan manusia sangat dipengaruhi oleh “somatic markers”—reaksi emosional yang tertanam dalam tubuh. Artinya, keputusan kita tentang apa yang kita anggap benar atau salah seringkali lebih menyerupai pilihan estetika daripada penalaran rasional. Kita menyukai kebenaran yang terasa “indah”, “masuk akal”, dan “menghibur”—walau tidak benar.
Bayangkan pertanyaan sederhana: Kenapa langit berwarna biru? Di masa lalu, jawabannya bisa saja: karena kentut dewa laut. Hari ini, jawabannya: karena hamburan Rayleigh. Namun apakah jawaban yang “ilmiah” ini lebih banyak dipercayai? Belum tentu. Teori konspirasi, mitos spiritual, dan narasi mistik masih lebih menarik bagi banyak orang, karena memberikan rasa nyaman, rasa makna, dan—yang terpenting—rasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri.
Michel Foucault dalam Power/Knowledge mengungkap bahwa pengetahuan tak pernah bebas dari kekuasaan. Yang kita sebut kebenaran sesungguhnya adalah hasil dari relasi kuasa yang bekerja di dalam masyarakat. Kebenaran adalah produk dari institusi, norma, dan bahasa yang mengatur wacana. Jadi ketika kita bertanya “apa yang benar?”, seringkali yang kita maksud sebenarnya adalah “apa yang disahkan oleh otoritas sebagai benar?”. Maka pengetahuan ilmiah pun kerap bersandar pada kredibilitas institusi—bukan pada kekuatan buktinya.
Lebih mencemaskan, dalam era digital hari ini, kita menyaksikan banalitas baru dalam konsumsi pengetahuan. Internet tidak mengangkat kebenaran, ia mempercepat sirkulasi narasi yang memuaskan. Mesin pencari bukan alat penemuan kebenaran, melainkan cermin dari hasrat mayoritas. Algoritma dirancang bukan untuk menilai benar atau salah, tapi untuk mengoptimalkan atensi dan retensi. Dan atensi manusia, sebagaimana diungkapkan oleh Nicholas Carr dalam The Shallows, semakin tergoda oleh yang dangkal dan menghibur.
Lalu, jika benar dan salah bukanlah kompas alami otak manusia, mungkinkah kita mendesain ulang cara berpikir kita? Atau justru kita harus menerima bahwa pengetahuan bukan soal “fakta” melainkan soal “fungsi”? Seperti yang pernah dikatakan oleh William James, “Kebenaran adalah apa yang terbukti berguna dalam cara berpikir kita.” Dengan kata lain, kebenaran adalah soal kegunaan—bukan kepastian.
Inilah tawaran pemikiran alternatif yang patut direnungkan: bahwa mungkin sudah waktunya kita meninggalkan model pengetahuan sebagai “cermin realitas” dan mengadopsi model pengetahuan sebagai “alat evolusioner”. Kebenaran bukan cermin, tapi alat—ia penting sejauh ia membuat kita hidup lebih baik, lebih selamat, dan mungkin, lebih bahagia. Namun konsekuensinya adalah kita harus belajar hidup dalam ketidakpastian, dan itu menuntut kedewasaan berpikir yang tidak semua orang siap memikulnya.
Di titik ini, pertanyaan tentang benar dan salah berubah bentuk. Ia bukan lagi soal fakta, tapi tentang keberanian: berani berpikir melampaui naluri purba otak kita yang hanya ingin merasa nyaman. Dan mungkin, disitulah letak kemanusiaan kita yang sejati.
Dengan segala kebanggaan manusia atas rasionalitasnya, barangkali ironi terbesar dari zaman kita adalah bahwa kebenaran masih ditentukan oleh rasa puas, bukan oleh bukti. Kita lebih memilih yang terdengar meyakinkan ketimbang yang terbukti benar. Kita lebih nyaman percaya bahwa dunia berjalan sesuai narasi yang sudah kita kenal, daripada membuka diri terhadap kenyataan yang barangkali mengguncang fondasi keyakinan kita.
Maka pertanyaan penting yang mesti diajukan bukan lagi: Apa yang benar? Melainkan: Apa yang kita cari dari kebenaran itu sendiri? Apakah kita sungguh ingin tahu, atau hanya ingin dibenarkan? Apakah kita menginginkan kebenaran sebagai cahaya, atau sebagai selimut? Jika otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan benar dan salah, lalu bagaimana kita akan hidup secara etis di dunia yang semakin kompleks? Bagaimana kita akan mendidik generasi yang mampu berpikir kritis, bila sistem sosial, media, dan bahkan pendidikan lebih sering merayakan kenyamanan intelektual daripada keberanian untuk meragukan?
Di sinilah setiap individu dihadapkan pada tanggung jawab eksistensialnya: mengubah cara berpikir tidak cukup dilakukan dengan menambah informasi, tetapi dengan menata ulang relasi kita terhadap kebenaran itu sendiri. Kita harus belajar memelihara ketidaknyamanan, menjinakkan ego, dan menjadikan keraguan sebagai awal pencarian, bukan akhir dari kepastian. Karena mungkin, sebagaimana diungkapkan oleh Søren Kierkegaard, “Kebenaran itu selalu subjektif—karena yang terpenting bukan apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita menghidupi pengetahuan itu.”
Kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya bebas dari bias otak purba yang lebih suka narasi yang menyenangkan daripada yang akurat. Tapi mungkin, kesadaran akan keterbatasan inilah yang bisa menjadi awal dari kemajuan sejati. Kemajuan yang tidak didasarkan atas ilusi bahwa kita pasti tahu apa yang benar, melainkan atas kerendahan hati untuk terus bertanya, menggugat, dan membuka ruang baru bagi makna yang lebih dalam.
Dan pada akhirnya, dalam hidup yang fana dan dunia yang terus berubah, barangkali pertanyaan yang paling manusiawi bukanlah “Apa yang benar?”, tapi “Apa yang akan aku lakukan dengan apa yang aku anggap benar?” Sebab hanya di situlah, kebenaran menjelma menjadi tindakan—dan tindakan, menjadi kehidupan. (*)
Fileski Walidha Tanjung adalah seorang penulis kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis esai, puisi, dan cerpen di berbagai media nasional.