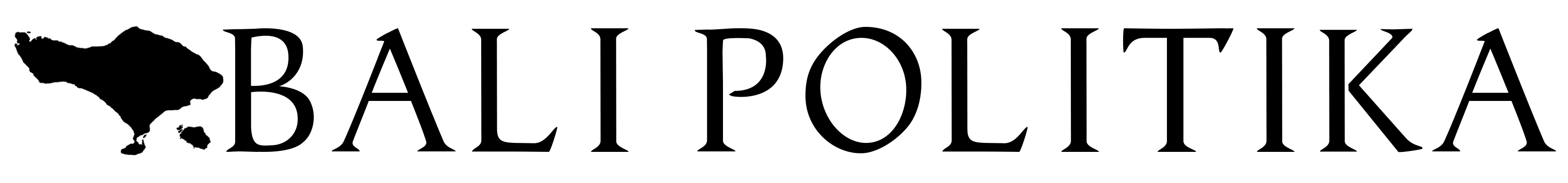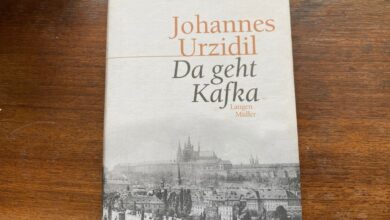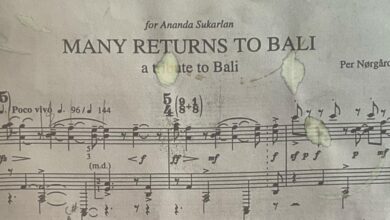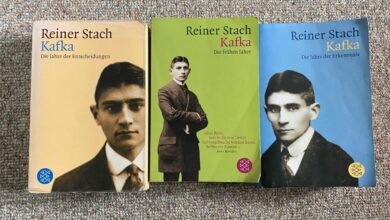PRIVATISASI lahan adat menjadi persoalan yang mengkhawatirkan bagi Bali. Seiring derasnya kucuran kapital—terutama yang digandeng pariwisata—narasi tentang ruang publik (baca: adat) yang lenyap semakin sering terdengar.
Kita bisa bercermin melalui beberapa kasus yang muncul ke gelanggang publik pada awal tahun 2025. Dugaan upaya privatisasi kawasan pesisir Pulau Serangan adalah salah satunya. Isu ini mungkin tidak akan pernah mendapat atensi berbagai kalangan jika tidak viral di media sosial. Kebetulan juga dalam waktu bersamaan ada isu nasional senada, yakni “pagar laut hantu” di Tangerang, Banten.
Setelah viral, beberapa keberatan masyarakat Serangan konon telah diakomodir pengembang. Namun, saya kira akar persoalannya belum sepenuhnya terurai. Perkara ini masih berpeluang berputar pada lingkaran setan yang sama di kemudian hari.
Pada bulan Februari 2025, 160 orang warga adat Jimbaran dikabarkan berjuang merebut tanah adatnya. Mereka yang menghimpun diri dalam Kesatuan Penyelamat Tanah Adat (Kepet Adat) Jimbaran mendatangi DPRD Bali dan menggugat PT Jimbaran Hijau. Mereka menuding perseroan melakukan penguasaan terhadap tanah adat yang konon laba Pura Ulun Swi Jimbaran.
Kasus ini memang samar-samar terdengar. Bahkan seperti pepatah, “anget-anget tahi ayam”. Tidak banyak tokoh publik atau lembaga pers mengawal kasusnya—seperti kasus Kura Kura Bali. PT Jimbaran Hijau pun sempat menampik tuduhan Kepet Adat Jimbaran pada sejumlah media massa. Setelah itu, kasus ini tidak lagi terdengar. Seolah menguap begitu saja.
Terlepas dari kesimpangsiuran kasus tersebut, klaim Kepet Adat Jimbaran bisa menjadi cermin paling mutakhir atas realitas Bali saat ini. Apabila Kepet Adat Jimbaran benar, perkara ini bukan hanya penting bagi warga Jimbaran atau masyarakat Badung, tetapi masalah serius bagi orang Hindu Bali secara umum. Sekali lagi, kasus ini bisa menjadi cermin tentang betapa rentannya masyarakat adat Bali kehilangan properti adatnya. Properti tempat orang Bali untuk terhubung dengan pemilik Semesta. Itu tentu merupakan jati diri, harga diri, dan kemegahan terakhir orang Bali!
Tanah Laba dan Eksistensi Adat Bali
Prinsip dasar properti adat adalah kepemilikan bersama oleh anggota adat. Properti ini diwariskan sebagai sumber daya untuk merawat adat-budaya. Maka, apabila sumber daya tersebut “dirampas” dari pewarisnya, sesungguhnya benteng kebudayaan Bali telah runtuh sepenuhnya. Adat akan semakin tidak berdaya. Kemandirian desa adat pun hanya ilusi.
Lahan adat di Bali dikenal sebagai tanah laba desa atau laba pura. Tanah laba desa atau pura itu umumnya dimanfaatkan untuk penyokong pelaksanaan segala macam ritual adat.
Secara esensial tidak ada ritual yang hadir untuk membebani warga. Upacara hadir justru sebagai momentum mengucapkan terima kasih atas segala keberlimpahan. Dalam hal ini, properti adat inilah yang semestinya dikelola untuk memenuhi kebutuhan kultural itu. Bahkan, dalam banyak desa tanah laba dikelola sebagai insentif bagi warga adat, terutama untuk prajuru dan krama ngarep.
Keberadaan tanah laba desa atau laba pura dapat menjadi salah satu indikator menelusuri jejak historis dan kedudukan desa atau pura di panggung kultural. Semakin luas laba desa yang dimiliki, kedaulatan dan kemandirian desa bersangkutan di masa lalu bukanlah mitos. Demikian pula keberadaan laba pura. Semakin luas laba pura, semakin penting posisi pura itu bagi umat. Semakin luas pengaruh pura di masyarakat.
Duwe Ida Bhatari Batur
Kepemilikan laba ini terang ditemukan di Desa Adat Batur. Selain memiliki kawasan permukiman adat, Batur memiliki properti berupa laba desa yang tersebar di beberapa tempat, seperti di wilayah Banjar Toya Mampeh, Bubungkelambu, Seked-Toya Bungkah, dan Taksu.
Laba desa di Banjar Toya Mampeh merupakan kawasan produktif pertanian yang secara khusus difungsikan untuk insentif masyarakat adat. Lahan-lahan di kawasan tersebut dibagi-bagi dalam beberapa petak yang dikenal sebagai bija atau sikutan. Lahan bija atau sikutan ini berhak dimanfaatkan oleh masyarakat adat yang telah matakaturun dan menjalankan kewajiban ngayah dalam kelompok-kelompok profesional adat (tempekan).
Selain diberikan kepada warga adat, sejumlah lahan sikutan di Yeh Mampeh juga diberikan kepada pejabat adat: jero gede, jero balian, jero penyarikan, jero mangku, dan jero kraman. Luas lahan sikutan ditentukan melalui besar-kecilnya tanggung jawab adat. Dalam hal ini Jero Gede Batur mendapat sikutan terluas.
Hak pengelolaan sikutan berbasis pada jabatan, bukan pada individunya. Artinya, ketika seseorang tidak lagi menjabat, maka yang bersangkutan dan/atau keluarganya otomatis kehilangan hak atas pengelolaan lahan. Selanjutnya, hak pengelolaan sikutan akan jatuh kepada pejabat yang sedang aktif.
Selain keberadaan sikutan di dalam wilayah adat Batur, Pura Ulun Danu Batur juga memiliki lahan adat di luar wilayah Desa Adat Batur. Tanah laba ini secara umum dikenal sebagai tanah duwe (milik) Ida Bhatari Batur.
Lahan duwe Ida Bhatari misalnya terletak di Sidembunut dan Penida Kaja. Tanah-tanah duwe itu sampai sekarang digarap oleh warga setempat secara turun-temurun. Sebagai gantinya, penggarap akan mempersembahkan hasil panen dengan besaran yang telah disepakati dengan Desa Adat Batur setiap tahunnya.
Ada beberapa ciri duwe Ida Bhatari Batur, antara lain ditandai dengan keberadaan batu lava (batu bulitan atau rejeng) dan hidupnya pohon jepun Bali (kamboja putih) di ulun carik–nya. Batu dan pohon kamboja itu biasanya dijadikan medium pemujaan Ida Bhatari Batur
Tanda ini dapat ditemui pada sejumlah pura masceti, ulun swi, dan sejenisnya yang berorientasi ke Pura Ulun Danu Batur. Contohnya bisa ditemui di Pura Batur Sari Tebesaya, Peliatan, Ubud. Dalam katalog daftar Pasihan Ida Bhatari Batur, pura ini teregister sebagai Pura Ancut Batur Gunung Majalan, Peliatan. Panyungsung pura setempat meyakini hubungan Ida Bhatari Batur dengan pura tersebut, yang ditandai dengan ketaatan datang setiap Ngusaba Kadasa dan nangkilang Ida Bhatara Pura Batur Sari dalam periode beberapa tahun sekali.
Konsep Pasihan Bhatari Sakti Batur yang menciptakan hubungan antara masyarakat subak dengan Pura Ulun Danu Batur kemungkinan berakar dari keberadaan lahan duwe di kawasan anggota pasihan. Hal ini bisa dilihat dari keterangan Rajapurana Batur yang mengamanatkan anggota pasihan untuk mengingat (ngelingang) duwe Ida Bhatari Batur.
Pengingat Ida Bhatari Batur pada anggota pasihan ditunjukkan melalui praktik persembahan sarin tahun (suwinih) setiap Ngusaba Kadasa. Konsep inilah yang kemungkinan menyebabkan besaran suwinih yang dikenakan kepada setiap anggota pasihan berbeda-beda, meskipun kadang letaknya bersebelahan.
Penjelasan teks Pangaci-acin Ida Bhatara Rajapurana Batur menjadi contoh nyata konsep ini. Misalnya pasal yang mencantumkan pengingat bagi Desa Apuan dan Desa Bangunlemah yang disebut mengelola (nguningang) duwe Ida I Ratu Sakti di Sinarata sebesar 10 tenah. Sebagai ganti pengelolaan duwe, kedua desa dikenai beras pajeg sejumlah 50 ceeng tembaga saban Ngusaba Kadasa.
Sinarata adalah nama arkais dari Batur selain Tampurhyang. Maka, Ida I Ratu Sakti di Sinarata sama dengan Ida Bhatara Sakti Batur, dalam hal ini merujuk pada entitas Ida I Ratu Sakti Madue Gumi ‘Beliau yang Mulia Pemilik Bumi’.
Kutukan bagi “Perampok” Duwe Desa
Teks Gama Patemon Rajapurana Batur—menurut penulis teks ini lebih cocok diberi judul Gaman Ida I Ratu Gde Makulem—memuat narasi penting pengelolaan duwe Ida Bhatari Batur. Gama Patemon adalah teks yang banyak mangatur tatanan adat, satu di antaranya terkait kewajiban dan hak tetua desa.
Pada halaman 32b teks lontar tersebut dijelaskan keberadaan lahan adat di Yeh Mampeh, Tegal Sapura, dan Tukad Malilit. Adapun lahan yang terletak di Tukad Malilit dan Tegal Sapura diwacanakan sebagai hak bagi Dane Baliwayah.
Dane Baliwayah dijelaskan sebagai pejabat yang telah melaksanakan ritual diksa Ida Ratu Makulem (Tukad Malilit, Tgal Sapura laban anak sampun madiksa ring I Ratu Makaulem, aja nglambuk). Ritual inisiasi ini juga dikenal sebagai munggah makraman. Secara khusus, Dane Baliwayah yang dimaksud di dalam teks tampaknya merujuk pada Dane [Jero] Kubayan dan Dane [Jero] Bahu.
Apabila ada masyarakat yang belum melaksanakan ritual munggah makraman berani merebut pengelolaan terhadap lahan-lahan tersebut, teks menulis bahwa yang bersangkutan akan terkena kutukan dari dewa dalam manifestasinya sebagai Ida I Ratu Makulem. Kutukan itu pun berlaku bagi mereka yang sudah menjabat, tetapi belum melaksanakan upacara munggah makraman. Inisiasi dari pejabat yang “rakus itu” akan dianggap gagal (tan sadya sira kneng pastun Ida I Ratu Makulem, urung kang pugala).
Kutukan bagi pencaplok lahan adat yang bukan haknya memang tidak dinyatakan secara terang di dalam teks. Namun, apabila kita periksa model kutukan pada bait-bait di dalam Gama Patemon, sanksi bagi pelanggar ketetapan dapat berupa hukuman jasmani maupun rohani.
Sanksi jasmani misalnya berupa pemecatan secara tak hormat dari jabatan publik sekaligus dihinakan secara sosial (kukurangan jerih arannya) atau diusir tinggal ke luar mandala inti permukiman (wanrah ka jaba bubung). Namun demikian, ada pula sanksi berupa kutukan rohani seperti jauh dari kesejahteraan lahir-batin (kurang pangan kurang kinum, tan metwa sira ring kakadenta), terkena penyakit menahun (sangkala sira, gring sire ta kita, warsa gringan), pendek umur (putusakna sumusup kita ring pastu, pastu ika kang abas paku, tebteb tihing aud kelor), hingga kelahiran hina pada kehidupan berikutnya (dadi kita namu-namu, mendem-medep).
Pengingat
Apa yang disuratkan Gama Patemon terkait dengan kutukan bagi perampas lahan adat adalah alarm bagi kita untuk berhati-hati dalam mengelola milik publik. Kehati-hatian ini berlaku dua kali lipat bagi pejabat publik yang telah dipercaya oleh rakyat!
Kehati-hatian ini tidak terlepas dari posisi pejabat publik yang secara prinsip memiliki piranti lebih kompleks dalam menentukan masa depan suatu komunitas. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemimpin menimbulkan risiko berkali-kali lipat dari tindakan rakyat biasa. Satu kebijakan positif dapat mengantarkan pemimpin menerima pahala segunung. Namun, jika pejabat main serong, negara akan bubar. Rakyat pun akan binasa.
Gama Patemon mengingatkan adanya kepastian hukum yang melindungi hak rakyat. Ada beragam sanksi yang bisa diambil untuk menghukum pelanggar ketetapan. Sanksi dapat ditentukan dari kecil-besarnya pelanggaran yang dilakukan.
Apabila segala upaya jasmani (sakala) telah diusahakan tetapi belum berhasil memberi efek jera, teks memberi garansi “pergerakan” Hakim Agung sebagai pengadil terakhir yang pasti mengikat. Ketika taring hukum sakala tumpul, etika publik dikangkangi, seruan rahib-rahib suci dijadikan keset peradaban, rakyat jangan padam harapan!
Semesta tak pernah tidur! Perampas hak rakyat akan menerima balasan setimpal, di kehidupan ini atau di kehidupan mendatang. Demikian Gama Patemon memberi jaminan kepada kita.
=====
*I Ketut Eriadi Ariana (Jero Penyarikan Duuran Batur) adalah dosen Sastra Jawa Kuno Universitas Udayana. Sejak akhir 2019 mengemban tugas spiritual-kultural sebagai jero penyarikan duuran (sekretaris adat) di Pura Ulun Danu Batur/Desa Adat Batur. Tertarik pada isu-isu kebudayaan dan ekologi. Menulis buku Ekologisme Batur (2020), buku antologi puisi Bali modern Ulun Danu (2019), dan sejumlah buku karya bersama.