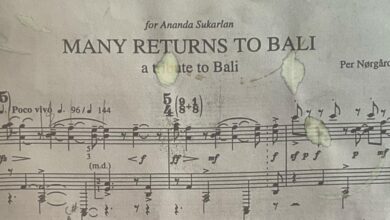PENDIDIKAN KARAKTER menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan nasional Indonesia. Sejak kemerdekaan, sistem pendidikan Indonesia merancang kurikulum untuk menumbuhkan karater bangsa Indonesia. Perubahan dan pebaikan kurikulum dari waktu ke waktu dilakukan untuk menemukan formula yang tepat hingga kurikulum yang terakhir diimplementasikan yakni Kurikulum Merdeka. Bahkan di dalam Kurikulum Merdeka secara eksplisit memuat komponen Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang tujuannya untuk memperkuat karakter siswa Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Namun kenyataan yang terjadi beberapa tahun terakhir, karakter siswa tidak menjadi lebih baik justru menunjukan sebaliknya. Jika koruptor boleh dipakai sebagai contoh hasil pendidikan karakter, maka mereka yang koruptor saat ini tiada lain merupakan produk dari pendidikan dua puluh hingga tiga puluh tahun yang lalu. Lalu karakter seperti apa yang ingin dihasilkan dari sistem pendidikan kita? Bagaimana cara mewujudkan pendidikan karakter yang dimaksud? Pertanyaan ini seolah tidak sungguh-sungguh direnungkan secara mendalam, meskipun regulasi pergantian menteri pendidikan berlangsung meriah dan seolah menjajikan sebuah harapan.
Mari kita menengok sejarah pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka banyak ahli pendidikan dan cendekiawan mencoba menyusun kurikulum baru yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia serta untuk melepaskan diri dari kurikulum buatan pemerintah Kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di Indonesia, pada tahun 1922 mendirikan sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa berarti tempat bermain dan belajar. Sekolah ini semula didirikan untuk menentang pemerintah Kolonial Belanda melalui pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sistem pendidikannya berorientasi pada kearifan lokal dan seni tradisi, seperti gamelan. Namun tidak sedikit yang mengkritik Ki Hajar waktu itu, karena sistem pendidikannya cenderung kejawa-jawaan atau hanya berdasarkan kearifan lokal masyarakat Jawa. Artinya pendidikan yang dibangun Ki Hajar bersifat segmentit dan kontekstual, yakni sebatas di Jawa.
Pendidikan Utuh Meliputi Logika, Etika dan Estetika
Ahli pendidikan nusantara lain bernama Driyarkara mencoba merumuskan paradigma pendidikan yang lebih universal. Menurutnya, pendidikan yang utuh meliputi tiga aspek yang harus dioptimalkan dari setiap individu. Ketiga aspek itu ialah logika, etika dan estetika. Logika dapat dimaknai sebagai aspek yang mengandalkan pemikiran logis manusia. Ilmu-ilmu yang terkait aspek ini di antaranya imu-ilmu sains dan matematika yang serba pasti, terukur serta objektif. Aspek etika erat kaitannya dengan hati nurani, empati, kepatutan, norma dan lain sebagainya. Ilmu yang terkait aspek estetika di antaranya ilmu sosial, agama, budaya dan budi pekerti.
Aspek ketiga, yakni aspek estetika. Aspek ini berkaitan dengan keindahan, harmoni, dan olah rasa. Ilmu-ilmu yang terkait aspek ini di antaranya seni dan sastra. Dari ketiga aspek ini, jika kita gunakan untuk melihat sistem pendidikan di Indonesia maka akan tampak aspek mana yang dominan. Jawabannya ialah aspek logika atau ilmu pasti yang diberi porsi banyak dalam sistem pendidikan di negeri ini. Ilmu-ilmu pasti bahkan telah mendapat stereotip sebagai indikasi kecerdasan seorang siswa di Indonesia. Stereotip itu masih berlaku hingga serakarang, bahkan penguasaan ilmu-ilmu pasti oleh siswa menjadi syarat untuk melanjutkan tahap pendidikan selanjutnya. Bagaimana implementasi aspek etika dan estetika dalam sistem pendidikan di Indonesia?
Berdasarkan pengalaman pribadi, dari ketiga aspek di atas yang paling sering diabaikan adalah aspek estetika. Aspek estetika dianggap tidak memiliki menfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu-ilmu yang terkait dengan aspek estetika pun dianggap tidak bisa dijadikan profesi untuk jaminan hidup. Padahal aspek estetika adalah aspek yang sangat penting dalam hal mengolah rasa, meningkatkan kepekaan dan mewujudkan keharmonisan. Dengan kata lain aspek estetika berkaitan langsung dengan mengolah emosi manusia hingga menerima keberagaman. Kegiatan kesenian dan sastra yang menjunjung tinggi kejujuran berekspresi, harmoni warna, harmoni nada dan harmoni gerakan dalam seni tari merupakan oleh batin yang sejati.
Sastra untuk Mengasah Etika Sekaligus Estetika
Sastra dengan ketiga genrenya: puisi, prosa dan drama, kurang mendapat porsi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Padahal pengajaran sastra memiliki peranan penting bagi masyarakat untuk belajar etika dan estetika. Karya sastra terkait erat dengan masyarakat dan kebudayaan. Sastra Indonesia dahulu bahkan bagian dari spiritual masyarakat, yakni berisi ajaran agama dan pedoman hidup, misalnya mantra, gurindam, hikayat, dan cerita rakyat lainnya yang menawarakan nilai-nilai kebaikan.
Di lain sisi, sejarah sastra Indonesia juga dikaitkan dengan politik dan ideologi. Menurut sejarawan Peter Carey, sastra dianggap lebih politis daripada ilmu sejarah. Oleh karena itu pada tahun 1972 sastra dihilangkan dari kurikulum nasional oleh Orde Baru. Hal ini sangat disayangkan karena sastra sebagai suatu ilmu semestinya dikaji dari sudut pandang akademis. Peter Carey juga menyayangkan dihilangkannya sastra dari kurikulum nasional, karena sastra selain melatih keterampilan menulis dan menambah wawasan juga dapat melatih berpikir kritis para siswa.
Dalam sastra modern, pengajaran sastra meliputi aktivitas membaca, menulis, berpikir, berekspresi, menganalisis, menginterpretasi, merefleksi, hingga puncaknya mengapresiasi sebuah karya. Pengajaran seperti ini tentu menumbuhkan karakter berpikir kreatif (creative thinking), berpikir kritis (critical thinking), keterampilan memecahkan masalah (problem solving skills), kerja sama (collaboration) dan keterampilan berkomunikasi (comunication skills) atau biasa disebut dengan 4C. Menurut para ahli, keterampilan 4C ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Dengan demikian pengajaran sastra merupakan upaya menumbuhkan pendidikan karakter secara konkret dan realistis.
Sebagai contoh ialah pengajaran puisi. Siswa selain menganalisis unsur pembangunya, juga akan tersentuh hatinya oleh amanat puisi, imaji, diksi dan rima pada puisi yang dibacanya. Begitu pula ketika siswa diminta menulis puisi, ia dengan cermat memilih kata-kata, menyusun kalimat, mempertimbankan rima dan imaji (efek bahasa) agar menarik dan memberi kesan keindahan bagi pembaca. Dengan demikian secara tidak langsung siswa belajar berpikir, berempati dan mengolah kepekaan emosinya. Karakter yang akan terbentuk dari pelajaran puisi ialah karakter yang tenang, penuh kehati-hatian, teliti, tidak mudah marah dan berbahasa lebih santun.
Begitupun dengan belajar prosa dan drama. Siswa tidak hanya diminta untuk menganalisa dan mengapresaiasi prosa, baik cerpen ataupun novel. Siswa juga akan belajar berempati terhadap tokoh-tokoh di dalam cerita, siswa belajar menemukan makna mendalam dari suatu cerita yang utuh serta siswa juga akan belajar tentang pemecahan masalah dari sebuah konflik yang ada dalam cerita. Dalam pelajaran drama, siswa tidak hanya belajar teori dan membaca naskah drama saja, melainkan harus berlatih seni peran, bekerja sama dengan teman lain (bersosialisasi dan berkoordinasi) sampai menampilkan drama sebagai sebuah seni pertunjukkan. Dalam drama siswa melatih kepercayaan diri mereka dalam berakting. Berakting berarti mengkomunikasikan karakternya melalui bahasa dan gestur di hadapan penonton. (*)