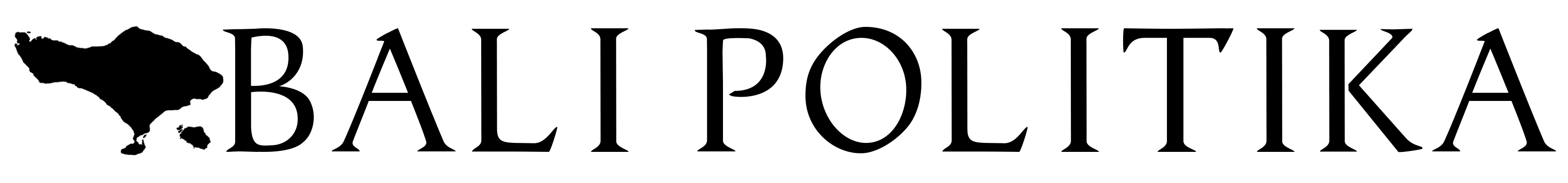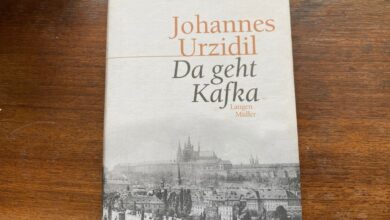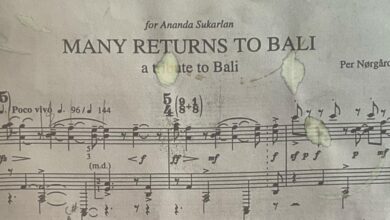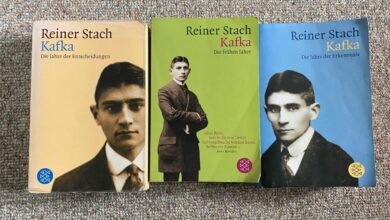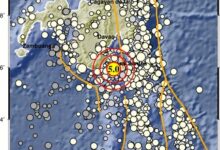DI TENGAH kemajuan teknologi dan akses informasi yang melimpah paradoks justru muncul: banyak manusia modern merasa hampa. Paradoks ini muncul dari ketidakseimbangan antara konektivitas digital yang intens dan isolasi emosional yang mendalam. Mengapa perasaan hampa bisa meluas di era ini? Jawabannya terletak pada cara hidup yang berubah drastis, hubungan yang dangkal, serta kehilangan makna hidup yang mendalam.
Pertama, kehilangan koneksi autentik. Di era digital ini, setiap orang bisa mempunyai ratusan teman bahkan ribuan di media sosial. Namun secara emosional, mereka justru lebih kesepian dari sebelumnya. Teknologi yang seharusnya bisa mempererat hubungan, justru menciptakan jarak dan perasaan hampa tiba-tiba. Contohnya, curhat kepada seseorang pun terasa berat karena adanya ketakutan akan dianggap sebagai beban. Akibatnya mereka lebih memilih curhat di dunia maya karena dirasa nyaman dan terpercaya. Padahal jika hal tersebut berlanjut secara berkala, maka tidak menutup kemungkinan akan memicu hilangnya koneksi autentik yang paling dibutuhkan untuk menjalin hubungan yang lebih nyata. Teknologi sungguh bisa membuat seseorang benar-benar merasa terhubung, padahal sebenarnya hubungan itu kosong dan tidak nyata. Sherly Turkle (2011) dalam bukunya Alone Together memberi penjelasan bahwa seseorang bisa merasa lebih “terhubung” secara digital, tapi secara emosional kering kerontang. Validasi eksternal yang diperoleh dari media sosial, tidak bisa memuaskan rasa lapar akan koneksi autentik yang sangat diperlukan untuk mencapai hubungan yang sehat dan mendalam.
Kedua, ekspektasi yang absurd. Kehidupan modern cenderung serba cepat dan kompetitif. Dari pagi hingga malam, banyak orang terjebak dalam rutinitas yang melelahkan demi mengejar kesuksesan finansial atau pengakuan sosial. Tanpa disadari, kehidupan menjadi mekanis dan terputus dari refleksi batin. Akibatnya, meskipun tujuan-tujuan materi tercapai, jiwa tetap merasa kosong karena tidak mendapatkan kepuasan emosional maupun spiritual. Tekanan untuk mencapai sukses di usia muda begitu dahsyat. Generasi Milenial dan Gen Z dituntut untuk meraih segalanya dalam waktu singkat. Mereka diharapkan bekerja keras, bahkan lembur hingga 60 jam seminggu, tetapi tetap harus menjaga kesehatan mental. Bagaimana mungkin kesehatan mental tetap stabil di tengah gempuran pekerjaan yang tak kenal lelah? Bukankah ini sebuah pertentangan yang tak masuk akal. Seperti berlari cepat, tanpa diberi kesempatan untuk bernapas. Selain tuntutan karier, ada juga tekanan memiliki tubuh ideal. Gambar-gambar tubuh yang “sempurna” menghantui dari berbagai sudut. Majalah, iklan, media sosial;— semua membombardir dengan standar kecantikan yang dianggap ideal di mata masyarakat. Jargon-jargon tentang kecantikan mulai dari kulit putih hingga bentuk tubuh yang langsing. Sudah sering kita melihat dan mendengar hal tersebut di berbagai platform berbasis internet. Gagasan-gagasan seperti ini berpotensi menuntut seseorang untuk berpenampilan sesuai standar kebanyakan, yang memungkinkan mereka dapat membenci penampilan asli. Jika hal tersebut sampai terjadi, perlahan bisa mengikis jati diri. Selain itu, adanya ekspektasi tentang menjadi ahli finansial, pandai berinvestasi, dan mengelola keuangan dengan cerdas. Padahal, banyak dari kita masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekspektasi-ekspektasi seperti ini ibarat rantai yang mengikat. Membatasi kebebasan untuk mengejar impian sesungguhnya. Menjebak seseorang dalam lingkaran setan yang tak berujung, untuk memenuhi standar yang tidak realistis. Berusaha keras untuk memuaskan orang lain, tetapi lupa mendengarkan suara hati dan kebutuhan diri sendiri. Studi dari American Psychological Association (APA, 2018) telah memaparkan bahwa salah satu sumber stres utama generasi muda adalah ekspektasi sosial yang tidak realistis. Untuk itu diperlukan cara untuk mengatasinya dengan membangun kesadaran, betapa pentingnya menerima diri sendiri apa adanya, menghargai proses di dalam hidup dan fokus pada tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dengan passion dalam diri. Jangan biarkan ekspektasi sosial mendikte hidup kita. Seseorang berhak menentukan jalan hidup mereka termasuk menetapkan standar kesuksesan sendiri. Ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah perlombaan untuk mencapai garis finis secepat mungkin, tetapi sebuah proses perjalanan hidup yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan penuh dengan pengalaman berharga.
Ketiga, over stimulasi. Seiring berkembangnya teknologi, kita sangat mudah mendapatkan rangsangan dopamin dari berbagai hal receh, seperti notifikasi aplikasi, video pendek di media sosial, atau sekadar scrolling tanpa tujuan. Akses yang instan terhadap rangsangan ini menyebabkan otak terus-menerus dibombardir oleh sensasi “reward” tanpa usaha yang berarti. Hal ini, jika terjadi terus-menerus, dapat menurunkan sensitivitas otak terhadap dopamin, yakni zat kimia yang berperan dalam sistem penghargaan dan motivasi. Sebuah studi dari Nature Neuroscience pada tahun 2016 menyatakan bahwa over stimulasi dopamin dari sumber-sumber instan berpotensi menurunkan respons alami otak terhadap kepuasan. Dengan kata lain, semakin sering kita terpapar stimulasi yang instan dan mudah didapat, semakin sulit bagi kita untuk merasa puas terhadap hal-hal yang sebelumnya terasa bermakna. Akibatnya, kita bisa kehilangan motivasi dalam melakukan aktivitas yang membutuhkan usaha dan konsistensi, seperti belajar, bekerja, atau menjalin relasi. Fenomena ini menjelaskan mengapa banyak orang saat ini mudah merasa bosan, sulit fokus, atau bahkan mengalami penurunan semangat hidup, meskipun secara fisik tidak kekurangan apa pun.
Keempat, absennya spriritualitas filosofi hidup. Tidak semua orang harus menjadi pribadi yang religius, namun setiap individu membutuhkan sistem nilai untuk memaknai hidup. Spiritualitas di sini tidak selalu berarti mengikuti ajaran agama tertentu secara ketat, melainkan mencakup kesadaran akan makna, arah, dan tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Tanpa adanya fondasi spiritual atau filosofi hidup, seseorang cenderung hidup seperti berjalan tanpa arah. Aktivitas sehari-hari terasa kosong, hubungan antar manusia kehilangan kedalaman, dan pencapaian pun sering kali tidak memberikan kepuasan batin. Viktor Frankl, seorang psikolog terkenal menyatakan bahwa penderitaan terbesar manusia adalah karena kehilangan makna hidup. Ketiadaan refleksi atas nilai-nilai hidup dapat menyebabkan kehampaan eksistensial, perasaan yang sulit dijelaskan yang bisa menurunkan kualitas hidup secara menyeluruh. Memiliki filosofi hidup, baik yang bersumber dari agama, kepercayaan pribadi, maupun pemikiran filsafat, dapat menjadi kompas moral dan emosional untuk membantu seseorang melewati fase-fase sulit di dalam hidup.
Kelima, perbandingan sosial kronis. Perbandingan sosial kronis merupakan fenomena psikologis yang sering muncul akibat penggunaan media sosial yang tinggi. Media sosial kini telah berubah menjadi semacam “etalase kehidupan” tempat orang memamerkan momen-momen terbaik mereka—liburan mewah, pencapaian pribadi, penampilan menarik, hingga kehidupan sosial yang tampak sempurna. Meskipun demikian, konten semacam ini sering kali tidak merepresentasikan kehidupan secara utuh. Akibatnya, pengguna cenderung melakukan perbandingan sosial yaitu membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih berhasil atau lebih bahagia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbandingan sosial yang intens di media sosial dapat meningkatkan risiko depresi dan kesepian. perbandingan ini bisa menjadi sangat melelahkan dan merusak apalagi jika dilakukan secara terus-menerus. Ini terjadi karena seseorang sering kali merasa tertinggal atau kurang berhasil dibandingkan dengan orang lain. Padahal, apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu mencerminkan realitas sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan media sosial dengan kesadaran dan batasan, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda dan tidak perlu dibandingkan satu dengan yang lainnya.
Perasaan hampa yang datang kepada manusia, bukanlah suatu kebetulan melainkan suatu sinyal bahwa seseorang membutuhkan arah tujuan dan kedalaman akan hidupnya. Dalam dunia yang ramai dan cepat ini, mungkin jawabannya justru terletak dalam keheningan dan kesederhanaan di dalam hidup itu sendiri.
BIODATA
Lusa Indrawati, seorang penulis yang berdomisili di Lamongan, Jawa Timur. Penulis tergabung dalam anggota komunitas Literasi Competer Indonesia, Kepul dan Negeri kertas. Beberapa karyanya termuat dalam buku antologi dan media. Selain aktif menulis, penulis juga menekuni bidang fotografi di komunitas PAC (Photography Art Community) dan IPF (Indonesia Photography Family) Jatim. Penulis bisa disapa di akun IG @indranys345