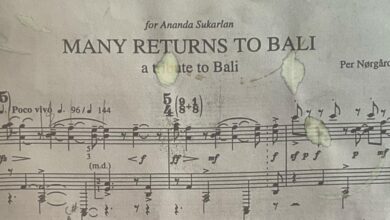DI BALIK lanskap eksotis dan citra “surga liburan” yang melekat pada Bali, tersembunyi realitas yang mengejutkan: provinsi ini mencatat tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia. Data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Bali mencatat 135 kasus bunuh diri, dengan tingkat 3,07 per 100.000 penduduk, melampaui Yogyakarta (1,58) dan Bengkulu (1,53).
Fenomena ini mengundang pertanyaan: bagaimana daerah yang dikenal dengan ketenangan dan keindahan alamnya justru menghadapi krisis kesehatan mental yang serius? Salah satu jawabannya terletak pada struktur sosial dan budaya Bali yang kompleks. Masyarakat Bali menjalani kehidupan yang sarat dengan upacara adat dan kewajiban komunal. Setiap individu diharapkan untuk aktif dalam berbagai ritual, mulai dari upacara kematian hingga perayaan keagamaan, yang seringkali memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Kewajiban ini tidak hanya membebani secara fisik dan finansial, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan.
Dalam konteks ini, konsep “libur” di Bali sering disalahartikan. Alih-alih waktu untuk beristirahat, banyak “libur” di Bali sebenarnya adalah hari-hari yang diisi dengan kegiatan adat yang wajib diikuti. Ketidakhadiran dalam upacara dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, yang berpotensi menimbulkan sanksi sosial atau bahkan pengucilan. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial ini, ditambah dengan beban ekonomi, dapat memicu stres kronis dan, dalam kasus ekstrim, keputusasaan yang berujung pada bunuh diri.
Filsuf Prancis Michel Foucault dalam karyanya “Discipline and Punish” membahas bagaimana struktur sosial dapat membentuk dan mengendalikan perilaku individu melalui mekanisme pengawasan dan norma. Dalam konteks Bali, norma sosial yang ketat dan ekspektasi komunal dapat berfungsi sebagai bentuk “pengawasan” yang menekan individu untuk mematuhi, bahkan ketika hal itu merugikan kesejahteraan pribadi mereka.
Sementara itu, di Jepang, tingkat bunuh diri mencapai 17,5 per 100.000 penduduk pada tahun 2023, dengan total 21.818 kasus. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Jepang tetap menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan mental. Budaya kerja yang menuntut, fenomena “karoshi” (kematian karena kerja berlebihan), dan tekanan sosial yang tinggi berkontribusi pada tingginya angka bunuh diri. Selain itu, sejarah budaya Jepang yang memandang bunuh diri sebagai tindakan kehormatan, seperti dalam praktik seppuku, menambah kompleksitas dalam menangani isu ini.
Perbandingan antara Bali dan Jepang menunjukkan bahwa struktur sosial dan budaya dapat memainkan peran besar dalam kesehatan mental masyarakat. Di kedua tempat, tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial dan budaya dapat menjadi beban yang berat bagi individu. Namun, pendekatan terhadap masalah ini berbeda. Jepang telah mulai mengembangkan sistem dukungan kesehatan mental yang lebih terbuka, sementara di Bali, isu kesehatan mental masih sering dianggap tabu, dan banyak kasus bunuh diri tidak dilaporkan atau dibahas secara terbuka.
Dalam menghadapi krisis ini, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Model perawatan kesehatan mental berbasis komunitas, seperti yang diterapkan di Trieste, Italia, menunjukkan bahwa integrasi sosial dan dukungan komunitas dapat efektif dalam mengurangi angka bunuh diri. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya individu dalam perawatan kesehatan mental.
Dengan demikian, perlu ada upaya untuk mereformasi struktur sosial yang menekan dan menciptakan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri tanpa takut akan sanksi sosial. Ini bukan hanya tentang menyediakan layanan kesehatan mental, tetapi juga tentang mengubah norma dan ekspektasi sosial yang dapat menjadi beban bagi individu.
Apakah mungkin kita hidup di dalam sistem yang secara tak sadar telah kita warisi dan pertahankan, meski perlahan menggerogoti ketahanan batin kita sendiri?
Kita sering terjebak dalam romantisisme kebudayaan—bahwa hidup dalam tradisi adalah hidup dalam harmoni. Namun, sebagaimana di Bali maupun Jepang, tampak bahwa tradisi, ketika tak diberi ruang dialog dan jeda, bisa menjadi beban tak kasat mata yang menghimpit. Kewajiban sosial yang tampak mulia dari luar ternyata bisa berubah menjadi tekanan batin yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Maka, sejauh mana sebuah komunitas memahami batas antara tanggung jawab kolektif dan hak individu untuk bernapas?
Jean-Paul Sartre pernah berkata, “Hell is other people.” Kutipan ini kerap disalahpahami sebagai serangan terhadap hubungan sosial. Padahal, yang ia maksud adalah bagaimana kita kerap menilai diri kita dari kacamata orang lain—dan ketika standar itu menjadi mutlak, di situlah penderitaan dimulai. Dalam masyarakat yang diatur oleh ekspektasi sosial yang ketat, seperti di Bali atau Jepang, ruang bagi individu untuk sekadar menjadi diri sendiri menjadi semakin sempit.
Namun, kita tak bisa serta-merta menyalahkan tradisi. Sebab tradisi adalah ingatan kolektif. Ia bukan musuh, melainkan refleksi dari sejarah panjang manusia untuk hidup bersama. Yang perlu kita tanyakan adalah: apakah struktur sosial yang kita pertahankan ini masih memberi ruang untuk kesehatan jiwa? Apakah dalam kesibukan merawat simbol dan ritual, kita masih sempat bertanya bagaimana kabar batin orang-orang di dalamnya?
Mungkin sudah saatnya kita memikirkan ulang makna “libur” bukan sebagai sekadar waktu tanpa kerja, tetapi sebagai momen untuk memulihkan diri—secara fisik, emosional, dan spiritual. Mungkin kita juga perlu membayangkan sebuah masyarakat yang tidak hanya menghargai kontribusi seseorang dalam ritual, tetapi juga mendengarkan suara lirih yang datang dari kelelahan jiwa.
Esai ini tidak menawarkan jawaban yang final. Justru ia ingin menjadi batu loncatan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar: Apakah kita berani mengoreksi struktur yang sudah dianggap sakral demi menyelamatkan kehidupan? Apakah mungkin menciptakan kebudayaan yang tidak menekan, tetapi menguatkan? Apakah kita masih punya keberanian untuk mengakui bahwa di balik “surga”, bisa saja ada neraka yang tak terlihat?
Pada akhirnya, jika tradisi adalah warisan, maka mungkin generasi ini dipanggil bukan untuk sekadar mewarisi, tetapi untuk menata ulang—dengan kasih, keberanian, dan kesadaran baru.
*Fileski Walidha Tanjung adalah penulis kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis esai, puisi, dan cerpen di berbagai media nasional.