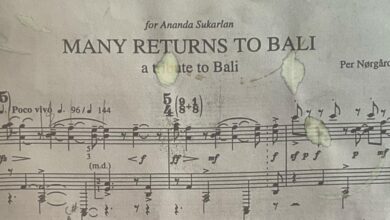Tanggal 21 April, nyaris tiap tahun, sekolah-sekolah di Indonesia menjelma panggung kontes kostum etnik. Anak-anak perempuan mengenakan kebaya, rambut disanggul, dilengkapi riasan lembut yang—entah sejak kapan—dikaitkan sebagai simbol kelembutan perempuan Indonesia. Hari Kartini, demikian katanya. Tapi siapa sesungguhnya Kartini yang dirayakan itu? Dan yang lebih penting: siapa Kartini yang hilang dari narasi?
Kita telah mengurung Kartini dalam bingkai foto di dinding sekolah, mengajarkannya sebagai ikon budaya, namun menelantarkan kegelisahan intelektualnya. Padahal, Kartini bukanlah lukisan perempuan tersenyum dengan sanggul dan kebaya. Ia adalah seorang pemikir yang gelisah—dan keberaniannya muncul bukan dari posisi sebagai istri bupati, melainkan sebagai perempuan muda yang memilih menulis ketika berbicara dilarang, dan berpikir ketika patuh adalah satu-satunya pilihan yang ditawarkan.
Dalam surat-suratnya kepada teman-temannya di Belanda, Kartini menyuarakan satu hal yang mendasar: perempuan adalah manusia yang berpikir. Ia menulis, “Saya mau belajar, agar saya menjadi manusia, seutuhnya manusia.” Inilah titik berangkatnya: ia tidak menuntut menjadi tokoh. Ia hanya ingin mengklaim kembali hak paling dasar dari seorang manusia—kebebasan berpikir dan menentukan arah hidup. Namun, masyarakat kala itu menganggap keinginan perempuan untuk berpikir adalah bentuk pembangkangan.
Ironisnya, Kartini hidup dalam kemewahan. Ia anak bangsawan berdarah biru, bahkan memiliki garis keturunan dari Sultan Hamengku Buwono VI dan jejak kerajaan Majapahit. Namun, alih-alih menikmati hak istimewa, ia mengalami penyangkalan identitas—baik sebagai perempuan Jawa, maupun sebagai manusia ras “pribumi” di bawah penjajahan. Meskipun ia pelajar yang pandai, guru-guru Belanda menolak memberinya nilai terbaik karena dia anak Jawa. Ini bukan hanya diskriminasi akademik. Ini adalah bentuk perampasan martabat intelektual. Dan dari sini, muncul satu ironi besar: pengetahuan diproduksi, tetapi akses terhadapnya dijaga oleh pagar kekuasaan kolonial dan patriarki.
Kartini menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda untuk meminta izin belajar ke Belanda. Ini bukan sekadar permohonan administratif. Ini sebuah momen perlawanan epistemik. Ia mempertanyakan siapa yang berhak memiliki ilmu, dan mengapa tubuh perempuan pribumi dilarang mengakses dunia yang lebih luas. Tapi kekuasaan selalu khawatir pada perempuan yang berpikir. Kartini dilarang berangkat. Pemerintah takut ia menjadi “masalah”, bukan karena ia membawa bom, tapi karena ia membawa gagasan. Ia dapat mengoyak tatanan.
Dan kemudian: pernikahan. Kartini menikah dengan Bupati Rembang, namun bukan tanpa syarat. Ia menetapkan tiga hal yang menggemparkan norma sosial Jawa: tidak mau mencium kaki suaminya, tidak mau berjalan jongkok di hadapannya, dan tidak mau berbahasa kromo inggil. Ini adalah pembangkangan simbolik. Kartini meruntuhkan simbol-simbol kekuasaan patriarki dengan tubuhnya sendiri sebagai arena perlawanan. Di sinilah ia menjadi tokoh yang dalam istilah Judith Butler, “mengganggu performativitas gender” yang dikonstruksi oleh sistem.
Namun, seperti kata Walter Benjamin, sejarah ditulis oleh para pemenang. Kartini yang kritis dan meledak-ledak dibungkam oleh sejarah yang ingin meredam bara. Surat-suratnya dibukukan oleh J.H. Abendanon dalam judul “Door Duisternis tot Licht”—Habis Gelap Terbitlah Terang. Judul ini indah, namun problematik. Ia menjadikan perjuangan Kartini sebagai narasi romantis ketimbang perjuangan politik. Dan pada masa Orde Baru, Kartini yang “galak dan ngegas” direduksi menjadi perempuan yang ayem tentrem dan penuh “etika Jawa”. Sebagaimana dikritisi oleh sosiolog Ariel Heryanto, Orde Baru membentuk identitas perempuan Indonesia sebagai sosok domestik, dan penurut. Kartini menjadi bagian dari propaganda pembangunan—diabadikan bukan sebagai penggugat, melainkan sebagai simbol perempuan yang dirias dan ditata.
Hari ini, Hari Kartini adalah acara lomba rias, lomba merangkai bunga, memasak, atau mencanting batik. Perayaan ini adalah penjinakan simbolik. Kita merayakan Kartini tanpa mengenal marahnya, tanpa menyelami pertanyaannya, tanpa menghidupkan pikirannya. Kita menjadikan Kartini sebagai “artefak”, seperti kata Roland Barthes, “yang telah diberi makna oleh sistem tanda, bukan oleh keberadaan nyatanya.” Kita tidak membaca Kartini; kita hanya memajangnya.
Padahal, bila Kartini hidup hari ini, ia bukan selebgram berkebaya. Ia adalah aktivis media sosial yang menulis thread panjang di X (dulu Twitter), yang mengkritik sistem pendidikan yang diskriminatif, yang mempersoalkan peran perempuan di rumah tangga modern, yang mengecam kebijakan publik yang membungkam suara perempuan. Ia akan bersuara keras, dan mungkin dianggap “terlalu vokal” atau “tidak perempuan”—seperti stigma yang kerap diterima perempuan vokal hari ini.
Simone de Beauvoir menulis, “One is not born, but rather becomes, a woman.” Kalimat ini seolah menggambarkan transformasi Kartini dari seorang gadis bangsawan yang dibesarkan dalam struktur patriarki, menjadi perempuan yang sadar akan ketertindasannya. Tapi kesadaran ini tidak kita warisi. Kita mewarisi kebaya, bukan keberanian. Kita merayakan riasannya, bukan tulisannya.
Apakah kita benar-benar menghormati Kartini, ataukah kita hanya memperingatinya karena takut pada gagasan yang sebenarnya ia bawa?
Kartini adalah perempuan yang menolak diam, namun hari ini ia dikisahkan agar perempuan kembali diam. Ia adalah korban dari sistem, tetapi kita hanya mengenalnya sebagai pahlawan. Kita terlalu sering menghargai pahlawan, tetapi tidak cukup menghargai mereka yang menjadi korban. Padahal, dalam tubuh korban seringkali tersembunyi bibit-bibit perlawanan yang paling murni—karena mereka tidak meminta panggung, hanya meminta keadilan.
Dan pada akhirnya, tak ada yang salah dengan mengenakan kebaya. Tak perlu merasa bersalah ketika anak-anak perempuan tersenyum dalam balutan kain tradisional, berias, berfoto, atau ikut lomba merangkai bunga. Semua itu bisa menjadi bentuk apresiasi budaya, selama tidak berhenti hanya di sana. Kartini bukan hanya tentang estetika. Ia tentang etika berpikir, tentang keberanian menulis, tentang kegigihan melawan ketimpangan sosial yang bahkan berasal dari lingkungan terdekatnya sendiri.
Hari Kartini seharusnya menjadi ruang kontemplasi, bukan hanya perayaan seremonial. Kita boleh menghias rambut anak perempuan dengan sanggul, tapi jangan lupa juga menyisipkan surat Kartini di tangan mereka. Kita boleh merayakan keanggunan luar, tapi jangan melupakan kegelisahan dalam yang membuat Kartini menulis kalimat-kalimat tajam dan penuh pertanyaan: Mengapa perempuan hanya menjadi bayang-bayang laki-laki? Mengapa kebebasan hanya milik kaum bangsawan dan penjajah?
Kartini tidak menulis untuk dikenang. Ia menulis untuk didengar. Maka, jika benar kita ingin menghormatinya, jangan hanya mengenakan kebaya, kenakan pula keberaniannya. Jangan hanya menata sanggul, tata pula cara kita mendidik dan memandang perempuan. Sebab setiap zaman punya bentuk penindasannya sendiri—dan setiap zaman pula membutuhkan suara yang berani menggugatnya.
Apakah kita hanya ingin menjadi generasi yang merayakan sosok Kartini, ataukah kita juga bersedia menjadi generasi yang membaca, memahami, dan meneruskan sikapnya. Itulah pertanyaan yang seharusnya kita renungkan setiap 21 April—dan setiap hari setelahnya.
Berikut saya tulis puisi untuk mengenang perjuangan sosok Kartini:
Surat yang Tak Pernah Dimakamkan
(oleh Fileski Walidha Tanjung)
Aku dilahirkan dari mata yang tak pernah tidur
pada malam-malam di mana sunyi mencekam
Tinta yang membawaku lahir,
dari rahim seorang wanita yang tak memiliki mimbar
yang berteriak, memekik, bersuara lewat kertas-kertas.
Aku bukan surat cinta.
aku menyapa dengan bara yang dirajut halus
oleh gadis Jepara bersanggul kata-kata.
Di tubuhku, kau bisa temukan luka yang dijilid
dan logika yang dipaksa tunduk pada penindasan.
Gurunya memberinya angka-angka kerdil
tapi pikirannya terus menjulang,
lebih tinggi dari menara yang dibangun penjajah.
Ia tidak minta dihormati,
ia hanya ingin bertanya:
“Mengapa akal sehat harus jongkok di hadapan status sosial?”
Aku menangis dalam amplop.
Bukan karena sedih, tapi karena tahu:
ada perlawanan yang begitu sunyi,
mengguncang kekuasaan yang rakus.
Aku menyaksikannya menulis dengan bahasa luka,
mengirimku ke dunia yang tidak siap membaca perempuan.
Sebagai manusia, ia mati muda,
dibalsem dengan kata “pahlawan”
dan dikubur dengan kebaya,
dirias agar pantas diceritakan pada anak-anak..
Padahal ia belum selesai bersuara,
ia bukan sekadar foto pajangan di dinding,
ia adalah senjata.
Sekarang aku terdampar di perpustakaan yang sunyi,
dikerubungi debu dan upacara seremonial.
Anak-anak menari di atas tulang kata-kata,
tapi tak satupun membacaku dengan mata terbuka.
Dengarlah, generasi yang sibuk menggulung rambut,
yang berhias rapi di pagi perayaan:
Aku, surat yang ditulis oleh tangan yang membara,
oleh ia yang masih hidup dalam jiwa.
Aku belum pensiun dari perang.
Aku menunggu untuk dibaca.
Dan jika kau benar-benar ingin merayakan Kartini—
jangan hanya memakai kebaya.
Pakai juga keberaniannya
Bukalah aku.
Bacalah aku.
Lantangkan suaraku.
21 April 2025
BIODATA
Fileski Walidha Tanjung adalah seorang penulis kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis esai, puisi, dan cerpen di berbagai media nasional.