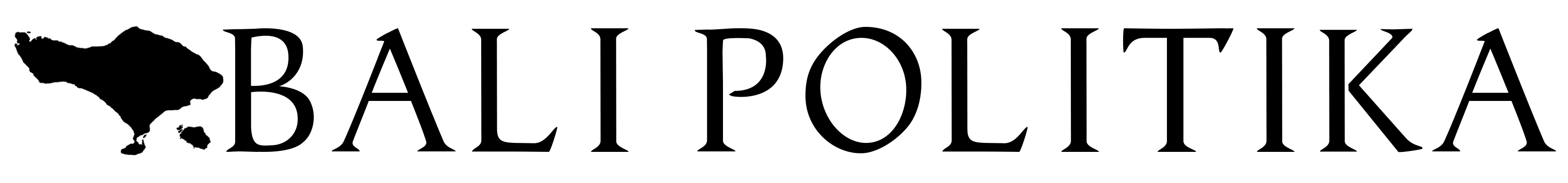DENPASAR (BaliPolitika.Com)- Peluang petahana “digeser” relatif tinggi dalam perhelatan Pilkada Serentak, 9 Desember 2020. Dengan catatan figur penantang memiliki tawaran yang masuk akal bagi masyarakat. Penentu kemenangan, yakni masyarakat juga dituntut menjadi pemilih rasional dan tidak melulu melihat warna parpol saat menyalurkan hak suaranya. Pasalnya, hingga 2026 mendatang kondisi Bali diprediksi kritis karena sektor pariwisata lumpuh. Hanya satu cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan keadaan, yaitu memilih pemimpin yang lahir benar-benar harus profesional, jelas background pendidikannya, kuat dalam manajemen keuangan daerah alias tidak boros, dan transparan.
Jika ingin daerahnya tidak bangkrut, masyarakat harus berani meninggalkan figur permimpin suryak siu; yang mementingkan ego pribadi dan tidak memiliki kepekaan pada persoalan riil yang dihadapi masyarakat. “Kalau kita ingin mengetahui karakter sejati seseorang berilah dia kekuasaan. Intinya sekarang sudah ada yang diberikan kekuasaan. Kini saatnya menilai karakter para pemimpin tersebut. Ada pemimpin yang memilih sembunyi di masa pandemi dan tak mau turun ke lapangan. Masyarakat harus tahu itu,” ucap Gede Pasek Suardika (GPS) diwawancarai beberapa waktu lalu. GPS menyebut kelemahan Bali saat ini adalah sedikitnya tokoh yang mau jadi calon kepala daerah.
Mantan anggota DPR RI dan DPD RI itu berharap situasi sulit di masa panemi corona membuat masyarakat memiliki referensi yang lebih objektif dibandingkan terhipnotis oleh bansos maupun bantuan pragmatis lainnya. GPS yakin pandemi ada sisi positifnya. Salah satunya berpeluang membangun idealisme pemilih. “Kalau pemilih idealis muncul, maka pertumbuhan demokrasi akan berkualitas. Sebaliknya, kalau pemilih pragmatis yang muncul, maka kualitas demokrasi akan turun. Kejadian seperti sekarang secara tidak langsung bisa membuka pandangan yang lebih ideal bagi masyarakat ketika memilih pemimpin. Masyarakat perlu memilih pemimpin yang punya sense of krisis yang bagus,” ungkapnya sembari menyebut siapapun bisa jadi bupati/walikota saat duit berlimpah. Sebaliknya, tidak semua orang bisa jadi pemimpin saat uang terbatas.
“Sekarang kelihatan bagaimana seorang Ganjar Pranowo, Ridwal Kamil, Kofifah, Bima Arya, Risma menjadi sosok yang benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Bima Arya bahkan kena Covid-19 sampai dokter yang merawatnya meninggal dunia. Namun begitu sembuh, dia kembali ke lapangan. Menilai pemimpin harus memperhatikan aspek tersebut. Punya kepekaan mengatasi krisis atau tidak? Dalam konteks Pilkada, referensi ini menjadi tambahan pertimbangan bagi rakyat ketika memilih,” ujarnya. GPS menekankan masyarakat juga harus memilih pemimpin yang memiliki wawasan yang konferehensif, peka, dan tidak nyari selamat sendiri.
Terkait sedikitnya tokoh yang mau jadi calon kepala daerah, GPS menyebut introspeksi besar-besaran harus dilakukan. Fakta tersebut ungkapnya juga mengarah pada “kegagalan” parpol menciptakan pemimpin berkualitas. “Kader sudah keder duluan melihat pragmatisme demokrasi kita,” sentil GPS. Ditambahkannya, banyak orang hebat akhirnya berpikir rugi ikut hajatan pilkada bila hanya bermodalkan wawasan dan kecerdasan. Buntutnya, banyak yang layak, namun memilih ikut karena aspek uang. Di sisi lain, masyarakat juga dinilai terlalu mudah dibeli dan tidak sadar hibah bansos yang didapat merupakan uang rakyat. (bp)