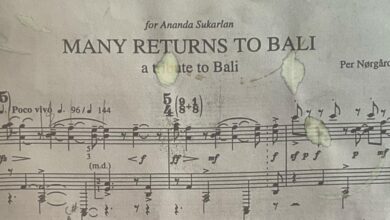Malam
Sebuah ayunan
mengayun gerimis
di halaman.
kriik kriik
Seekor belalang
jatuh
dari lampu
ke rerumputan.
(Majalah Horison, 1973)
Kita boleh membayangkan jika ayunan yang sedang mengayun gerimis itu adalah ayunan yang dengan tergesa-gesa ditinggalkan oleh Frans Nadjira. Lalu, kita juga bisa menduga, belalang yang jatuh dari lampu itu bukan karena cengkraman kakinya kurang kuat mengikat bohlam, tapi karena kaget dengan kecipak air genangan gerimis yang diinjak oleh Frans Nadjira. Lalu, kemana Frans Nadjira pergi? Meninggalkan gerimis yang belakangan sering ia munculkan dalam puisi-puisinya.
Jika seperti itu, berarti sudah waktunya jiwanya terpanggil untuk menepi. Membawa gelembung-gelembung pertanyaan yang jawabannya tak terjangkau. Selama terasing itu, ia berdialog dengan apa dan siapa saja. Percakapannya tak biasa, ia abadikan pada dua ruang yang sesungguhnya masih erat dan melekat: sastra dan seni rupa. Irisan keduanya terletak pada kegelisahan eksistensial sebagai manusia.
Mantra
Pusar laut
Pusar angin
Pusar yang menyisih
Menjauh dari anjungku.
…
Kulabuhkan perahuku
Dengan jangkar dari jarum
Mengapung bagai pinang
Menantang pusat laut
Menantang pusar ribut.
…
Dalam salah satu puisi dalam bukunya Springs of Fire Spring of Tears (1998) ini, Frans Nadjira bak pelaut ulung yang tak berhenti menantang maut. Ia tahu betul mengemudikan perahu kehidupannya agar tetap berlayar. Ketangkasan dan keras tekad sebagai pengembara itulah yang menuntunnya pada sebuah perjalanan eksistensial. “Mencari kemudian menunggu bukanlah mimpi buruk yang hampa. Di sana ada harapan menanti selubung menyambung setiap hari. Semacam sulur pohon yang terus memanjang setiap hari,” katanya.
Pengalaman yang sifatnya personal itu ia letakkan sebagai “tabung pembakaran” (semacam fermentasi) kreativitas estetik, di mana yang muncul kemudian bukanlah “narasi penderitaan”, melainkan apa saja yang telah terbebaskan hingga menjadi sebuah karya estetik yang digali dan diciptakan bersama-sama dengan upaya menemukan orisinalitas.
Jika kita uji pandangan Frans Nadjira tentang kedalaman kontemplasinya di dalam karya-karyanya, kita akan menemukan intisari dari semua proses kepenyairannya, yaitu kegelisahan eksistensial. Frans Nadjira memang soliter berdialog dengan kegelisahan-kegelisahan subtil itu, baik yang vertikal maupun horizontal.
Kegelisahan itu tidak berjarak dengan badannya, ia hadir dan menubuh dalam diri Frans Nadjira. Lewat tempaan cambuk pedati kehidupan yang memang sejak kecil sudah karib dengannya. Kegelisahan yang menubuh membuncah pada selubung puisi-puisinya yang menggunakan simbolisme gelap. Lihat bagaimana selubung itu lirih dan samar-samar namun tak kehilangan dorongan untuk menciptakan ruang-ruang negosiasi internal.
Daging
Setumpuk daging bergerak
menyeberang bayang-bayang mesin jahit
Di ranjang pulas anak-anakku
telah kutempeleng mereka tadi sore
hanya karena alasan yang sepele.
Pemintal terkutuk,
pestalah sepuasmu
beraikan percahan nafsuku.
Setumpukan daging membusuk
meleleh sekerat
dari langit-langit syahwat.
(1998)
Sisi lain dari sikap kesendirian itu juga membentuk puisi-puisi Frans Nadjira bersuara secara bernas: /kutempeleng/ /sepele/ /terkutuk/ /membusuk/. Kita bisa menduga, Frans Nadjira bisa begitu latang karena puisinya seperti menanggung penderitaan umat manusia yang sebenarnya adalah pengalaman lahiriah penulisnya sendiri. Yang menarik kemudian adalah pertemuan antara diksi yang telanjang itu /kutempeleng/ /sepele/ /terkutuk/ /membusuk/ dengan simbolisme yang memiliki selubung seperti /daging/ /mesin jahit/ /ranjang/ /nafsuku/ /syahwat/. Simbolisme terselubung itu memang terkesan samar-samar, terkesan kontradiktif dengan yang bernas. Namun jika kita cermati, itulah gaya kritik Frans Nadjira dalam puisinya. Sengaja membenturkan hubungan antara kegelisahan eksistensial yang bersifat vertikal dengan horizontal; yang lahiriah dan ilahiah. Jika kedua realitas itu dibenturkan, terkadang kita baru menyadari, tentang pentingnya untuk negosiasi dalam menjalani hidup. Baik negosiasi terhadap diri sendiri maupun dengan takdir Tuhan.
Kepekaan kontemplasi Frans Nadjira juga mempertajam indranya untuk mengupas eksistensialisme dengan liris. Pilihan diksinya memberikan penciptaan gambaran peristiwa yang kuat. Selain itu, puisi ini begitu cepat menawarkan lompatan imaji yang radikal: /Seorang perempuan/ baru saja /menebar jala/ di /rerumputan/ tiba-tiba /turun gerimis/, /dari atas bukit-bukit/. Namun di situlah kekuatan dari puisi ini. Lompatan-lompatan imaji diperlukan Frans Nadjira untuk memberikan efek kejut dalam puisi-puisi naratifnya.
Mimpi dalam Demam
Seorang perempuan
Berbaju hitam
Menebar jala
Di atas rerumputan
Lalu turun gerimis
Dari atas bukit-bukit
Serombongan anak-anak
Bernyanyi
Kami telah menadah matahari
Mengumpulkan dalam keranjang
Kami telah memetik matahari
Memasukkannya dalam keranjang
Bercampur bunga-bunga.
(Majalah Horison, 1973)
Puisi tersebut juga bisa disebut serupa memoar, menampilkan pandangan tak berjarak Frans Nadjira sebagai saksi kesia-siaan yang dialami /Seorang perempuan/ yang seolah-olah buta /menebar jala/, /di atas rerumputan/. Tapi sekaligus ada harapan tak putus yang disematkan pada /serombongan anak-anak/ yang /bernyanyi/ seusai /kami telah memetik matahari/, dan /memasukkannya dalam keranjang/. Frans Nadjira nampaknya berupaya untuk membaca ulang tentang esensi hidup, khususnya pada peristiwa-peristiwa yang tak terkatakan. “Manusia dipertemukan oleh takdir. Pada saat kekuatan dahsyat itu bekerja, maka lenyaplah segala perbedaan. Manusia hanya sebuah sampan kecil di tengah samudera luas kehidupan yang penuh dengan rahasia,” tulisnya dalam buku kumpulan cerpennya Pohon Kunang-Kunang (2010).
***
Menjadi perupa ataupun penyair, bagi Frans Nadjira, bukanlah pentasbihan yang tiba-tiba. Ia harus melewati sebuah proses yang panjang karena untuk dapat mendapatkan karakter karyanya, seorang harus sabar menjalani liku-likunya dan tak sembarang orang tahan menjalaninya. Sebaliknya, Frans Nadjira berhasil melewati tantangan itu dengan proses panjang perjalanan berkeseniannya. Frans Nadjira betul-betul memanfaatkan keterbatasan bidang datar—kanvas maupun kertas—sebagai tantangan kreatif.
Dalam memaksimalkan watak dasar kegiatan melukis dan menulis, Frans Nadjira menemukan kebebasan ekspresi yang tak terduga. Kebebasan ekspresi itu menubuh dalam dirinya. Mengkristal melalui laku-laku perjalanan visual dan spiritual yang ia babat habis seumur proses kreatifnya. “Sempatkan merenung bahwa kita akan tiba di senja keberangkatan menuju kedalaman?” pungkasnya.
*Pengajar Sastra Indonesia Universitas Udayana.