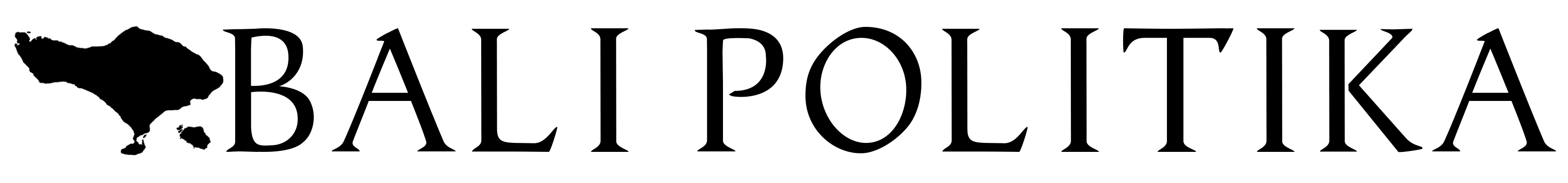GIANYAR, Balipolitika.com- Serangkaian Peringatan Hari Jadi Kota Gianyar ke-254, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan resmi membuka Pameran Dagang Lokal yang digelar di Alun-Alun Gianyar mulai tanggal 12 April hingga 19 April 2025.
Hal ini sesuai amanah PP 29 tahun 2021 (Kementerian Perdagangan RI) tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dengan melaksanakan Pameran Dagang Lokal dengan menampilkan UKM /IKM binaan Dekranasda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan lokal serta memperkuat posisi UMKM dan IKM dalam rantai ekonomi daerah yang siap sebagai calon eksportir dan yang sudah menjadi eksportir.
Pameran dibuka Bupati Gianyar, I Made Mahayastra bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar Ny. Doktor Surya Adnyani Mahayastra ditandai dengan pengguntingan pita dan dilanjutkan kunjungan ke stand-stand peserta.
Pameran Dagang Lokal 2025 menampilkan 40 peserta pelaku usaha, mulai dari kerajinan kayu, perak dan handycraft, fashion, produk spa hingga produk inovasi IKM lokal.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary menyampaikan, pameran dagang merupakan komitmen pemerintah untuk mendorong produk lokal tampil di pasar yang lebih luas dan mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen, investor, pembeli, serta mitra strategis.
“Pameran tahun ini konsepnya agak beda, yakni menampilkan UMKM calon eksportir sesuai dengan konsep Bapak Bupati mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan lokal, membuka peluang ekspor, meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar global dengan kualitas, kemasan, dan standar yang sesuai,” kata Eka Suary.
Kegiatan ini dilakukan guna mendukung program nasional dalam peningkatan ekspor non-migas dan substitusi impor, sebagaimana diamanatkan dalam PP 29 Tahun 2021.
“Tujuan utamanya adalah memeriahkan HUT Kota Gianyar ke-254 dengan kegiatan produktif dan berdampak langsung bagi pelaku ekonomi yang ingin memajukan IKM dan memperkenalkan produk baru yang ada di Gianyar,” lanjut Eka Suary.
Hal tersebut dilakukan mengingat banyaknya UMKM/IKM yang ada di Kabupaten Gianyar.
Sementara itu, Bupati Mahayastra mengatakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran dan kontribusi nyata dalam perekonomian daerah.
Dengan kemampuannya menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta melestarikan produk dan budaya khas daerah, UMKM menjadi salah satu sektor paling strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“UMKM identik ada di Gianyar. UMKM di Bali 60% bahkan lebih ada di Gianyar,” ujar Bupati Mahayastra.
Selain perannya dalam perekonomian, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan bahkan tetap bergerak ketika menghadapi krisis perekonomian, baik krisis global maupun nasional.
“Jadi ini yang paling bertahan ketika mengalami kesulitan, seperti pada saat covid, karna ini adalah penggerak sektor kerakyatan, sehingga akan menumbuhkan seni, budaya dan kreativitas yang dapat menjadi pondasi perekonomian daerah dan nasional,” lanjutnya.
Ketahanan ini didukung oleh karakteristik UMKM yang fleksibel, berbasis lokal, serta memiliki sistem operasional yang relatif sederhana dan tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal global.
Pameran diharapkan mampu menjadi ajang promosi, peningkatan jaringan bisnis, dan ruang belajar bagi pelaku usaha. Pemerintah juga mendorong agar kegiatan serupa dapat menjadi agenda rutin tahunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (bp/dp/ken)