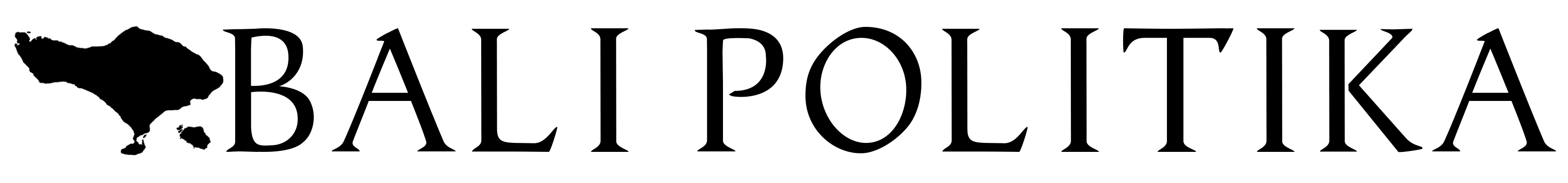TERIMA TANTANGAN: Ketua DPD Golkar Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry saat berada di Kampus Universitas Udayana berdiskusi bersama mahasiswa Sabtu, 30 September 2023.
DENPASAR, Balipolitika.com– Partai Golkar Bali menyambut baik tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) untuk beradu ide dan gagasan.
BEM Unud ingin menjadi bagian mewujudkan gagasan dan terobosan untuk parpol sebagai peserta pemilu adu ide dan gagasan melalui kegiatan simakrama pemilu di Gedung Juang Unud, Sabtu, 30 September 2023.
Tahap pertama BEM mengundang 4 partai, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Golongan Karya (Golkar), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Acara itu dihadiri jajaran BEM Unud, BEM- BEM berbagai perguruan tinggi dan mahasiswa berbagai Fakultas Unud. Totol peserta sekitar 150 orang.
Dalam sambutannya, Ketua BEM Unud Putu Bagus Padmanegara menyampaikan syukur langkah awal ini terwujud dan dihadiri secara antusias oleh kalangan BEM dari berbagai perguruan tinggi dan mahasiswa Unud.
Namun, Putu Bagus Padmanegara sangat menyayangkan hanya Partai Golkar yang hadir alias memenuhi undangan BEM Unud.
Sedangkan Partai Nasdem, Hanura, dan PKS tidak hadir dengan berbagai alasan.
Beber Putu Bagus Padmanegara ada parpol yang menginfokan 1 jam sebelum acara dimulai tidak bisa hadir dengan berbagai alasan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Bali, Dr. Nyoman Sugawa Korry hadir didampingi M.Kadafi, SH.MH yang notabene mantan aktivis dan alumni Unud.
Meski tiga parpol mangkir, Putu Bagus Padmanegara menegaskan hal tersebut tidak mengurangi kualitas diskusi yang dipandu Riski Dimas Tio sebagai moderator.
Di lain sisi, Dr. Dewa Gede Wiryangga Selangga mewakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unud, menyambut baik program BEM ini, karena sebagai mahasiswa, universitas sebagai lembaga ilmiah dan pendidikan mengharapkan ilmu pengetahuan yang diraih dipadukan dengan fenomena dan praktik dalam dunia nyata.
“Termasuk di bidang politik. Program ini diharapkan terus dievaluasi dan disempurnakan,” kata Dosen yang akrab disapa Dewa Angga itu.
Sementara itu, Sugawa Korry dalam paparannya menjelaskan Partai Golkar yang pada awalnya disebut dengan Sekber Golkar dilahirkan pada 20 Oktober 1964 oleh berbagai komponen masyarakat pada saat itu.
Sekber Golkar diharapkan berperan mengatasi persoalan-persoalan bangsa.
“Pada saat itu, kondisi bangsa dalam keadaan terancam akibat dari tarik menarik kekuatan ekstrem kiri dan ekstrim kanan. Puji syukur Sekber Golkar berhasil menjaga eksistensi bangsa Indonesia pada saat itu, untuk selanjutnya membangun bangsa tahap demi tahap,” jelas Sugawa Korry.
Ketika kondisi Partai Golkar dalam keadaan paling terpuruk pada saat lahirnya reformasi, Partai Golkar tetap komit mengawal bangsa ini dengan mewujudkan aspek regulasi atau undang-undang berkenaan dengan reformasi di bawah BJ Habibie dan anggota-anggota parlemen Partai Golkar.
Begitu juga halnya pada saat bangsa ini mengalami tantangan berat mengatasi Covid–19, Partai Golkar melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto dengan seluruh jajaran kader, pemerintah, dan masyarakat menyelamatkan dari keterpurukan.
“Ke depan, Partai Golkar berharap kita semua bersatu untuk atasi middle income trap atau jebakan pendapatan menengah dan memaksimalkan bonus demografi untuk menuju negara maju. Khusus untuk Bali, Partai Golkar mengajak untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Bali secara adil dan merata dengan tetap menjaga kearifan lokal, yaitu nilai-nilai adiluhung budaya Bali,” ujar Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
M. Kadafi, dalam kesempatan pemaparan berikutnya menjelaskan sebagai aktivis reformasi ia adalah orang paling getol mendemo Golkar.
Namun, saat ini, ia mengaku mencintai Golkar karena setelah dia mendalami di tubuh Partai Golkar bersemi semangat sebagai partai terbuka.
Ungkapnya, tidak ada pemilihan saham mayoritas di tubuh Golkar dan selalu mendorong kadernya untuk meningkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta bersikap demokratis.
“Ke depan saya berharap di Bali ini, terwujud keseimbangan kekuatan sosial politik, sehingga yang dikedepankan adalah adu ide dan gagasan, terwujudnya kontrol sosial politik sehat dan berimbang dan tidak ada mayoritas tunggal sehingga kualitas SDM menjadi syarat utama,” harapnya.
Pada sesi diskusi, direspons dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan kritis dari para mahasiswa yang berjalan dengan penuh kekerabatan dan kaidah-kaidah ilmiah.
Acara diakhiri dengan penyerahan empat buah buku kajian dan pokok-pokok pikiran Golkar yang disusun berdasarkan webinar, dan forum diskusi grup.
Buku dimaksud adalah Strategi Pembangunan Ekonomi Pasca- Covid–19, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Usulan Revisi Perda Desa Adat, dan Usulan Revisi Undang-Undang Perimbangan Keuangan dan Pembinaan Petani Bali. (bp)