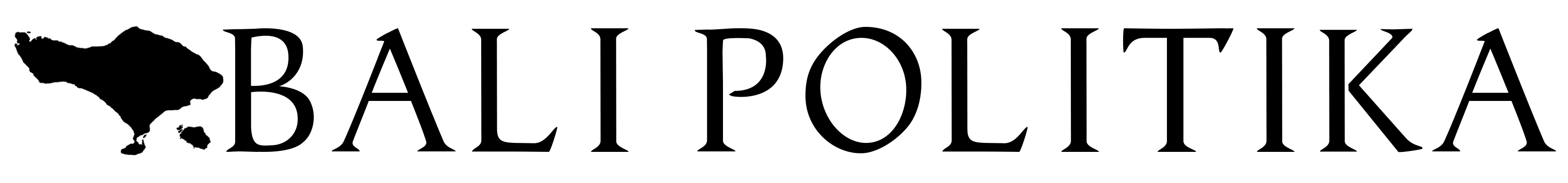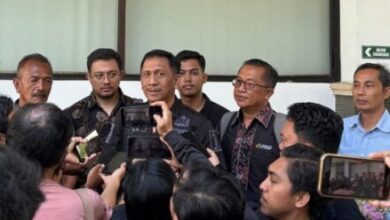TITIPAN DITOLAK?: Rektor Unud, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.IPU ditetapkan sebagai tersangka korupsi sejak Rabu, 8 Maret 2023 dan diumumkan pada Senin, 13 Maret 2023 oleh Kejati Bali.
DENPASAR, Balipolitika.com– Perbedaan terjal hasil audit antara penyidik Kejaksaan Tinggi Bali versus Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan (BPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo, Inspektorat Jenderal Kemendikbud RI, Satuan Pengawas Internal Unud, dan Akuntan Publik sehingga secara subjektif melalui kewenangannya akhirnya Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Unud, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.IPU sebagai tersangka korupsi sejak Rabu, 8 Maret 2023 dan diumumkan pada Senin, 13 Maret 2023 mencuri perhatian.
Banyak pihak menilai apabila ketimpangan ini dibenarkan, maka seluruh Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia akan terjerat pasal korupsi terkait Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang merupakan jenis biaya kuliah sah yang harus dibayar mahasiswa saat masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di tanah air.
Keberanian Kepala Kejaksan Tinggi Bali Ade T Sutiawarman tidak membenarkan alias membantah audit terhadap Unud yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo pun jadi sorotan hingga menimbulkan banyak tanda tanya.
Tak sedikit netizen yang berkomentar bahwa ada hal “menarik” terkait penetapan Rektor Unud, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.IPU sebagai tersangka korupsi.
Dugaan itu salah satunya disampaikan oleh pemilik akun media sosial bernama suaryaningrat yang mengaku heran Rektor Unud ditetapkan sebagai tersangka sementara di sisi lain 5 audit oleh lembaga terpercaya atau kredibel menyatakan tidak ada masalah terkait keuangan di kampus tertua Pulau Dewata.
“Rektor Unud dinyatakan tersangka oleh Kejati (Bali, red) konon anak petinggi Kejati ga bisa masuk Unud dan ga mau mau lewat jalur mandiri, mintanya gratis, padahal SPI itu dilegalkan. Liat aja berapa beasiswa yang dikeluarkan Unud, berapa gedung baru yang dibuat sekarang. Ini cuma konspirasi untuk jatuhin Rektor. Kalian mahasiswa punya intelektual tolong cari informasi yang benar dulu baru demo,” tulisnya.
Usut punya usut dugaan titipan oknum petinggi Kejaksaan Tinggi Bali ternyata dibenarkan oleh sumber terpercaya dari Universitas Udayana. Bahkan disebutkan bahwa ada memo yang ditulis langsung oleh oknum petinggi Kejati Bali tersebut.
“Nggih. Inilah motif sejatinya. Informasi A1 memo (dari oknum petinggi Kejati Bali, red) masih tersimpan rapi,” ujar sumber.
Sumber menyayangkan Rektor Unud Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.IPU tidak optimal membantu alias memenuhi permintaan oknum petinggi Kejati Bali tersebut.
“Kita salah kenapa tidak optimal bantu. Akibatnya jauh melampaui dari kesalahan tersebut,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, SPI merupakan jenis biaya kuliah yang harus dibayar mahasiswa saat masuk perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia.
Terkait SPI, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) pada praktiknya membuat Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan keuangan di lingkungan Kemdiknas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu diatur ketentuan mengenai persyaratan administratif penetapan badan layanan umum, pedoman umum penyusunan tarif layanan badan layanan umum, penyusunan, pengajuan, dan penetapan rencana bisnis dan anggaran serta penetapan dokumen anggaran, penghapusan piutang, kewenangan peminjaman, kewenangan pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan aset badan layanan umum.
Pegangan inilah yang antara lain digunakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkait dengan SPI. Salah satunya oleh Universitas Udayana (Unud). Meski demikian, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali pada Senin, 13 Maret 2023 mengumumkan Rektor Unud, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.IPU. sebagai tersangka.
Status tersangka yang disandang Rektor Unud ini otomatis menggugurkan 5 audit yang menyatakan tidak ada masalah terkait keuangan di kampus tertua Pulau Dewata. (bp)