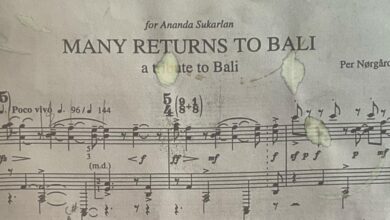DALAM “Simulacra and Simulation”, Jean Baudrillard menyatakan bahwa dalam masyarakat pascamodern, representasi bisa melampaui kenyataan dan bahkan menggantikannya. Apa yang kita konsumsi sebagai “realitas” tak lagi merujuk pada yang nyata, melainkan pada citra yang terus-menerus direproduksi, dipoles, dan dikomersialisasikan. Di titik ini, lelaki Korea yang hadir dalam drama dan boyband bukan lagi manusia, melainkan citra hiperreal—fantasi kolektif yang menuntut pemujaan tanpa syarat. Kita tidak sedang mencintai pria Korea, kita mencintai ide tentang pria Korea.
Indonesia, seperti banyak negara lain di Asia, kini tengah mengalami fenomena besar: demam Korea, atau yang lazim disebut Korean Wave (Hallyu). Namun, di balik gejala kultural ini, tersembunyi kegelisahan yang tak banyak disadari. Terutama ketika perempuan Indonesia mulai mengidealkan karakter pria Korea semata-mata dari tontonan layar kaca—sosok lelaki yang penuh kelembutan, perhatian tanpa batas, dan cinta yang selalu mengalah. Citra ini membius, namun juga menyesatkan. Dalam terminologi Slavoj Žižek, ini adalah bentuk “ideologi sebagai fiksi”—sebuah fiksi yang disadari sebagai tidak nyata, namun tetap dipercayai karena menawarkan kenyamanan psikologis.
Kita hidup dalam zaman di mana eksistensi manusia seringkali dinilai bukan dari laku hidupnya, melainkan dari seberapa “layak tayang” ia dalam narasi digital. Budaya visual, seperti yang dikritik Susan Sontag dalam On Photography, tidak lagi menangkap kenyataan, tetapi menciptakan kenyataan alternatif yang lebih bisa dijual dan dikonsumsi. Pria Korea dalam drama romantis bukan sedang “direpresentasikan”, melainkan sedang “diciptakan ulang” sebagai objek konsumsi budaya global. Ia adalah artefak budaya, bukan entitas manusiawi. Di sinilah titik persoalan kita: ketika perempuan mencintai bukan manusia, tetapi ilusi estetik yang dikonstruksi untuk memuaskan harapan emosional pasar.
Sebuah studi dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan (MOGEF) tahun 2023 mencatat bahwa hampir 34 persen perempuan di Korea pernah mengalami bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini mencakup kontrol psikologis, ancaman verbal, dan kekerasan fisik. Namun ironi mencuat ketika negara yang dilabeli maju ini justru menyimpan wajah patriarki yang masih kental, seperti yang disinggung oleh sosiolog feminis Choi Hyeon. Ia menyebut bahwa “modernitas Korea adalah modernitas maskulin”—kemajuan ekonomi dan teknologi tidak serta-merta membawa kesetaraan gender. Dalam keluarga, lelaki masih dominan, dan perempuan sering kali diposisikan sebagai objek pelengkap. Di sinilah letak paradoks: layar memperlihatkan cinta utopis, sementara realitas memproduksi luka-luka tak terlihat.
Sebagian besar perempuan Indonesia yang tergila-gila dengan pria Korea, tak pernah benar-benar bersinggungan dengan realitas sosial Korea itu sendiri. Mereka tak hidup di sana, tak menjalin relasi nyata, dan tak menyaksikan bagaimana budaya kerja yang keras, tekanan sosial, dan sistem nilai konfusius sering kali menekan ekspresi kasih sayang. Justru karena itulah industri drama dan K-Pop menjadi bentuk pelarian kolektif masyarakat Korea sendiri, sebagaimana disebut oleh ahli budaya populer, Kim Ji-young, bahwa “drama Korea bukanlah cermin realitas, melainkan jendela impian.” Mereka adalah dunia yang seharusnya, bukan dunia yang sebenarnya.
Namun di Indonesia, citra ini diserap bulat-bulat, bahkan ditinggikan. Kekritisan hilang digantikan oleh kultus emosi. Jika Roland Barthes menyebut mitos sebagai “cara bagaimana budaya berbicara kepada kita”, maka pria Korea dalam drama menjadi mitos baru tentang cinta—narasi yang tampaknya netral, tapi sesungguhnya politis. Ia membentuk bagaimana perempuan membayangkan cinta, relasi, dan bahkan nilai hidup itu sendiri. Bukan tak mungkin, dalam proses ini, perempuan kehilangan kemampuan untuk mengenali dan mencintai laki-laki di sekitarnya yang nyata, dengan segala kekurangan dan keotentikannya.
Dampaknya bisa jauh lebih serius dari sekadar preferensi tontonan. Ketika pemujaan ini berkembang tanpa kritik, kita tak hanya membiarkan diri larut dalam fiksi, tapi juga memperlebar jarak antara realitas dan ekspektasi emosional. Relasi menjadi medan ilusi. Mencintai hanya ketika sesuai dengan template drama. Dan ini bukan hanya soal rasa, ini soal cara kita sebagai bangsa mengelola kebudayaan.
Seperti yang diingatkan oleh filsuf Prancis, Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk represi, tetapi juga dalam bentuk wacana. Siapa yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan “laki-laki ideal” juga memiliki kuasa atas imajinasi kolektif perempuan. Dalam konteks ini, industri Korea telah dengan sangat halus dan canggih mengkolonisasi ruang batin kita. Kita tidak hanya mengimpor produk, tetapi juga membiarkan sistem nilai dan standar cinta yang dikonstruksi negara lain membentuk identitas emosi bangsa kita.
Jika Indonesia tidak segera membangun narasi tandingan, perempuan Indonesia hanya akan menjadi penonton dari peradaban bangsa lain—terus-menerus menelan imajinasi romantik yang bukan hanya palsu, tetapi juga menjebak. Kita harus mulai melihat drama Korea bukan sebagai realitas, melainkan sebagai artefak budaya: ia menyimpan jejak trauma kolektif, harapan, dan bahkan ketimpangan yang coba dihaluskan dalam narasi cinta. Maka yang kita butuhkan bukan sekadar menonton dengan mata, tetapi membaca dengan kesadaran. Membaca, seperti kata Walter Benjamin, adalah “melihat dengan cara yang berbeda.”
Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar, “Kenapa perempuan Indonesia menyukai pria Korea?” tetapi, “Apa yang sedang dicari oleh perempuan melalui pria Korea dalam drama?” Apakah mereka merindukan kelembutan yang tak mereka temukan di sekelilingnya? Atau justru mereka sedang melawan realitas sosial yang keras dengan membangun ruang batin yang lembut dan utopis, meskipun semu?
Di titik ini, drama Korea bukan hanya soal hiburan. Ia menjadi jendela yang mengantar kita menengok ke dalam: ke ruang-ruang kosong dalam jiwa manusia modern yang rindu pada kasih yang tidak manipulatif, perhatian yang tidak transaksional, dan cinta yang tidak perlu selalu rasional. Maka dari itu, alih-alih menyalahkan perempuan yang tergila-gila pada pria Korea, barangkali lebih adil jika kita bertanya: apa yang telah gagal diberikan oleh masyarakat kita sendiri kepada mereka, hingga fiksi terasa lebih bisa dipercaya daripada kenyataan?
Seberapa jauh kita memahami bahwa kebutuhan akan kelembutan, penghargaan, dan cinta yang tulus adalah kebutuhan universal yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam tatanan sosial kita? Seberapa sadar kita bahwa industri hiburan luar bukan hanya mengisi ruang kosong dalam waktu luang kita, tapi juga mengisi kekosongan dalam struktur emosi yang sudah terlalu lama dikekang oleh norma, oleh budaya malu, oleh relasi gender yang timpang?
Mungkin inilah saatnya kita menilik ulang bukan hanya apa yang kita tonton, tapi juga mengapa kita menontonnya. Apakah kita sedang membangun imajinasi tentang cinta yang sehat? Ataukah kita sedang menegaskan betapa rusaknya cara kita mencintai dan dicintai dalam kehidupan nyata?
Ketika pria Korea dalam drama dipuja sebagai lambang cinta ideal, ia sebetulnya sedang menjadi cermin dari harapan manusia akan kasih sayang yang belum mereka temukan. Dalam kerangka ini, sang pria bukan lagi tokoh fiktif, melainkan semacam doa diam-diam yang terucap lewat layar: bahwa di dunia yang begitu sering menyakiti, masih ada ruang untuk cinta yang tidak melukai.
Namun, seperti semua doa, ia butuh dijawab—bukan oleh dunia sinema, tetapi oleh kita semua, yang hidup di dunia nyata. Pertanyaannya: sanggupkah kita menciptakan kenyataan yang layak untuk menggantikan ilusi. (*)
BIODATA
Fileski Walidha Tanjung adalah seorang penulis dan penyair kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis prosa, puisi, dan esai di berbagai media lokal dan nasional.