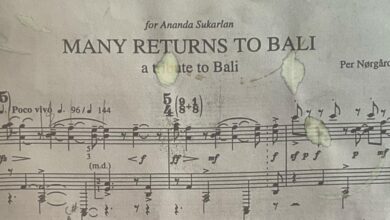DI SEBUAH dunia yang berisik oleh notifikasi, ada keheningan yang hilang—hening yang dulu melahirkan filsuf, penyair, dan penemu. Kini, layar-layar kecil mengajari kita bahwa mendapat perhatian adalah komoditas, bukan proses batin yang sakral. Dalam dunia seperti itu, sebuah data muncul sebagai anomali: China dan Iran, dua negara yang membatasi akses media sosial, tercatat memiliki rata-rata IQ tertinggi secara global. Apakah ini sebuah kebetulan statistik, atau ada semacam arkeologi makna yang menunggu digali dari balik angka-angka?
Kita hidup dalam era dimana logika Guy Debord dalam La Société du Spectacle terasa semakin nyata: dunia tidak lagi dipahami melalui pengalaman langsung, melainkan melalui representasi—gambar, suara, dan cuplikan 15 detik yang menuntut atensi instan dan menyisakan pemikiran keruh. “Segala yang pernah langsung dijalani telah menjelma menjadi representasi,” tulis Debord. Di sini, media sosial bukan sekadar alat, melainkan habitat baru kesadaran.
Bahwa China dan Iran menempati posisi tertinggi dalam rata-rata kecerdasan bukanlah hal remeh. Keduanya memiliki sistem sosial yang, suka atau tidak, memproteksi warganya—khususnya generasi mudanya—dari paparan terus-menerus terhadap dunia digital yang seringkali brutal dan tanpa filter. Ini mengingatkan kita pada peringatan Neil Postman dalam Amusing Ourselves to Death (1985), bahwa masyarakat yang terlalu sibuk menghibur dirinya sendiri akan kehilangan kemampuan berpikir kritis. Media sosial, dalam banyak kasus, telah mengerdilkan refleksi menjadi reaksi, dan pemikiran menjadi performa.
Sastrawan C.S. Lewis pernah menyindir bahwa zaman modern bukan hanya tidak membaca karya besar, tetapi lebih buruk: “tidak tahu bahwa karya itu ada.” Di banyak negara dengan indeks literasi rendah, bukan hanya buku yang ditinggalkan, tetapi budaya bertanya yang perlahan hilang. Dalam konteks ini, larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia matang seperti yang diterapkan di Australia menjadi semacam resistansi kultural—upaya mempertahankan otonomi intelektual dalam dunia yang semakin terotomatisasi.
Namun, larangan semata tidak menjawab seluruh pertanyaan. Kita harus bertanya lebih jauh: apakah media sosial memang merusak kecerdasan, ataukah kita hanya gagal merancang ekologi digital yang sehat? Di sinilah esai ini tidak hendak terjebak dalam dikotomi antara “akses” dan “penyekatan,” melainkan ingin memetakan lanskap yang lebih rumit—bahwa media sosial bukan sekadar teknologi, tapi medan kuasa, arena politik kognitif, dan semacam teks budaya yang mesti dimaknai berlapis-lapis.
Walter Benjamin dalam esainya “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” mencatat bahwa teknologi modern telah mengubah cara kita mengakses pengalaman estetis, dan dengan itu juga cara kita berpikir. Begitu juga dengan media sosial: ia mendemokratisasi ekspresi, namun sekaligus mendangkalkan eksistensi. Anak-anak yang tumbuh dengan algoritma yang mengatur apa yang mereka lihat dan pikirkan, akan kesulitan mengembangkan daya kritis, sebab mereka tidak dibesarkan untuk bertanya, tetapi untuk scroll.
Barangkali, inilah paradoks yang menyentuh akar kebudayaan kita: bahwa dalam mengejar kemajuan teknologi, kita justru kehilangan perangkat batiniah untuk menafsirkan dunia. Kita menyebut ini “kebebasan berekspresi”, namun seringkali yang terjadi hanyalah “kebebasan berisik”. Apa yang dulu menjadi ranah kontemplasi dan dialektika, kini dipadatkan dalam opini-opini cepat dan meme yang viral. Bahkan makna pun menjadi sekadar tanda yang bisa dipakai ulang tanpa akar.
Dalam dunia yang seperti ini, apakah larangan akses media sosial menjadi jalan menuju kebijaksanaan? Atau justru ia menciptakan ketidakseimbangan baru, ketika otoritas negara mengambil alih fungsi edukasi kultural tanpa kejelasan arah etik? Kita perlu menjawabnya dengan menengok ulang bagaimana kita memahami intelektualitas. Bukan semata kemampuan kognitif mengerjakan soal logika, tapi daya untuk bertanya, menyelidik, dan membentuk horizon makna.
Simone Weil pernah menulis bahwa “perhatian adalah bentuk cinta yang paling murni.” Dalam dunia yang memecah perhatian menjadi fragmentasi monetisasi, upaya mengarahkan ulang generasi muda agar kembali belajar memberi perhatian—pada bacaan, pada dunia nyata, pada pikiran sendiri—adalah tindakan politik yang radikal. Bukan dengan melarang secara dogmatis, tetapi dengan membangun etos baru, di mana keheningan dan bacaan bukan dianggap kuno, tapi esensial.
Dan mungkin, dalam keheningan itulah, IQ bukan lagi soal angka, melainkan soal kebijaksanaan. Sebab seperti kata T.S. Eliot dalam Choruses from ‘The Rock’:
“Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?”
Dan pada akhirnya, pertanyaan yang mesti kita ajukan bukan hanya soal siapa yang paling cerdas, tetapi bagaimana kecerdasan itu dibentuk, diarahkan, dan untuk apa ia digunakan. Apakah kecerdasan manusia hari ini masih memiliki akar moral dan daya jelajah spiritual, ataukah telah menjadi sekadar alat dalam ekosistem digital yang tak memberi ruang untuk hening, apalagi renungan?
Kita mungkin bisa melatih anak-anak untuk memecahkan teka-teki logika, tapi apakah kita juga sedang membentuk mereka untuk menjadi manusia yang tahu kapan harus diam, bertanya, mendengar, dan memahami? Di tengah kebisingan yang dijustifikasi sebagai kebebasan, masihkah ada ruang bagi batin yang tumbuh perlahan seperti pohon, yang kuat bukan karena cepat tumbuh, tapi karena akarnya menyentuh kedalaman?
Jika media sosial adalah cermin dari peradaban, maka barangkali kita telah terlalu lama bercermin tanpa pernah bertanya siapa yang sedang kita lihat. Apakah wajah yang menatap kita dari balik layar adalah cerminan dari jiwa yang utuh, atau hanya topeng algoritma yang tersenyum palsu demi kelangsungan “engagement”?
Di dunia yang semakin mendewakan kecepatan, mungkin saatnya kita bertanya dengan jujur: apa yang sedang kita korbankan dari generasi mendatang demi ilusi bahwa semua harus terkoneksi? Apakah kecerdasan sejati bisa tumbuh di tanah yang gersang dari makna? Ataukah kita perlu kembali pada kesadaran purba bahwa menjadi manusia bukan soal siapa yang tahu lebih banyak, tapi siapa yang bisa hidup dengan lebih sadar?
Seperti kata Rainer Maria Rilke dalam Letters to a Young Poet:
“Try to love the questions themselves… Do not now seek the answers… live the questions now. Perhaps then, someday far in the future, you will gradually, without even noticing it, live your way into the answer.”
Dalam pertanyaan-pertanyaan itulah, kita mungkin bisa mulai membangun kembali peradaban yang tidak hanya mengagumi IQ tinggi, tapi juga merayakan jiwa yang dalam. Sebab dunia yang kita wariskan tidak hanya butuh orang pandai, tetapi juga manusia yang peka—yang mampu menyelamatkan makna dari derasnya informasi, dan membawanya kembali ke pangkuan kehidupan yang lebih utuh. (*)
*Fileski Walidha Tanjung adalah seorang penulis kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis esai, puisi, dan cerpen di berbagai media nasional.