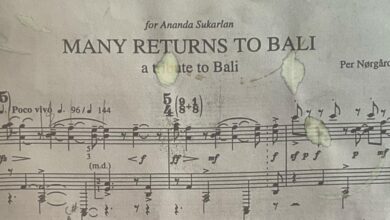ORANG BILANG, ikan sangat menyukai air, tapi air malah merebus ikan. Seperti paradoks Zen, kalimat ini menyodorkan lanskap berpikir yang mengganggu nalar sehari-hari. Ia menggugah, karena mencipta ilusi logika yang memikat, lalu menampar kita dengan kesadaran bahwa kehidupan seringkali menyembunyikan racunnya dalam tempat yang paling akrab. Namun, benarkah demikian? Apakah air betul-betul bersalah? Atau ada tangan lain yang mengatur suhu dan membiarkan sesuatu menjadi tragedi?
Simone Weil, filsuf eksistensialis asal Prancis, menulis dalam Gravity and Grace, “Kesengsaraan sejati adalah kehilangan akar.” Maka ketika kita merasa dikhianati oleh air, angin, tanah, dan cinta—barangkali yang hilang adalah kesadaran atas akar sebab. Kita terputus dari relasi kausal yang lebih dalam, dan memilih menyederhanakan kenyataan agar tampak bisa ditangani secara emosional. Air tidak merebus ikan. Air hanya taat pada panas. Yang membuatnya bergolak adalah api.
Kita hidup dalam zaman ketika banyak orang merasa menderita, tetapi tidak tahu kenapa. Kita menderita karena cinta, padahal cinta hanyalah medium: yang menyakitkan adalah ego yang mengikatnya. Ini mengingatkan pada pemikiran Rumi, “Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kamu ciptakan atau hancurkan. Ia hanya terjadi. Tapi egomu akan membuatnya jadi penjara.” Maka, ketika cinta menyakitimu, sebenarnya itu bukan cinta—melainkan keinginan untuk memiliki, dominasi atas ketidakpastian, dan ilusi tentang keabadian.
Dalam dunia yang semakin digerakkan oleh impuls digital dan kepuasan instan, kita sedang kehilangan kapasitas untuk mengolah penderitaan secara filosofis. Seperti kata Walter Benjamin, dalam The Storyteller, “Pengalaman telah menurun nilainya.”
Kita tidak lagi mengendapkan luka, kita ingin langsung menyembuhkannya—padahal, seperti halnya musim, penderitaan adalah fase yang harus dialami, bukan dielakkan. Jika angin menggugurkan daun, bukan angin yang bersalah. Ia hanya mengemban tugas musim. Maka tidak tepat menyalahkan angin, sebab daun memang harus gugur agar pohon bisa tumbuh kembali.
Paradoks ini membongkar cara kita memaknai relasi antara subjek dan dunia. Manusia hidup di atas tanah, dan suatu hari dikubur oleh tanah. Tapi tanah bukanlah antagonis; ia hanya menjadi saksi perubahan wujud. Heidegger berbicara tentang Sein-zum-Tode—keberadaan manusia selalu menuju kematian. Namun, dalam pendekatan ini, kematian bukan sekadar akhir, melainkan cara untuk memahami makna hidup. Maka, tanah bukan sekadar medium penguburan, melainkan simbol integrasi kembali pada asal. Bahwa tubuh kembali menjadi debu, dan itu bukan tragedi, melainkan siklus purba.
Masalahnya adalah manusia tak suka kompleksitas. Kita terbiasa mencari musuh dari hal-hal yang tak kita mengerti. Ketika seseorang yang kita cintai menyakiti kita, kita menyebut cinta sebagai luka. Padahal, cinta bukan entitas otonom yang bisa melukai. Yang melukai adalah ilusi tentang balasan, tentang kepastian. Sebagaimana kata Alain de Botton, “Kita terluka bukan karena realitas, melainkan karena harapan yang tak terpenuhi.”
Dalam dunia pasca-modern, relasi kita dengan realitas sering kali seperti kaca cermin yang retak. Kita melihat pantulan diri yang terdistorsi oleh trauma masa lalu, ekspektasi yang tak pernah dibicarakan, dan luka-luka yang tak sempat dijahit. Maka, sering kali kita bukan melihat sesuatu sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana luka kita ingin melihatnya. Ini adalah bentuk penderitaan terselubung, penderitaan yang dipilih, bukan yang diberikan.
Inilah kenapa Nietzsche mengatakan, “Tidak ada fakta, hanya interpretasi.” Kalimat ini bukan relativisme banal, melainkan seruan untuk menyadari bahwa persepsi kita membentuk kenyataan. Air tidak selalu merebus ikan. Dalam kondisi lain, air adalah tempat kelahiran. Angin tidak selalu menggugurkan daun—dalam musim semi, ia menjadi pembawa sari dan kehidupan. Cinta pun tidak selalu menyakitkan; ia adalah cermin terdalam untuk mengenal diri sendiri, jika kita bersedia jujur.
Namun, manusia modern lebih suka menggenggam derita daripada memahami sumbernya. Karena penderitaan memberi narasi tentang keberartian. Tanpa penderitaan, hidup terasa datar. Maka, jangan-jangan, kita pun mulai mencintai penderitaan itu sendiri, karena di dalamnya kita merasa hidup. Seperti Narcissus yang jatuh cinta pada pantulan dirinya, kita pun jatuh cinta pada versi derita kita yang paling dramatis. Kita tidak ingin sembuh, karena kita takut kehilangan identitas yang terbangun dari luka itu.
Barangkali inilah kritik yang perlu kita angkat hari ini: bahwa penderitaan bukan takdir, melainkan pilihan. Dunia memang tidak selalu adil, tetapi cara kita membaca dunia itulah yang menciptakan makna. Ketika kita belajar melihat air bukan sebagai pembunuh, tetapi sebagai elemen yang tunduk pada hukum alam, kita belajar memaafkan. Ketika kita tidak lagi menyalahkan cinta atas kegagalan relasi, kita memberi ruang bagi cinta untuk hadir dalam bentuknya yang lebih jujur.
Jean-Paul Sartre pernah berkata, “Kita dikutuk untuk bebas.” Sebuah kutukan yang ironis, karena kebebasan berarti kita harus bertanggung jawab atas cara kita menderita. Tidak bisa lagi menyalahkan air, angin, tanah, atau cinta. Kita hanya bisa bercermin, dan bertanya: apakah aku benar-benar ingin sembuh?
Lalu jika semua ini bukan soal air, bukan soal angin, bukan tanah, bukan pula cinta—melainkan soal bagaimana kita menafsirkan semuanya itu, maka pertanyaan besar pun menggantung di ujung kesadaran: berapa banyak luka yang sebenarnya kita rawat sendiri, hanya karena kita belum siap mengganti sudut pandang?
Jika kita tahu bahwa air tidak pernah bermaksud membunuh, bahwa angin tak memilih daun yang gugur, bahwa tanah hanya menyambut kembali yang pernah hidup, dan bahwa cinta tidak pernah bersekongkol dengan derita, masihkah kita akan terus menyalahkan hal-hal di luar diri kita?
Atau jangan-jangan, justru karena kita enggan mengakui bahwa luka itu berasal dari dalam, kita memilih menyusun narasi yang menyalahkan luar?
Di dunia yang penuh dengan kekacauan makna dan limpahan informasi, kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk menanyakan ulang: apakah cara kita melihat dunia hari ini membuat kita tumbuh, atau justru membuat kita semakin jauh dari diri yang utuh?
Mengapa begitu banyak orang merasa asing di rumah sendiri—dalam tubuhnya, dalam pikirannya, dalam cintanya? Apakah karena kita terus-menerus hidup dalam persepsi yang diwariskan, bukan yang dipilih dengan sadar?
Kalau benar penderitaan bisa diubah hanya dengan mengubah cara memandangnya, apakah kita berani? Berani kehilangan versi diri yang selama ini merasa paling benar hanya karena terbiasa? Berani sembuh, meski itu berarti kehilangan hak untuk menyalahkan?
Dan bila penderitaan bukan karena keadaan, melainkan karena cara kita menjelaskannya pada diri sendiri, maka pertanyaan terakhir—dan mungkin yang paling penting—adalah: apa yang sesungguhnya kamu perjuangkan—kebahagiaan, atau narasi tentang penderitaan yang membuatmu merasa penting?
Di antara angin yang bertiup dan air yang tenang, di antara daun yang gugur dan tanah yang menanti, kita semua sedang menulis makna atas dunia. Maka renungkanlah baik-baik: apakah kamu sedang hidup, atau sekadar mengulangi tafsir lama yang sudah saatnya kamu tinggalkan. (*)
BIODATA
*Fileski Walidha Tanjung adalah seorang penulis kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis esai, puisi, dan cerpen di berbagai media nasional.