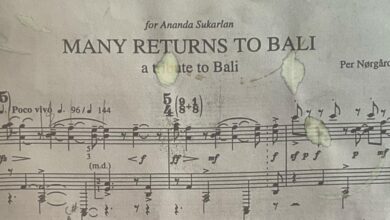“Kamu tidur dengan Pekak saja malam ini. Besok ada Nyepi?”
“Nyepi itu apa?”
“Orang tak boleh ke luar ke jalan.”
Itu percakapanku dengan anak tuan rumah kos di Jalan Hayam Wuruk, Tanjung Bungkak, Denpasar, di awal tahun 1989. Tiga puluh enam tahun silam, ketika aku diterima sebagai guide training di sebuah travel biro di dekat tempat aku indekos. Kenapa aku indekos di situ? Agar tidak memerlukan biaya transportasi lagi ke tempat kerja.
Aku memasuki pekarangan rumah besar di Jalan Raya Hayam Wuruk itu. Aku menanyakan kepada tuan rumah sekiranya menerima kos. Tuan rumah mengantar ke deret bangunan saling berhadapan dan hanya bersela jalan dan tanaman tinggi.
Ia jelaskan, kalau kamar yang ada kamar mandi di dalam, sewanya Rp25.000/bulan. Dek. Uang di saku hanya Rp80.000. Itu saja bekal dari ibuku di kampung di Jawa yang menggadaikan kartu pensiun ayahku. Ketika kutanyakan, apakah tak ada yang lebih murah? Ia menjawab, “Ada. Tetapi bekas dapur.”
Aku melangkah lebih maju, sampai di rerumputan setinggi lutut dan kulihat ada tiga ruangan kecil berjendela jeruji besi berkarat.
“Di sebelah kiri ini, tempat kami memasak. Di paling kanan itu sudah disewa sopir bemo. Di tengah masih kosong. Harganya lebih murah, Rp10.000/bulan.”
Aku sedikit lega dan langsung memutuskan untuk menyewa kamar dapur. Kamar dapur itu kecil dan di lantai tengah ada gundukan tanah; rumah semut.
Suatu pagi yang gelap sekitar pukul lima, aku memasak sayur kangkung dan mi. Ketika aku menoleh ke rerumputan di seberang, ada seorang perempuan menghadap arahku dan berjalan. Perempuan berparas cantik itu rambutnya terurai panjang. Yang agak aneh, jalannya mengambang, tak menginjak tanah. Aku alihkan pandanganku ke panci masak kangkung.
Agak ragu, kutoleh perempuan itu lagi dan mendekat sampai jarak sekitar lima meter. Ia ramah, tersenyum lagi, kemudian berbalik arah berjalan menuju lubang terbuka di tembok belakang. Aku masih memandangnya dan ternyata ia keluar melewati lubang besar tak berpintu itu.
Dalam benakku sesaat, pasti anak nakal yang pulang pagi. Tapi rasa penasaranku berhamburan. Ketika aku menuju lubang besar di belakang di antara dinding melingkar, betapa kaget, ternyata di luar lubang besar itu genangan air membundar. Tidak mungkin kalau ini orang biasa?
Kutemui ibu-ibu di kamar kos sebelah dan kutanyakan, “Apakah ada yang membuang sampah petang tadi?”
Tak seorang pun mengiyakan. Giliran kutanya, istri anak tuan rumah. Jawabnya, membuat aku tak berani tidur di kamarku sendiri.
“Biasa, itu Sang Penunggu Karang yang di tugu ingin berkenalan dengan penghuni baru.”
Kebetulan kamarku berhadapan langsung dengan tugu.
Beberapa hari berselang, aku naik bemo dari Sanur menuju Tanjung Bungkak, tempat indekosku. Tetapi sesampai di perempatan patung Kapten Japa, Renon, bemo tidak bisa berlanjut, aku turun.
Ada patung raksasa dipanggul oleh banyak anak muda dengan musik bertalu. Dengan suka cita aku bergabung di belakangnya.
Aku tak tahu, ini perayaan apa? Senang rasanya seperti pawai perayaan 17-an Agustus di Jawa.
Di dekat selokan, ada orang mengambil air dengan ember dan air itu disiramkan ke para pemanggul patung raksasa berwajah bengis. Siraman airnya terkena baju dan celanaku.
Beberapa langkah selanjutnya. Dek. Kutoleh sebelah kiri, kantor biro perjalanan, tempat aku magang. Malam itu ada pertemuan karyawan. Aku lupa ada undangan dan sudah 30 menit lewat dimulai.
Saat aku mengetuk pintu kantor, disambut oleh manager travel, “Inilah contoh karyawan yang tidak disiplin.”
Aku langsung menyelinap di antara karyawan lain yang wajahnya padam. Aku mirip tikus masuk comberan.
Kembali ke indekos, ternyata sepi. Semua orang yang kos pulang kampung. Ketika kutanyakan, anak tuan rumah, jawabnya: “Besok hari Nyepi.” Baru kali ini aku mendengar istilah Nyepi. Di kampungku di Kendal, Jawa Tengah, belum pernah mendengarnya.
Lalu lintas di Jalan Raya Hayam Wuruk mulai sepi. Aku hanya mengintip dari sela-sela teras rumah dengan anak tuan rumah.
Pekak (kakek) tak berbaju masuk kamar bersamaku. Kamar itu kecil dan gelap. Kucoba rebahan, Pekak tergeletak di lantai. Aku merasa rikuh, anak muda tidur di atas kasur, sedang orang tua di bawah dan tak berbaju juga.
“Pekak, tidur di atas?”
“Tidak bisa.”
“Kenapa, Kak?”
“Sejak aku masih bujang hingga beristri, tetap tidur di lantai.”
“Kenapa, Kak?”
“Kalau ada orang jahat mengirim benda gaib, kalau tidurnya sejajar dengan tanah, aman.”
Cerita Pekak itu bukan hal baru buatku sebenarnya. Aku juga sering mendengar kepercayaan seperti itu di Jawa.
Semalam tidur nyaman dan sesiang sampai pagi, kami lalui dengan bersahaja. Sejak itulah aku mengenal pawai ogoh-ogoh dan perayaan Nyepi sekaligus.
Ketika aku sudah bekerja sebagai pemandu wisata bahasa Jerman, aku mulai mempelajari tradisi Hindu Bali. Aku membeli beberapa buku saku stensilan di pasar malam Kreneng tentang berbagai upacara dan mitologi Hindu.
Apalagi setiap akan ada perayaan Nyepi, travel kami selalu mempunyai program nonton pawai ogoh-ogoh di Jalan Veteran, Denpasar. Tepatnya di teras Bali Hotel. Biasanya aku mengantar rombongan turis Jerman atau Swiss mulai pukul 17.00 sudah meninggalkan hotel, baik di kawasan Nusa Dua, Kuta atau Sanur.
Di perjalanan aku ceritakan dalam bahasa Jerman makna Nyepi. Warga Bali melakukan Catur Brata Penyepian. Empat pantangan harus diikuti selama sehari semalam di hari Nyepi itu. Amati Geni, tanpa ada api atau menyalakan lampu. Amati Karya, tanpa kerja. Amati Lelungan, tidak bepergian dan Amati Lelanguan tidak mengadakan rekreasi, pesta atau hiburan.
Turis-turis Eropa itu takjub dan kagum dengan tradisi Bali. Tradisi yang sudah membumi, tanpa ada aba-aba dari manapun.
Aku teringat Walter Spies, Le Mayeur, Miquel Covarrubias dan Ketut Tantri yang di zaman koloni Belanda sudah mengagumi dan tinggal di Bali. Pilihan para seniman dunia di Bali itu ternyata tak salah. Buktinya eksotika budaya dan alam Bali hingga detik ini masih digandrungi wisatawan lokal maupun internasional.
Pada pawai ogoh-ogoh itu manusia tumpah ruah menyaksikan kreasi berbagai bentuk sosok raksasa yang digotong banyak orang. Musik bertalu menyertainya.
Dalam Hinduisme dikenal ada Bhuana Agung, yaitu alam semesta atau dunia dan Bhuana Alit, yaitu diri manusia. Kedua elemen ini harus diseimbangkan.
Itu kisahkku selama tujuh tahun sebagai guide di Bali dan bersinggungan akrab dengan pawai ogoh-ogoh terbesar di jalan raya Denpasar.
Ketika aku sudah tinggal di Switzerland dan mudik ke Bali bersama istri, tak kusangka tanggal keberangkatan ke Switzerland lagi bertepatan dengan hari Nyepi. Bagaimana aku yang tinggal di Desa Batubulan harus sendiri ke bandara? Aku ingat bekas kantor travel aku bekerja dulu, Trio Bali Tours di Jalan Pandu, Hayam Wuruk.
Beruntung, aku diizinkan naik bus dari kantor, karena bus-bus dari kantor kami disewa hotel-hotel untuk mengantar dan menjemput turis di bandara Ngurah Rai. Usai pesta ogoh-ogoh kami tidur di kantor travel dan esoknya kami naik bus yang bertuliskan: khusus transfer hotel – airport – hotel.
Bus kosong dari kantor, hanya aku dan istri. Sepanjang jalan dari Denpasar ke Sanur dan bandara Ngurai Rai, sepi dan hening. Aku bisa melihat jalanan lengang. Di sudut-sudut pertigaan ada pecalang berjaga. Pada waktu itu memang karyawan hotel diizinkan bekerja dan dijemput oleh bus khusus yang sudah disiapkan.
Seorang teman yang bekerja di Hotel Hyatt, Sanur, juga harus bekerja di Hari Nyepi itu. Ia sempat bilang aku, khawatir berjalan dari rumah ke jalan raya, tempat bus menunggu. Meski dia sudah punya surat jalan, takut dengan pecalang.
Beberapa tahun silam pelaksanaan Nyepi semakin dipertegas. Bandara Ngurai Rai ditutup, tak ada pesawat yang datang maupun pergi.
Hari ini, kami di rumah Batubulan lagi. Kemarin sempat kami keliling ke beberapa Banjar Buda Ireng, Banjar Mula dan yang lain untuk melihat persiapan ogoh-ogoh beserta penabuh gamelan.
Sungguh sesuatu yang sangat mengesankan. Ada ogoh-ogoh buatan anak-anak dan siap dipanggul anak-anak. Mereka akan ikut dalam pawai resmi dengan posisi di depan ogoh-ogoh besar.
Aku sempat bertanya kepada anak-anak, mereka bersebelas akan mengangkat ogoh-ogohnya. Sampai di sini aku melihat sistem regenerasi seni, baik seni patung, musik akan berjalan mulus.
Aku bertemu dengan orang tua yang sedang berdiri di depan ogoh-ogoh yang dinobatkan menjadi juara satu di Kecamatan Sukawati, Gianyar.
Lelaki tua itu bilang, ogoh-ogohnya dibuat oleh seniman patung dan tampak hidup. Di antara ogoh-ogoh yang lain, ogoh-ogoh ini menjadi Juara 1. Hadiahya sekitar Rp.15.000.000. Bapak itu merasa terhormat, karena membawa nama banjar dan ogoh-ogohnya akan dibawa ke Gianyar. Meskipun biaya membuat ogoh-ogoh sendiri mencapai Rp75.000.000.
Pengerupukan
Sebelum pawai ogoh-ogoh ada ritual di rumah yang tak kalah menarik. Di depan rumah diletakkan aneka sesaji berupa nasi putih yang terpisah di atas daun kelapa.
Aku diajak memegang panci sambil dipukul-pukul, sementara istriku memegang daun kelapa kering yang dibakar. Teman lain membawa sesaji dan membawa gebukan, dipukul-pukulkan ke tanah.
Asap mengepul dari daun kelapa kering dan suara gaduh timbul. Tujuannya, supaya ruh jahat menyingkir dan tidak berada di rumah.
Ritual yang disebut Pengerupukan ini sungguh menarik.
Tiba-tiba aku teringat pesan ibuku di Jawa, ketika menjelang ujian negara di kampus, aku disuruh ibuku mengelilingi gedung aula tiga kali.
Pun ritual Pengerupukan ini juga kami semua mengelilingi rumah sampai tiga kali.
Pawai Ogoh-Ogoh
Menjelang pukul 18.00 jalanan Batuyang, Batubulan sudah mulai langka motor lewat dan diganti warga berdatangan. Tua muda, anak, kakek, nenek ikut berjalan.
Ogoh-ogoh sudah berjejer di tepi jalan dekat jembatan. Remang tiba, gamelan membahana dan pawai ogoh-ogoh dimulai.
Barisan pertama nama banjar berupa tulisan di kain dibawa gadis berseragam hitam. Disusul gamelan dan ogoh-ogohnya.
Ketika dua ogoh-ogoh besar saling berhadap-hadapan, tampak seperti hidup. Apalagi ogoh-ogoh yang warna merah, ternyata di kegelapan menyala. Narasi dari pengeras suara semakin membuat mencekam.
Memori lamaku tentang ogoh-ogoh dengan turis-turis Jerman dan Swiss bermunculan. Kini aku bukan sebagai pemandu, sebagai warga yang menikmati suasana.
Sebelum ogoh-ogoh selesai pawai, ada grup bocah yang mengangkat ogoh-ogoh bilang ibunya di sebelahnya, “Berat, Capek!”
Dari rangkaian peringatan Nyepi itu, terbersit di pikiranku, mirip dengan puasa bagi umat Muslim di bulan Ramadhan.
Apalagi tahun 2025 ini Nyepi jatuh pada hari Sabtu, 29 Maret, di akhir bulan Ramadhan. Umat Muslim menjalankan puasa sebulan penuh dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam lima rukun Islam. Pertama, membaca dua kalimat syahadat. Kedua, menjalankan salat. Ketiga, menjalankan puasa. Keempat, memberikan zakat. Kelima, menunaikan ibadah haji.
Pada saat Nyepi, umat Hindu sehari semalam hening di rumah masing-masing untuk membersihkan diri. Ritme hidup yang setahun penuh perlu jeda sejenak. Ketenangan mencari harmoni.
Umat Muslim melakukan puasa sebulan penuh dengan harapan membersihkan diri, tanpa bicara kotor, rasan-rasan, atau ngerumpi. Bahkan, ruh-ruh halus diikat tali, tak boleh mengganggu manusia selama sebulan itu.
Ada saudara perempuanku di Jawa yang berani tidur di rumah yang cukup angker di pinggir kali. Ketika kutanya, “Hebat, kamu berani tidur seminggu di rumah yang banyak orang anggap angker?”
Saudara perempuanku itu menjawab, “Ya, berani. Kan di bulan Ramadhan ruh-ruh halus tak boleh mengganggu manusia.”
Lepas dari ritual spiritual di atas, aku teringat program Car Free Day pemerintah Kota Roma, Italia. Waktu itu aku dengar pertama kali di Roma ada larangan dari pemerintah kota, supaya mobil dan motor tidak masuk kota.
Sehari saja, biar kota itu istirahat. Kota dan penghuninya lelah. Kampanye yang kudengar dari Roma itu, kini telah menjadi trend Car Free Day kota-kota di dunia, termasuk di Indonesia. Warga kota harus menghirup udara bersih. Hidup bebas dari polusi menjadi impian masa depan.
Beberapa kota seperti di Jakarta dan di Lombok sudah rutin mengadakan acara ini. Tentu banyak manfaatnya, selain untuk memperlambat laju globalisasi materi, mengurangi polusi, juga membuat renungan hidup baru.
Car Free Day yang berkali-kali kukunjungi di Jalan Udayana, Lombok, menjadi potret wajah kita hari ini. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mulai berkembang mengenalkan produknya.
Di Switzerland mulai tumbuh kelompok-kelompok pengontel sepeda yang rutin mempromosikan pentingnya hidup sehat. Mereka meminta jalur sepeda lebih diperhatikan di kota-kota.
Jauh sebelum Roma mencanangkan kotanya sunyi senyap, di Bali sudah lama menjalankan Nyepi.***
BIODATA
Sigit Susanto lahir di Kendal, 21 Juni 1963. Karya-karyanya antara lain Sosialisme di Kuba (2004), Pegadaian (novel; 2004), Menyusuri Lorong-Lorong Dunia 1 (2005), Menyusuri Lorong-Lorong Dunia II (2008), Menyusuri Lorong-Lorong Dunia III (2012), Kesetrum Cinta (2016), Jejak-Jejak yang Tertinggal (puisi, 2023), Si Bolang dari Baon (novel, 2024). Ia juga menerjemahkan beberapa karya sastra dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, seperti: Proses karya Franz Kafka (2016), Surat untuk Ayah karya Franz Kafka (2016), Metamorfosis karya Franz Kafka (2018), Percakapan dengan Kafka karya Gustav Janouch (2018), Novelet Catur karya Stefan Zweig dalam proses penerbitan.