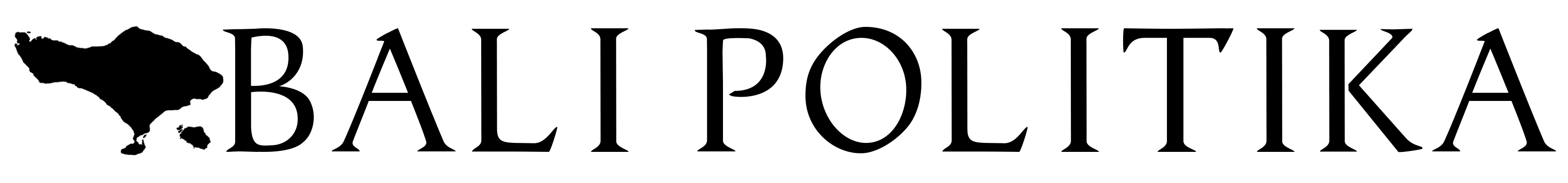DESA ADAT merupakan salah satu bentuk badan persekutuan hukum yang awalnya dikenal dengan persekutuan hukum adat (Adatrechtsgemeenschappen) dan yang secara hitoris direferensi dari cerita dalam lontar Markandya Purana.
Desa Adat awalnya juga disebut dengan desa tradisional, yaitu sebagai persekutuan yang tumbuh, hidup, berkembang dari masyarakatnya sendiri sehingga oleh Korn dan Liefrinck menyebut sebagai desa otonom karena mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, seperti memiliki pemerintahan sendiri yang dilandasi oleh hukum yang tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakatnya, memiliki wilayah serta harta kekayaan yang bersifat materiil dan immaterial. Oleh karena itu disebut bersifat “Otonom dan Otohton”.
Setelah kemerdekaan merupakan bagian dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini diperlukan pendekatan “koeksistensi” dalam sistem hukum dengan mengingat desa adat di Bali sebagai badan persekutuan hukum masih utuh dibandingkan dengan di daerah lainnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dualitas dalam sistem pemerintahan desa di Bali mengindikasikan bahwa selain dikenal ada “Pemerintahan Desa Dinas”, juga dikenal adanya “Pemerintahan Desa Adat” dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam konsep koeksistensi sehingga tidak perlu dipertentangkan, tapi perlu dipilah dalam memahami dan memerhatikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga tidak kontra produktif dengan sifatnya yang otonom dan otohton dengan mengingat keberadaannya yang sangat strategis dan riskan untuk diintervensi dan dikooptasi terutama oleh kekuasaan dan partai politik.
Oleh karena itu “Etikad Baik” dan “Etika Politik” merupakan ujian terberat bagi desa adat, pemegang kekuasaan dan politisi di Bali dalam menjaga keberadaan desa adat yang rentan dapat merusak sifat otonom dan otohtonnya karena ada pengutamaan kepentingan kekuasaan dan kepentingan partai politik yang selalu haus akan kekuasaan dengan mengalalkan berbagai cara dibandingkan menjaga marwah desa adat dalam mencapai “kasukertan desa” sekala dan niskala.
Desa adat yang keberadaannya sangat strategis akan selalu menghadapi dan berhadapan dengan tantangan dan sekaligus peluang yang dapat menjadi masalah atau berkah, sehingga diperlukan kemampuan, keberanian dan strategi untuk menyikapainya.
Selain itu secara pasti akan menghadapi kompleksitas permasalahan ketika prajuru adat sebagai pelaksana pemerintahan desa adat yang diberikan kewenangan melaksanakan otonominya dan menjaga kultur krama desanya belum mampu mengelolanya secara patut sesuai perkembangan.
Oleh karena itu diperlukan kemampuan dan profesionalitas tinggi serta kualitas dalam memilah dan memilih menu yang ada dan ditawarkan oleh pihak out sider dalam sistem interaktif sebagai bagian dari tata kelola desa adat.
Masalah demi msalah dihadapi oleh prajuru adat dan krama desa dalam hidup dan kehidupannya untuk mencapai “kasukertan” dalam komunitasnya di lingkungan banjar atau desa yang diatur dalam awig-awig sebagai aturan yang mampu menetralisasi perbedaan kepentingan individu sebagai krama banjar/desa.
Salah satu fenomena yang selalu dihadapi krama desa adat baik sebagai individu maupun sebagai prajuru adat, yaitu tekanan, intervensi, dan kooptasi dari kekuasaan dan kekuatan partai menjelang dan pada saat “pemilu”.
Hak politik sebagai salah satu kebebasan invividu dan merupakan salah satu hak asasi yang paling mendasar sebagai warganegara hanya tinggal wacana karena fenomena demi fenomena yang menunjukkan adanya intervensi dan intimidasi sepertinya terbiarkan bahkan terpelihara secara terstruktur melalui kepala adat di banjar atau desa adat oleh pucuk pimpinan dalam pemerintahan desa adat.
Bahkan di beberapa desa adat teramati, bahwa jabatan bendesa dijadikan batu loncatan dan sekaligus kendaraan untuk memperoleh kekuasaan sebagai anggota legislatif atau eksekutif.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepertinya menganggap sebagai sebuah kewajaran dan fungsi kelembagaan hanya sebagai pelengkap dalam pelaksanaan pemilu.
Beberapa contoh kasus mungkin relevan diungkap kembali sebagai pengingat dan bahan hukum dan dasar analisis, seperti intimidasi seorang Pemangku Pura Melanting di Kabupaten Tabanan sekitar bulan Nopember 2024, kemudian di bulan Desember 2024 seorang krama desa adat di salah satu Banjar di Kabupaten Tabanan tidak mendapat pelayanan (penyanggran banjar) secara patut pada saat melaksanakan upacara penguburan istri saat meninggal dunia karena berbeda pilihan politik pada saat pilkada.
Apakah kondisi yang tidak sehat dan miris ini akan terbiarkan atau dipelihara demi untuk mempertahankan status quo sebuah kekuasaan?
Fenomena yang pada dasarnya sebagai soal ujian tampak tidak mampu dipahami dan dikerjakan dengan baik oleh para politisi dan penguasa (legislatif dan eksekutif) untuk sebuah “keteladanan” dalam mencapai kekuasaan saat pemilu dan ujian bagi para kepala adat secara melembaga dalam menjaga netralitas.
Ujian lainnya juga berlaku bagi kultur hukum krama banjar atau desa dalam mendasarkan pilihannya kepada calon yang berkualitas dan kuktur dari para strukur hukum yang mampu menghargai perbedaan pilihan politik dari krama banjar atau desanya.
Memperhatikan dua contoh kasus intimidasi dan kooptasi terhadap lembaga banjar yang berimplikasi adanya sanksi adat dengan cara sesat pikir karena tidak dadasarkan pada tiga asas kerja dalam hukum adat, yaitu laras, rukun, dan patut, tetapi didasarkan pada “kebencian” sebagai akibat perbedaan pilihan politik, sementara oleh hukum negara penempatan asas LUBER dan JURDIL dalam pemilu menjadi keniscayaan. Oleh karena itu menjadi relevan dicermati dari perspektif sistem hukum.
Peraturan perundang-undangan di bidang pemilu secara limitatif menegasi adanya jaminan atas adanya perbedaan pilihan sebagai bagian dari hak yang paling azasi, demikian pula awig-awig tidak pernah mengintervensi hak politik krama desanya, di mana perbedaan justru menjadi salah satu identitas dari adat dan hukum adat, bahkan awig-awig sebagai hukum adat merupakan refleksi hukumnya Pancasila yang menegasi adanya kewajiban dalam pemeliharaan terhadap kahyangan desa, pengakuan yang sama terhadap martabat manusia sebagai krama, menjaga kekompakan dan kesatuan sebagai pengikat krama, terpeliharanya musyawarah melalui paruman sebagai lembaga pemutus, adanya lembaga pesuka-dukaan yang merefleksikan kehadiran pemerintahan desa adat untuk mewujudkan keadilan sosial.
Dengan demikian dari perspektif legal subtance (UU dan aturan organiknya, serta awig-awig) telah memberikan jaminan dalam pelaksanaan hak setiap krama desa.
Namun, ditemukan fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam perilaku hukum senyatanya dari para struktur hukum (legal structure) dan kultur hukum (legal culture) krama desa dalam penyikapan.
Artinya adanya penyikapan yang menyesatkan dari struktur hukum terhadap isi norma hukum yang ada, yaitu yang mengutamakan “kepentingan dan ambisi” akan kekuasaan dengan mengabaikan etika dan moral politik.
Ambisi privat ini dicopy paste oleh kepala adat (prajuru) secara melembaga dan oleh krama desa secara tidak langsung digunakan sebagai pedoman hidupnya dalam menyikapi kontestasi di pemilukada seolah moment sosialisasi oleh calon merupakan hasil paruman yang bersifat mengikat dalam arti jika ada krama desa ditengarai memiliki pilihan berbeda adalah bentuk penyimpangan hasil paruman sehingga layak diberi “sanksi”.
Dalam kondisi inilah dapat diamati adanya intimidasi dan sekaligus kooptasi oleh kekuasaan terhadap kelembagaan adat dan hukum adat yang secara hakiki dapat merusak sifat otonom dan otohton desa adat.
Kepentingan akan kekuasaan dengan intimidasi dan kooptasi dapat dibilang menyesatkan, ditambah dengan cara penyikapan oleh kepala adat sebagai prajuru yang menyesatkan pula menjadikan bahwa kelembagaan adat dan hukum adat keliru menyikapi menjadikan krama desa sendiri sebagai korban kebencian.
Kondisi ini jika terbiarkan, maka lembaga adat seperti banjar dan desa adat di masa depan akan menjadi korban dan korban lagi sebagai akibat keluar dari tugasnya dalam mencapai “kasukertan” desa sekala dan niskala.
Oleh karena itu, diperlukan perbaikan struktur hukum dari atas baik aspek etika, moral dan hukum dengan mereferensi pernyataan Sahetapy yang menyatakan bahwa: “bau busuk ikan datangnya dari kepalanya ikan dan bukan dari ekornya”, sehingga sangat diperlukan “keteladan” yang harus dimulai dari seorang “pemimpin” yang berkualitas.
Selain itu diperlukan penciptaan kultur hukum bagi krama desa yang tidak melakukan peradilan di luar kepatutan dan paruman; artinya krama desa tidak dengan caranya sendiri memberi sanksi seperti tidak mendapat “penyanggran” banjar menurut rasa politiknya secara individual tanpa dilandasi suatu kesalahan sebagai bentuk perbuatan yang disebut “iwang”.
Untuk itu diperlukan pemimpin dan calon pemimpin yang sejak awal mau dan mampu memberikan pendidikan politik yang patut untuk menemukan kebenaran melalui koherensi antara pemikiran, konsep, nilai, norma, dan yang koresponden dengan perilakunya untuk tujuan sebuah kemanfaatan bagi keadilan dan kepastian agar kehidupan krama desa dalam wadah desa adat dapat berjalan sesuai dengan tugas desa adat, yaitu: mencapai “kasukertan” desa sekala dan niskala untuk mengubah “kebencian” menjadi “keguyuban”. Astungkara dapat diperjuangkan. (bp/*)