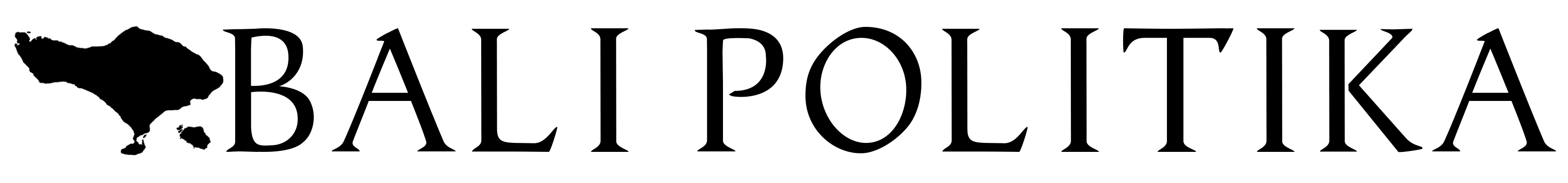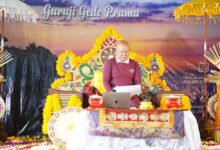SAAT INI, penyuluh pertanian adalah salah satu profesi yang tetap dapat berjalan meski tanpa anggaran besar.
Mereka tidak bergantung pada besarnya dana, berbeda dengan banyak pemerintah daerah yang kesulitan memenuhi janji-janji politik akibat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari realitas politik Indonesia.
Dalam sistem demokrasi yang kita anut, para pejabat negara adalah produk dari proses pemilu, yang sayangnya justru menjerat mereka pada jebakan janji politik, bukannya memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Pejabat negara di Indonesia umumnya hanya diizinkan untuk memimpin selama dua periode.
Saat memasuki periode kedua, terjadi perubahan sikap yang begitu kentara.
Pada periode pertama, mereka mungkin terlihat mencoba menjalankan tugas dengan baik, setidaknya untuk menciptakan kesan bahwa mereka layak dipilih kembali.
Namun, di periode kedua, segala berubah; alih-alih berfokus pada kebijakan strategis jangka panjang, mereka justru sibuk menjaga kepentingan partai dan kelompok politik yang mendukung mereka.
Di periode kedua, biasanya para pejabat ini cenderung melakukan manuver untuk memperkuat posisi politik pasca-jabatannya.
Mereka menggelontorkan dana hibah dan bantuan sosial yang tampaknya populis, sementara di balik layar, pembangunan berskala besar dilakukan dengan mengabaikan keseimbangan neraca keuangan.
Sungguh ironis, pembangunan yang seharusnya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat justru kerap kali menimbulkan masalah baru.
Alih-alih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), malah memperbesar defisit APBD.
Sejak kita memilih untuk menjalankan demokrasi ala Barat, kita menjalankan pemilu dengan prinsip “satu orang, satu suara.”
Dalam demokrasi populer ini, siapapun bisa terpilih selama dia memiliki cukup dukungan.
Seorang calon yang mungkin tidak terpelajar dan tidak memahami prinsip-prinsip pemerintahan bisa saja menjadi pemimpin hanya karena punya banyak teman dan dukungan.
Bandingkan dengan negara-negara yang lebih matang demokrasinya. Di beberapa negara Barat, seperti Amerika Serikat, suara rakyat diatur melalui sistem elektoral yang memperhitungkan banyak hal, termasuk bobot suara.
Profesor yang menguasai isu-isu strategis memiliki bobot suara lebih besar dibandingkan penyuluh, yang mungkin kurang memahami kebijakan pemerintahan.
Sistem pembobotan suara ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas pemimpin yang dihasilkan, bukan hanya berdasarkan popularitas semata.
Tetapi, kita di Indonesia, entah kenapa, memilih meniru demokrasi Barat setengah-setengah, menerapkan popular vote, yang justru membuka jalan bagi populisme dan pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan politik sempit ketimbang kepentingan rakyat banyak.
Jika kita kembali kepada cita-cita awal bangsa ini, demokrasi kita harusnya berlandaskan pada Pancasila, terutama sila keempat, yang menekankan pada “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila sebenarnya menuntut proses yang lebih inklusif, mempertimbangkan kualitas dan kapasitas para pemimpin kita.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan sistem pemilihan langsung yang kita anut saat ini, kriteria “kebijaksanaan” sering kali diabaikan.
Alih-alih memilih pemimpin berdasarkan kapasitasnya untuk memimpin dengan bijaksana, kita justru mengedepankan popularitas.
Seorang yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola negara, apalagi soal isu strategis seperti ketahanan pangan, bisa dengan mudah memenangkan pemilu.
Hasilnya? Kebijakan strategis seperti pangan dan pertanian dibiarkan begitu saja, tanpa perhatian yang serius. Pertanian seakan menjadi sektor yang berjalan sendiri, autopilot, tanpa arahan dan kebijakan yang jelas dari pemerintah.
Salah satu sektor yang paling menderita akibat buruknya kualitas kepemimpinan kita adalah pertanian.
Padahal, sektor pangan dan pertanian adalah sektor strategis yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional.
Tanpa ketersediaan pangan yang cukup, stabil, dan terjangkau, kita tidak hanya berbicara tentang kelaparan, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik negara.
Namun kenyataannya, banyak pejabat di pemerintahan yang justru memandang sektor ini sebelah mata.
Ketahanan pangan bukan menjadi prioritas utama. Padahal, Indonesia adalah negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, yang artinya kebutuhan pangan kita sangat besar.
Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, seperti krisis iklim, pandemi, dan perang yang mempengaruhi rantai pasokan pangan, kebijakan pangan yang solid seharusnya menjadi fondasi utama bagi pemerintahan yang cerdas.
Di lapangan, kita melihat bagaimana sektor pertanian justru berjalan dengan modal semangat dan kerja keras para petani dan penyuluh.
Para penyuluh pertanian sering kali harus bekerja dengan anggaran minim, atau bahkan tanpa anggaran sama sekali.
Mereka adalah pejuang yang berusaha membantu petani untuk meningkatkan produksi di tengah keterbatasan yang ada. Namun, apakah mereka mendapat apresiasi yang layak? Tentu tidak.
Di banyak daerah, para penyuluh pertanian bahkan harus bekerja tanpa mendapat honor yang memadai, sementara para pejabat daerah sibuk mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang tidak jelas manfaatnya.
Defisit APBD menjadi alasan yang sering dilontarkan, padahal jika dilihat lebih dalam, masalahnya bukan pada kurangnya anggaran, tetapi pada salah urus anggaran itu sendiri.
Mengapa defisit APBD sering terjadi? Jawabannya sederhana: janji politik.
Setiap kali ada pemilu, para calon kepala daerah berlomba-lomba membuat janji-janji populis yang pada akhirnya sulit untuk ditepati tanpa merusak neraca keuangan daerah.
Salah satu contoh yang paling mencolok adalah besarnya alokasi dana hibah dan bantuan sosial, yang meskipun penting, sering kali lebih bersifat politis ketimbang solutif.
Dana hibah dan bantuan sosial ini biasanya digelontorkan dalam jumlah besar menjelang pemilu atau di tahun-tahun akhir masa jabatan.
Pada akhirnya, kebijakan ini lebih dimaksudkan untuk menjaga dukungan politik daripada benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Padahal, anggaran tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Melihat kondisi ini, kita harus jujur mengakui bahwa demokrasi yang kita jalankan saat ini tidak benar-benar bekerja sesuai dengan cita-cita awalnya.
Demokrasi yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi rakyat justru sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek.
Para pemimpin yang terpilih melalui sistem popular vote lebih sibuk memperkuat posisi politiknya ketimbang bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.
Di tengah semua ini, sektor pertanian, yang merupakan sektor strategis bagi keberlangsungan bangsa, justru menjadi korban utama.
Para petani dan penyuluh yang berjuang untuk menyediakan pangan bagi bangsa ini dibiarkan bertahan sendiri, tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah.
Jika kita ingin keluar dari situasi ini, kita perlu melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem demokrasi kita.
Demokrasi Pancasila yang sejati harus dikembalikan, dengan menempatkan kebijaksanaan sebagai landasan utama dalam memilih pemimpin, bukan semata-mata popularitas.
Pertanyaan besar bagi kita adalah: apakah kita siap untuk berubah? Atau kita akan terus terjebak dalam siklus politik yang membingungkan ini, di mana janji-janji populis lebih dihargai daripada kebijakan strategis yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat? (bp/***)